hubungan antara ulama dan umara
Halaman 1 dari 1 • Share
 hubungan antara ulama dan umara
hubungan antara ulama dan umara
Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan sebuah
keputusan dalam kaitan hari libur Idul Fithri sebagai hari
libur nasional. Dan itu terlansir dalam sebuah Keputusan
Presiden dan diperkuat Keputusan Menteri Agama.
Hal itu jelas memperlihatkan keterkaitan Pemerintah dengan
urusan keagamaan (pelaksanaan ajaran agama). Lebih lanjut
kita melihat hal seperti itu dalam masalah perkawinan dan
peradilan khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa
urusan kekeluargaan di kalangan kaum muslimin bangsa
Indonesia. Maka dalam rangka urusan tersebut kita dapat
memahami kehadiran Undang-undang Perkawinan dan
Undang-undang Peradilan Agama (yang belum lama ini sudah
diundangkan). Dalam kaitan masalah-masalah tersebut di atas
terkait permasalahan wali al-amr.
Kata "wali al-amr" (dalam sebutan Indonesia) berasal dari
"waliy-u 'l-amr" (bahasa Arab). Kata ini biasa diartikan
"penguasa." Kedua bagian kata majemuk ini sudah lazim
dipakai dalam bahasa Indonesia; yaitu kata "amr" biasa
dibunyikan "amar" yang berarti: perintah atau suruhan
(misalnya: dengan amar raja diartikan: atas perintah raja).
Mengamarkan: memerintahkan, menyuruh melakukan. Kalau
ditambah dengan akhiran "an" maka menjadi "amaran" yang
berarti: perintah, suruhan, tugas (yang harus dilakukan).
Tetapi dalam kata asalnya, ia mempunyai arti yang lebih
luas, selain berarti: order, komando, otoritas, power, juga
berarti: urusan, persoalan atau perkara, masalah penting.
Dari akar kata "amr" ini, timbul bentuk-bentuk kata "amir,"
"amiral" (admiral), "amiralay (brigadier general), amirul
mu'minin (khalifah), "imarah" (sifat keamiran, atau
markasnya, atau wilayahnya).
Adapun kata "wali" juga sudah lazim dipakai dalam bahasa
Indonesia, yang berarti: orang yang menurut hukum diserahi
kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu
belum dewasa; pengasuh pengantin perempuan ketika nikah
yaitu keluarga dekatnya yang melakukan janji atau akad nikah
dengan pengantin laki-laki (dalam urusan nikah ini dikenal
juga adanya wali hakim yaitu pejabat urusan agama yang
bertindak sebagai wali); wali Allah atau waliullah, yaitu
orang suci dan keramat (seperti Wali Songo); kepala
pemerintahan (seperti wali kota, wali negara). Dalam bahasa
asalnya, kata ini berarti juga: penolong, pelindung, teman
atau sahabat, pemilik atau penguasa sesuatu barang,
pemelihara, petugas. Dari akar kata ini berkembang
bentuk-bentuk kata: wala yang berarti: cinta, persahabatan,
loyalitas, kekeluargaan; kata "wilayah" yang berarti
kekuasaan, kewenangan, daerah yurisdiksi. Itulah pembahasan
sepintas dari segi etimologis dan lexicologis, tentang
kata-kata "wali" dan "amr."
Maka kata "waliy-u 'l-amr" dengan pengertian "penguasa" atau
"pemerintah," cukup beralasan dilihat dari segi pemakaian
bahasa. Sesudah itu, ingin kita melihat kaitan pengertian
kata ini dengan persoalan hukum dalam rangka kajian fiqh.
Dalam persoalan ini tentunya pada tingkat pertama kita
berupaya mencari pokok persoalannya dalam al-Qur'an. Maka
disana kita akan menemukan pemakaian kata "uli 'l-amr" (yang
artinya dengan "waliy-u 'l-amr"), pada dua tempat, yaitu
pada ayat 59 surah an-Nisa, dan pada ayat 83 dari surah yang
sama. [1] Yang pertama berbunyi (terjemahnya): Hai
orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
rasulNya dan "ulil amri" dari kalian...). Dan yang kedua
berbunyi (Terjemahnya): Apabila mereka ditimpa sesuatu
peristiwa keamanan atau ketakutan, lalu mereka
menyiarkannya. Seandainya mereka mengembalikan persoalan itu
kepada Rasul dan kepada "uli 'l-amri" dari mereka, niscaya
orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui hal itu
...). Mufassir kenamaan yakni Imam 'Imaduddin Ibn Katsir
menukilkan keterangan Ibn 'Abbas (Sahabat Nabi) r.a. "yakni
ahl-u 'l fiqh-i wa 'l-din" (yang dimaksud dengan uli 'l-amr
yaitu ahli dalam masalah-masalah agama). Sama dengan itu,
pendapat Mujahid, 'Atha, Al Hasan Al Bashri dan Abul 'Aliyah
(semuanya ulama Tabi'in) yakni al-'ulama" (yang dimaksud
dengan uli 'l-amr adalah ulama). Ibn Katsir melanjutkan
keterangannya bahwa yang jelas (wa 'l-Lah-u a'lam), kata ini
pengertian umumnya mencakup para amir (umara) ulama.
Pengertian ini diperkuat oleh ayat 63 surah al-Maidah dan
ayat 43 surah an-Nahl; [2] ditambah dengan penjelasan hadits
shahih yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. dari sabda
Rasulullah s.a.w.: Barangsiapa mendurhakai aku berarti dia
sudah taat kepada Allah dan barangsiapa mendurhakai amir
yang saya angkat berarti dia telah mendurhakai aku. [3] Maka
semua penjelasan ini merupakan perintah untuk mentaati para
ulama dan umara. Beberapa hadits lainnya dari berbagai
sumber berita dari sejumlah sahabat Nabi telah dipaparkan
oleh Ibn Katsir, yang semuanya mengacu kepada keharusan
mentaati amir-amir (para petugas atau penguasa yang diangkat
Nabi dalam berbagai urusan yang ditempatkan di berbagai
daerah (yang telah dibebaskan ketika itu). (Lihat h.517 Juz
I Tafsir Ibn Katsir).
Ahli fiqh kenamaan yakni Imam Abul Hasan 'Ali al-Mawardi
ketika mengulas jenis-jenis kewenangan yang disebut "imarah"
yang pejabatnya disebut "amir" beliau mensitir juga ayat 59
surah an-Nisa tersebut di atas, lalu beliau menjelaskan
bahwa didalam pengertian "uli- 'l-amr" ada dua pendapat.
Pertama, bahwa yang dimaksud dengan kata itu, ialah
amir-amir, dan ini pendapat Ibn Abbas r.a. Pendapat kedua,
bahwa yang dimaksud dengan kata ini ialah para ulama.
Demikian pendapat Jabir, al-Hasan dan 'Atha. Bahkan Imam
al-Mawardi ini ketika membahas masalah Imamah atau
Kekhalifahan (Bab Pertama dari bukunya yang berjudul
al-Ahkam al-Shulthaniyah), beliau juga berpatokan dari ayat
59 (surah an-Nisa) tersebut. Dari ulasan beliau dapat
ditarik pengertian bahwa didalam kata "uli 'l-amr" termasuk
penguasa atau pemimpin tertinggi pemerintahan sampai kepada
pejabat-pejabat yang berwenang di daerah-daerah, atau dalam
urusan-urusan yang diserahkan pengelolanya kepada mereka.
Mereka itu disebut "wulat" (mufradnya wali sebagai singkatan
dari waliy-u 'l-amr) dan umara (tunggalnya amir) yaitu
penguasa yang diberi kewenangan dalam satu urusan tertentu,
atau suatu daerah kekuasaan tertentu.
Teori Wilayah (Kekuasaan atau Kewenangan)
Di dalam Fiqh (Ilmu Hukum Islam) ditemukan adanya dua jenis
kekuasaan (wilayah) yang dikaitkan dengan sumbernya, dan dua
jenis lagi yang dikaitkan dengan jangkauan kewenangannya.
Yang dikaitkan dengan sumbernya atau pangkal timbulnya
kekuasaan itu, ialah pertama: sumber kekuasaan yang sifatnya
natural-kultural, yang timbul dari suatu keadaan yang
menyangkut kepentingan dirinya, dimana yang bersangkutan
tidak atau belum cakap dan mampu melakukan tindakan hukum
yang berkaitan dengan hak-hak dan atau kewajibannya (faqid-u
'l-ahliyah atau naqish-u 'l-ahliyah). Disini berperan orang
lain menggantikan melakukan tindakan hukum, maka timbullah
apa yang misalnya disebut "vaderlijke-macht" (kekuasaan
ayah) yang sifatnya natural, yang berkembang menjadi
kultural. Yang kedua: sumber kekuasaan yang sifatnya sosial
atau konstitusional, yang timbul dari suatu keadaan yang
menyangkut kepentingan umum, utamanya untuk memberikan
perlindungan bagi kepentingan masyarakat, supaya terjamin
kebebasannya, keamanannya, dan ketertibannya, dalam
memperoleh hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya.
Maka timbullah apa yang misalnya disebut rechtsmacht
(kekuasaan mengadili), beheersmacht (kekuasaan mengelola),
regeringsmacht (kekuasaan memerintah) dan seterusnya yang
semuanya itu sifatnya sosial yang berkembang menjadi
konstitusional.
Kekuasaan jenis pertama (menurut fiqh) ada dua macam, yaitu:
wilayah (perwalian), wishayah (pengampunan atau kuratel).
Perwalian ini merupakan hak alamiah (natural) dari orang tua
dan keluarga dekat, dan dalam keadaan tertentu dapat
melompat kepada uli 'l-amr (pemegang kekuasaan sosial atau
konstitusional) seperti wali hakim dalam masalah pernikahan
yang wali nasabnya berlaku 'adhal (menolak untuk menjadi
wali dalam perkawinan yang dibenarkan menurut hukum dan
wajar dilangsungkan). Perwalian tersebut menyangkut diri dan
harta benda mereka yang belum cakap melakukan tindakan
hukum, seperti anak-anak yang belum dewasa (akil baligh).
Dan perwalian tersebut meliputi kekuasaan (kewenangan)
pemeliharaan, termasuk penyusuan (radha'ah), perawatan
(hadhanah), pemberian nafkah, pendidikan, pemberian izin
kawin. Pemegang kekuasaan perwalian atau mereka yang disebut
wali, tidak termasuk dalam pengertian uli 'l-amr atau
waliy-u 'l-amr (wali al-amr). Mereka itu termasuk dalam
kelompok pemegang wilayah khasshah, yang kedudukannya dalam
mengurus dan mengelola diri dan harta benda orang-orang yang
berada dalam perwaliannya, kekuasaannya lebih kuat dari
kelompok pemegang wilayah 'ammah (uli al-amr). Kewenangan
wali tersebut diatas hanya menyangkut hal-hal yang bersifat
perdata, sedang kewenangan waliy-u 'l-amr menyangkut hal-hal
yang bersifat kemaslahatan umum (algemeeneblang) dalam ruang
lingkup hukum publik (al-ahkam al-shulthaniyah).
Teori Fiqh dalam Kekuasaan Waliy-u 'l-amr
Al-ahkam al-sulthaniyah (hukum publik) dan
kewenangan-kewenangan yang bersangkutan dengan itu yang
ditata dalam hukum Islam (al-wilayat al-diniyah), dalam
suatu pembahasan yang luas oleh Imam Al Mawardi, telah
dirinci dalam 20 macam kewenangan. Yaitu, pertama, al-Imamah
(al-Khilafah); kedua, al-Wizarah (Kementrian); ketiga,
al-Imarah 'ala 'l-bilad (Pemerintahan Daerah); keempat,
al-Imarah 'ala 'l-Jihad (Kekuasaan Pertahanan atau
Keamanan); kelima, al-Wilayah 'ala 'l-hurubi 'l-mashalih
(Kekuasaan Penertiban Masyarakat); keenam, Wilayat-u
'l-Qadha (Kekuasaan Kehakiman); ketujuh, Wilayat-u
'l-Mazhalim (ada kemiripan dengan Kekuasaan Kepolisian);
kedelapan, Wilayat-un Naqabah 'ala dzaw-i 'l-ansab
(Kekuasaan Pengawasan atau Pencatatan cipil); kesembilan,
al-Wilayat 'ala Imamat-i 'l-Masajid (Kekuasaan pengangkatan
Imam-Imam dan penataan pimpinan masjid-masjid); kesepuluh,
al-Wilayah 'ala 'l-Hajj (Kekuasaan penyelenggaraan ibadah
haji); kesebelas, Wilayat-u 'l-Shadaqat (Kekuasaan
pelaksanaan Zakat); kedua belas, Fi Qasm-i 'l-Fa'i wa
'l-Ghanimah (Kekuasaan pengaturan dan pengurusan harta
rampasan); ketiga belas, Fi wadh-'i 'l-jizyah wa 'l-kharaj
(Kekuasaan penetapan dan pemungutan pajak-pajak); keempat
belas, Fi ma takhtalif ahkamuh-u min al-bilad (Penetapan
status tanah); kelima belas, Fi Ihya al-mawat wa 'l-stikhraj
al-miyah (Kekuasaan pengelolaan tanah dan penggunaan sumber
air); keenam belas, Fil hima wa 'l-arfaq (Kekuasaan
penetapan tanah atau hutan lindung); ketujuh belas, Fi Ahkam
al-Iqtha' (Hukum Pertanahan); kedelapan belas, Fi Wadh-'i
'I-Diwan (Kekuasaan pengaturan Tata Usaha Pemerintahan);
kesembilan belas, Fi Ahkam al-Jaraim (Pengaturan Hukum
Pidana), dan kedua puluh, Fi Ahkam al-Hisbah (ada kemiripan
dengan Kekuasaan Kejaksaan).
Berbagai macam kekuasaan dan kewenangan yang diuraikan dalam
rincian tersebut di atas, maka kekuasaan yang pertama
dibahas yaitu Imamah atau Khalifah merupakan kekuasaan yang
tertinggi dan merupakan juga sumber segala kewenangan yang
bermacam-macam yang disebutkan sesudahnya. Kekuasaan ini
digambarkan sebagai suatu perikatan (akad) dimana terlibat
dua pihak di dalamnya. Pihak pertama disebut "ahl-u
'l-ikhtiyar atau ahl-u 'l-hall-i wa 'l-'aqd" dan pihak kedua
disebut "ahlul imamah," yaitu pihak yang dianggap mempunyai
kelayakan untuk menjadi pemegang kekuasaan tertinggi karena
telah memenuhi persyaratan tertentu yang menjamin kualitas
fisik, mental atau spiritual, intelektual, kultural, dan
struktural kemasyarakatan yang menjamin wibawanya.
keputusan dalam kaitan hari libur Idul Fithri sebagai hari
libur nasional. Dan itu terlansir dalam sebuah Keputusan
Presiden dan diperkuat Keputusan Menteri Agama.
Hal itu jelas memperlihatkan keterkaitan Pemerintah dengan
urusan keagamaan (pelaksanaan ajaran agama). Lebih lanjut
kita melihat hal seperti itu dalam masalah perkawinan dan
peradilan khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa
urusan kekeluargaan di kalangan kaum muslimin bangsa
Indonesia. Maka dalam rangka urusan tersebut kita dapat
memahami kehadiran Undang-undang Perkawinan dan
Undang-undang Peradilan Agama (yang belum lama ini sudah
diundangkan). Dalam kaitan masalah-masalah tersebut di atas
terkait permasalahan wali al-amr.
Kata "wali al-amr" (dalam sebutan Indonesia) berasal dari
"waliy-u 'l-amr" (bahasa Arab). Kata ini biasa diartikan
"penguasa." Kedua bagian kata majemuk ini sudah lazim
dipakai dalam bahasa Indonesia; yaitu kata "amr" biasa
dibunyikan "amar" yang berarti: perintah atau suruhan
(misalnya: dengan amar raja diartikan: atas perintah raja).
Mengamarkan: memerintahkan, menyuruh melakukan. Kalau
ditambah dengan akhiran "an" maka menjadi "amaran" yang
berarti: perintah, suruhan, tugas (yang harus dilakukan).
Tetapi dalam kata asalnya, ia mempunyai arti yang lebih
luas, selain berarti: order, komando, otoritas, power, juga
berarti: urusan, persoalan atau perkara, masalah penting.
Dari akar kata "amr" ini, timbul bentuk-bentuk kata "amir,"
"amiral" (admiral), "amiralay (brigadier general), amirul
mu'minin (khalifah), "imarah" (sifat keamiran, atau
markasnya, atau wilayahnya).
Adapun kata "wali" juga sudah lazim dipakai dalam bahasa
Indonesia, yang berarti: orang yang menurut hukum diserahi
kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu
belum dewasa; pengasuh pengantin perempuan ketika nikah
yaitu keluarga dekatnya yang melakukan janji atau akad nikah
dengan pengantin laki-laki (dalam urusan nikah ini dikenal
juga adanya wali hakim yaitu pejabat urusan agama yang
bertindak sebagai wali); wali Allah atau waliullah, yaitu
orang suci dan keramat (seperti Wali Songo); kepala
pemerintahan (seperti wali kota, wali negara). Dalam bahasa
asalnya, kata ini berarti juga: penolong, pelindung, teman
atau sahabat, pemilik atau penguasa sesuatu barang,
pemelihara, petugas. Dari akar kata ini berkembang
bentuk-bentuk kata: wala yang berarti: cinta, persahabatan,
loyalitas, kekeluargaan; kata "wilayah" yang berarti
kekuasaan, kewenangan, daerah yurisdiksi. Itulah pembahasan
sepintas dari segi etimologis dan lexicologis, tentang
kata-kata "wali" dan "amr."
Maka kata "waliy-u 'l-amr" dengan pengertian "penguasa" atau
"pemerintah," cukup beralasan dilihat dari segi pemakaian
bahasa. Sesudah itu, ingin kita melihat kaitan pengertian
kata ini dengan persoalan hukum dalam rangka kajian fiqh.
Dalam persoalan ini tentunya pada tingkat pertama kita
berupaya mencari pokok persoalannya dalam al-Qur'an. Maka
disana kita akan menemukan pemakaian kata "uli 'l-amr" (yang
artinya dengan "waliy-u 'l-amr"), pada dua tempat, yaitu
pada ayat 59 surah an-Nisa, dan pada ayat 83 dari surah yang
sama. [1] Yang pertama berbunyi (terjemahnya): Hai
orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
rasulNya dan "ulil amri" dari kalian...). Dan yang kedua
berbunyi (Terjemahnya): Apabila mereka ditimpa sesuatu
peristiwa keamanan atau ketakutan, lalu mereka
menyiarkannya. Seandainya mereka mengembalikan persoalan itu
kepada Rasul dan kepada "uli 'l-amri" dari mereka, niscaya
orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui hal itu
...). Mufassir kenamaan yakni Imam 'Imaduddin Ibn Katsir
menukilkan keterangan Ibn 'Abbas (Sahabat Nabi) r.a. "yakni
ahl-u 'l fiqh-i wa 'l-din" (yang dimaksud dengan uli 'l-amr
yaitu ahli dalam masalah-masalah agama). Sama dengan itu,
pendapat Mujahid, 'Atha, Al Hasan Al Bashri dan Abul 'Aliyah
(semuanya ulama Tabi'in) yakni al-'ulama" (yang dimaksud
dengan uli 'l-amr adalah ulama). Ibn Katsir melanjutkan
keterangannya bahwa yang jelas (wa 'l-Lah-u a'lam), kata ini
pengertian umumnya mencakup para amir (umara) ulama.
Pengertian ini diperkuat oleh ayat 63 surah al-Maidah dan
ayat 43 surah an-Nahl; [2] ditambah dengan penjelasan hadits
shahih yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. dari sabda
Rasulullah s.a.w.: Barangsiapa mendurhakai aku berarti dia
sudah taat kepada Allah dan barangsiapa mendurhakai amir
yang saya angkat berarti dia telah mendurhakai aku. [3] Maka
semua penjelasan ini merupakan perintah untuk mentaati para
ulama dan umara. Beberapa hadits lainnya dari berbagai
sumber berita dari sejumlah sahabat Nabi telah dipaparkan
oleh Ibn Katsir, yang semuanya mengacu kepada keharusan
mentaati amir-amir (para petugas atau penguasa yang diangkat
Nabi dalam berbagai urusan yang ditempatkan di berbagai
daerah (yang telah dibebaskan ketika itu). (Lihat h.517 Juz
I Tafsir Ibn Katsir).
Ahli fiqh kenamaan yakni Imam Abul Hasan 'Ali al-Mawardi
ketika mengulas jenis-jenis kewenangan yang disebut "imarah"
yang pejabatnya disebut "amir" beliau mensitir juga ayat 59
surah an-Nisa tersebut di atas, lalu beliau menjelaskan
bahwa didalam pengertian "uli- 'l-amr" ada dua pendapat.
Pertama, bahwa yang dimaksud dengan kata itu, ialah
amir-amir, dan ini pendapat Ibn Abbas r.a. Pendapat kedua,
bahwa yang dimaksud dengan kata ini ialah para ulama.
Demikian pendapat Jabir, al-Hasan dan 'Atha. Bahkan Imam
al-Mawardi ini ketika membahas masalah Imamah atau
Kekhalifahan (Bab Pertama dari bukunya yang berjudul
al-Ahkam al-Shulthaniyah), beliau juga berpatokan dari ayat
59 (surah an-Nisa) tersebut. Dari ulasan beliau dapat
ditarik pengertian bahwa didalam kata "uli 'l-amr" termasuk
penguasa atau pemimpin tertinggi pemerintahan sampai kepada
pejabat-pejabat yang berwenang di daerah-daerah, atau dalam
urusan-urusan yang diserahkan pengelolanya kepada mereka.
Mereka itu disebut "wulat" (mufradnya wali sebagai singkatan
dari waliy-u 'l-amr) dan umara (tunggalnya amir) yaitu
penguasa yang diberi kewenangan dalam satu urusan tertentu,
atau suatu daerah kekuasaan tertentu.
Teori Wilayah (Kekuasaan atau Kewenangan)
Di dalam Fiqh (Ilmu Hukum Islam) ditemukan adanya dua jenis
kekuasaan (wilayah) yang dikaitkan dengan sumbernya, dan dua
jenis lagi yang dikaitkan dengan jangkauan kewenangannya.
Yang dikaitkan dengan sumbernya atau pangkal timbulnya
kekuasaan itu, ialah pertama: sumber kekuasaan yang sifatnya
natural-kultural, yang timbul dari suatu keadaan yang
menyangkut kepentingan dirinya, dimana yang bersangkutan
tidak atau belum cakap dan mampu melakukan tindakan hukum
yang berkaitan dengan hak-hak dan atau kewajibannya (faqid-u
'l-ahliyah atau naqish-u 'l-ahliyah). Disini berperan orang
lain menggantikan melakukan tindakan hukum, maka timbullah
apa yang misalnya disebut "vaderlijke-macht" (kekuasaan
ayah) yang sifatnya natural, yang berkembang menjadi
kultural. Yang kedua: sumber kekuasaan yang sifatnya sosial
atau konstitusional, yang timbul dari suatu keadaan yang
menyangkut kepentingan umum, utamanya untuk memberikan
perlindungan bagi kepentingan masyarakat, supaya terjamin
kebebasannya, keamanannya, dan ketertibannya, dalam
memperoleh hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya.
Maka timbullah apa yang misalnya disebut rechtsmacht
(kekuasaan mengadili), beheersmacht (kekuasaan mengelola),
regeringsmacht (kekuasaan memerintah) dan seterusnya yang
semuanya itu sifatnya sosial yang berkembang menjadi
konstitusional.
Kekuasaan jenis pertama (menurut fiqh) ada dua macam, yaitu:
wilayah (perwalian), wishayah (pengampunan atau kuratel).
Perwalian ini merupakan hak alamiah (natural) dari orang tua
dan keluarga dekat, dan dalam keadaan tertentu dapat
melompat kepada uli 'l-amr (pemegang kekuasaan sosial atau
konstitusional) seperti wali hakim dalam masalah pernikahan
yang wali nasabnya berlaku 'adhal (menolak untuk menjadi
wali dalam perkawinan yang dibenarkan menurut hukum dan
wajar dilangsungkan). Perwalian tersebut menyangkut diri dan
harta benda mereka yang belum cakap melakukan tindakan
hukum, seperti anak-anak yang belum dewasa (akil baligh).
Dan perwalian tersebut meliputi kekuasaan (kewenangan)
pemeliharaan, termasuk penyusuan (radha'ah), perawatan
(hadhanah), pemberian nafkah, pendidikan, pemberian izin
kawin. Pemegang kekuasaan perwalian atau mereka yang disebut
wali, tidak termasuk dalam pengertian uli 'l-amr atau
waliy-u 'l-amr (wali al-amr). Mereka itu termasuk dalam
kelompok pemegang wilayah khasshah, yang kedudukannya dalam
mengurus dan mengelola diri dan harta benda orang-orang yang
berada dalam perwaliannya, kekuasaannya lebih kuat dari
kelompok pemegang wilayah 'ammah (uli al-amr). Kewenangan
wali tersebut diatas hanya menyangkut hal-hal yang bersifat
perdata, sedang kewenangan waliy-u 'l-amr menyangkut hal-hal
yang bersifat kemaslahatan umum (algemeeneblang) dalam ruang
lingkup hukum publik (al-ahkam al-shulthaniyah).
Teori Fiqh dalam Kekuasaan Waliy-u 'l-amr
Al-ahkam al-sulthaniyah (hukum publik) dan
kewenangan-kewenangan yang bersangkutan dengan itu yang
ditata dalam hukum Islam (al-wilayat al-diniyah), dalam
suatu pembahasan yang luas oleh Imam Al Mawardi, telah
dirinci dalam 20 macam kewenangan. Yaitu, pertama, al-Imamah
(al-Khilafah); kedua, al-Wizarah (Kementrian); ketiga,
al-Imarah 'ala 'l-bilad (Pemerintahan Daerah); keempat,
al-Imarah 'ala 'l-Jihad (Kekuasaan Pertahanan atau
Keamanan); kelima, al-Wilayah 'ala 'l-hurubi 'l-mashalih
(Kekuasaan Penertiban Masyarakat); keenam, Wilayat-u
'l-Qadha (Kekuasaan Kehakiman); ketujuh, Wilayat-u
'l-Mazhalim (ada kemiripan dengan Kekuasaan Kepolisian);
kedelapan, Wilayat-un Naqabah 'ala dzaw-i 'l-ansab
(Kekuasaan Pengawasan atau Pencatatan cipil); kesembilan,
al-Wilayat 'ala Imamat-i 'l-Masajid (Kekuasaan pengangkatan
Imam-Imam dan penataan pimpinan masjid-masjid); kesepuluh,
al-Wilayah 'ala 'l-Hajj (Kekuasaan penyelenggaraan ibadah
haji); kesebelas, Wilayat-u 'l-Shadaqat (Kekuasaan
pelaksanaan Zakat); kedua belas, Fi Qasm-i 'l-Fa'i wa
'l-Ghanimah (Kekuasaan pengaturan dan pengurusan harta
rampasan); ketiga belas, Fi wadh-'i 'l-jizyah wa 'l-kharaj
(Kekuasaan penetapan dan pemungutan pajak-pajak); keempat
belas, Fi ma takhtalif ahkamuh-u min al-bilad (Penetapan
status tanah); kelima belas, Fi Ihya al-mawat wa 'l-stikhraj
al-miyah (Kekuasaan pengelolaan tanah dan penggunaan sumber
air); keenam belas, Fil hima wa 'l-arfaq (Kekuasaan
penetapan tanah atau hutan lindung); ketujuh belas, Fi Ahkam
al-Iqtha' (Hukum Pertanahan); kedelapan belas, Fi Wadh-'i
'I-Diwan (Kekuasaan pengaturan Tata Usaha Pemerintahan);
kesembilan belas, Fi Ahkam al-Jaraim (Pengaturan Hukum
Pidana), dan kedua puluh, Fi Ahkam al-Hisbah (ada kemiripan
dengan Kekuasaan Kejaksaan).
Berbagai macam kekuasaan dan kewenangan yang diuraikan dalam
rincian tersebut di atas, maka kekuasaan yang pertama
dibahas yaitu Imamah atau Khalifah merupakan kekuasaan yang
tertinggi dan merupakan juga sumber segala kewenangan yang
bermacam-macam yang disebutkan sesudahnya. Kekuasaan ini
digambarkan sebagai suatu perikatan (akad) dimana terlibat
dua pihak di dalamnya. Pihak pertama disebut "ahl-u
'l-ikhtiyar atau ahl-u 'l-hall-i wa 'l-'aqd" dan pihak kedua
disebut "ahlul imamah," yaitu pihak yang dianggap mempunyai
kelayakan untuk menjadi pemegang kekuasaan tertinggi karena
telah memenuhi persyaratan tertentu yang menjamin kualitas
fisik, mental atau spiritual, intelektual, kultural, dan
struktural kemasyarakatan yang menjamin wibawanya.

keroncong- KAPTEN
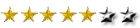
-

Age : 70
Posts : 4535
Kepercayaan : Islam
Location : di rumah saya
Join date : 09.11.11
Reputation : 67
 Re: hubungan antara ulama dan umara
Re: hubungan antara ulama dan umara
Adanya pihak kedua yang disebut ahl-u 'l-hall-i wa 'l-'aqd
ialah untuk menjamin terwujudnya upaya ikhtiyar (sehingga
mereka juga disebut ahl-u 'l-ikhtiyar) yaitu upaya seleksi
dan pemilihan untuk menentukan yang terbaik (al-afdhal) dari
pihak pertama. Dan selanjutnya formulasi "ikhtiyar" ini
dimaksudkan juga adanya pencerminan kebebasan dan
kesuka-relaan (tanpa tekanan dan paksaan) dalam upaya
ikhtiyar tersebut, bagi semua pihak yang bersangkutan. Oleh
karenanya akad ini disebut juga 'aqd-u muradhat (akad yang
dilandasi sikap kesuka-relaan).
Dari teori pokok yang diuraikan di atas, diciptakan beberapa
teori lain sebagai kelanjutannya. Di antaranya teori
"tauliyah" untuk melahirkan legalitas atas suatu otoritas
tertentu. Untuk lebih mendalami teori tersebut dapat kita
simak praktek penjabarannya yang digambarkan dalam fiqh
(Ilmu Hukum Islam) ketika membahas pengangkatan hakim
(qadhi) dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman
(wilayat-u 'l-qadha). Bahwa pengangkatan hakim itu termasuk
fardhu kifayah (sama dengan penetapan Imam (a'dzham) yaitu
Khalifah, yakni suatu tugas mengemban amanat keagamaan yang
menyangkut keseluruhan masyarakat, tidak bagi orang seorang,
dengan kata lain bukan tugas individual yang bersifat
personal, tetapi tugas semacam ini menjadikan setiap orang
dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan,
keseluruhannya menanggung dosa (dipandang bersalah dalam
hukum agama), tetapi yang berkaitan dengan keharusan
pemenuhan tugas kolektif tersebut, cukup seorang atau
sekelompok orang tertentu yang memenuhi persyaratan dalam
kedudukan tertentu yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya
tugas tersebut maka masyarakat yang bersangkutan berarti
sudah menunaikan tugas kolektif itu.
Gambaran selengkapnya dari teori tauliyah (dalam
pengangkatan hakim) diuraikan sebagai berikut:
Imam Dimyathi menguraikan bahwa pengangkatan hakim harus
merupakan tauliyah dari Imam atau Pemegang kekuasaan
tertinggi dalam pemerintahan atau pejabat (makdzun) yang
ditunjuk olehnya. Jika tidak terdapat penguasa seperti itu,
maka tauliyah dilakukan oleh ahl-u 'l-halli wa 'l-'aqd yaitu
kelompok orang-orang yang berwibawa dalam masyarakat yang
dapat menentukan pelaksanaan atau pembatalan suatu urusan
penting dalam masyarakatnya, dalam hal ini seperti para
ulama dan pemuka-pemuka masyarakat yang dapat berhimpun dan
membuat kesepakatan diantara mereka. Atau cukup sebahagian
dari mereka walaupun hanya seorang diantara mereka asal ada
persetujuan. Dalam proses perubahan sosial, fiqh
mengembangkan teori yang lebih rialistik dengan teori
kekuasaan "sulthan." Yaitu, pemegang kekuasaan dan
kewenangan memerintah dengan kekuasaan yang nyata (dzu
syaukah). Penguasa seperti itu dapat menggantikan kedudukan
Imam dalam fungsinya menegakkan (melindungi dan mengurus)
kepentingan umum dari masyarakatnya, sebagai satu hal yang
tak terelakkan (li 'l-dharurah) untuk tidak terbengkalai
kepentingan rakyat banyak (untuk menghindari kevakuman dalam
kekuasaan yang menjurus kepada anarki).
Uraian Imam Dimyati tersebut di atas bertemu dengan
pokok-pokok pandangan Imam al-Mawardi dalam pembahasannya
tentang latar belakang pemikiran dalam teori Imamah atau
Khilafah, yaitu suatu bentuk- kekuasaan umum dalam sosok
seorang penguasa tertinggi dalam lingkungan suatu masyarakat
besar untuk mencegah terjadinya anarki dalam masyarakat
tersebut, dengan adanya kekuasaan yang berwibawa dengan
kewenangan memerintah, mengadili, mengamankan dan ketertiban
masyarakat.
Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat kaum muslimin,
kekuasaan seperti tersebut telah dijalankan oleh Rasulullah
setelah berhasil membentuk masyarakat merdeka yang terdiri
dari masyarakat majemuk di kota Yatsrib (Madinah) dimana ia
memperoleh suatu kekuasaan umum yang luas, meliputi
kewenangan memerintah, mengadili, melindungi wilayah dan
penduduknya, menegakkan keadilan dan mengembangkan
kesejahteraannya, melalui suatu perjanjian yang dibuat
bersama dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang
bersangkutan dengan tata masyarakat baru. Dengan lahirnya
naskah perjanjian Madinah (al-'Ahd al-Madani) ini, dunia
abad ke-7 Masehi diperkenalkan pada satu model kekuasaan
yang sebelumnya dunia hanya mengenal dua jenis atau model
kekuasaan yang mengatur masyarakat, yaitu kekuasaan kepala
suku (dalam masyarakat yang mengenal domisili tetap dan
lahan pemukiman). Ketika itu dunia sama sekali belum
mengenal dan menyaksikan model kekuasaan dalam bentuk negara
dan pemerintahan modern, kecuali sedikit teori klasik negara
utopia ciptaan para filsuf Yunani yang tidak pernah lahir
dalam kenyataan.
Dari model pertama tersebut di atas, berkembang model
kekuasaan kekhalifahan, yang kemudian berangsur pudar dimana
pada gilirannya model kesultanan muncul menjadi kenyataan,
yang menurut ilmuwan kenamaan Ibn Khaldun, model terakhir
ini cenderung bersifat sekuler, namun tidak dapat melepaskan
dlri dari berbagai bagian kekuasaan keagamaan (wilayat
syar'iyyah), karena tidak dapat mengabaikan kepentingan
rakyatnya yaitu kaum muslimin.
Problematika Hubungan Ulama dan Umara
Pembicaraan teoritis tentang masalah kekuasaan yang dibahas
dalam fiqh merupakan bagian dari peran ulama dalam
pembentukan hukum Islam. Di lain pihak praktek-praktek
penyelenggaraan kekuasaan nyata yang dijalankan oleh umara
(waliy-u 'l-amr) mulai dari model kekhalifahan, selanjutnya
dalam model kesultanan dan terakhir dalam model negara
dengan bentuk-bentuk pemerintahan modern ada kalanya terpadu
atau menyatu dengan upaya para ulama dalam pembentukan hukum
Islam (penggalian dan pengembangan serta penetrapannya), dan
ada masanya juga tidak sejalan.
Sepanjang masa kekhalifahan pertama (umara' al-mu'minin) itu
personalnya adalah ulama penuh, dan kerja samanya dengan
para ulama yang berada di luar jaringan kekuasaan sangat
baik, sehingga tidak timbul sesuatu dalam hal pengembangan
dan penerapan hukum Islam yang merupakan problematika dalam
arti yang menimbulkan kesulitan atau konflik. Namun dalam
perkembangan sejarah pasca kekhalifahanpertama,
kebijaksanaan umum umara dalam kekuasaan kekhalifahan Bani
Umayyah mengalami perubahan orientasi dimana keseimbangan
antar fungsi "harasat-u 'l-din" (pemeliharaan kepentingan
agama) dan fungsi "siasat-u 'l-dunya" (kebijakan penataan
urusan pemerintahan), cenderung lebih memberatkan sisi yang
kedua itu. Ditambah lagi kalau kebetulan personalia umaranya
bukan ulama. Dalam hal perkembangan keadaan yang demikian
itu, kita melihat keengganan banyak tokoh ulama (termasuk
para imam mujtahidin) menolak ajakan atau permintaan para
umara, supaya mereka masuk menempati kedudukan-kedudukan
dalam jaringan kekuasaan. Di antaranya ada yang melakukan
penentangan legal terbuka seperti Imam Ahmad Bin Hanbal
terhadap Khalifah al-Maimun. Sepanjang zaman itu hukum
positif yang diberlakukan oleh umara senantiasa diawasi dan
dari waktu ke waktu mendapat koreksi dari para ulama,
pengemban amanat pemeliharaan dan penerapan hukum Islam.
Maka pembentukan hukum Islam lebih banyak berkembang diluar
lembaga kekuasaan atau pemerintahan. Hukum Islam terbentuk
dengan mantap didalam lembaga keilmuan dan di tangan para
ulama dan kesadaran hukum di kalangan rakyat banyak (kaum
muslimin) tumbuh berkembang dan terbentuk melalui jalur
pendidikan dalam Ilmu fiqh. Hal ini banyak positifnya dalam
memberikan daya tahan bagi hukum Islam itu. Diantaranya yang
terpenting bahwa dengan keadaan seperti itu, ada pengawasan
juridis yang bebas terhadap perilaku kekuasaan yang ada di
tangan umara. Itu hal positif yang pertama, dan yang kedua
ialah nasib hukum Islam itu tidak tergantung pada nasib
lembaga-lembaga kekuasaan yang dari waktu ke waktu timbul
tenggelam, dan pada waktu-waktu tertentu menjadi hancur
berantakan. Yang sangat menyedihkan ialah sekitar empat abad
terakhir dari sejarah kaum muslimin sedunia, lembaga-lembaga
kekuasaannya yang pernah jaya dan dibanggakan, menjadi
hancur berantakan di tangan-tangan penjajahan Barat.
Wilayah-wilayah Islam yang luas di Afrika, Timur Tengah dan
Asia, ditaklukan oleh penjajah-penjajah itu, dan mereka
menduduki kawasan yang terbentang luas itu sebagai
penguasa-penguasa yang tidak disenangi dan tidak diakui
legalitasnya oleh rakyat banyak (kaum Muslim). Oleh
karenanya secara terpaksa mereka menciptakan
penguasa-penguasa boneka dari Bumiputera, atau memberi
pengakuan terbatas kepada umara lokal (raja-raja atau
sultan-sultan setempat) dengan bentuk pemerintahan yang
mereka namakan zelfbestuur. Keadaan seperti itu berlangsung
cukup lama sampai terjadinya perubahan global dengan
terjadinya dua Perang Dunia yang berjarak tidak terlalu
lama, yang mengubah struktur umum kekuasaan di seluruh
dunia. Maka di Indonesia lahirlah suatu negara merdeka
(Republik Indonesia) yang segera disambut oleh para ulama
dengan satu pengakuan legalitas, diantaranya yang dicetuskan
oleh pertemuan besar para ulama di Surabaya pada awal
Oktober 1945 yang menerima baik Fatwa Rois Akbar K.H. Hasyim
Asy'ari, didalamnya tercantum dua butir penting yang
berkaitan langsung dengan pembahasan kita ini, yaitu
bagian-bagian fatwa tersebut yang berbunyi: Kemerdekaan
Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945
wajib dipertahankan; Republik Indonesia sebagai satu-satunya
pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan meski
pun meminta pengorbanan harta dan jiwa.
Legilitas yang diberikan oleh sejumlah ahl-u 'l-hall-i wa
'l-'aqd-i yaitu para ulama tersebut diatas merupakan titik
tolak yang penting dalam perkembangan ketata-negaraan dan
hukum di Indonesia ini, yang mengantarkan adanya penegasan
yang bersifat parsial yang memberikan status waliy-u 'l-amr
kepada pemegang kekuasaan tertinggi di negara merdeka ini
yaitu Kepala Negara (ketika itu dijabat oleh Presiden
Sukarno). Dan kelanjutannya dari perkembangan itu
memungkinkan kehadiran Undang-undang Perkawinan dan
Undang-undang Peradilan Agama sebagaimana disinggung di
atas.
CATATAN
1. Tafsir Ibn Katsir
2. Tafsir Bin Badis
3. Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin,
4. Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al-Shulthaniyah
5. Ibn Ya'la Al Farra, Al-Ahkam Al-Shulthaniyah
6. Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah
7. Sayyid Bakri Addimyathi, I'anat-u al-Thalibin.
8. Inwar al-Khathub, Al-Ahliyyah al-Madaniyah.
9. Dr. Mushthafa Ahmad Azzarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am
10. K.H. Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam.
11. Elias A. Elias, Al-Qamus al-'Ashari.
12. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia
13. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum.
ialah untuk menjamin terwujudnya upaya ikhtiyar (sehingga
mereka juga disebut ahl-u 'l-ikhtiyar) yaitu upaya seleksi
dan pemilihan untuk menentukan yang terbaik (al-afdhal) dari
pihak pertama. Dan selanjutnya formulasi "ikhtiyar" ini
dimaksudkan juga adanya pencerminan kebebasan dan
kesuka-relaan (tanpa tekanan dan paksaan) dalam upaya
ikhtiyar tersebut, bagi semua pihak yang bersangkutan. Oleh
karenanya akad ini disebut juga 'aqd-u muradhat (akad yang
dilandasi sikap kesuka-relaan).
Dari teori pokok yang diuraikan di atas, diciptakan beberapa
teori lain sebagai kelanjutannya. Di antaranya teori
"tauliyah" untuk melahirkan legalitas atas suatu otoritas
tertentu. Untuk lebih mendalami teori tersebut dapat kita
simak praktek penjabarannya yang digambarkan dalam fiqh
(Ilmu Hukum Islam) ketika membahas pengangkatan hakim
(qadhi) dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman
(wilayat-u 'l-qadha). Bahwa pengangkatan hakim itu termasuk
fardhu kifayah (sama dengan penetapan Imam (a'dzham) yaitu
Khalifah, yakni suatu tugas mengemban amanat keagamaan yang
menyangkut keseluruhan masyarakat, tidak bagi orang seorang,
dengan kata lain bukan tugas individual yang bersifat
personal, tetapi tugas semacam ini menjadikan setiap orang
dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan,
keseluruhannya menanggung dosa (dipandang bersalah dalam
hukum agama), tetapi yang berkaitan dengan keharusan
pemenuhan tugas kolektif tersebut, cukup seorang atau
sekelompok orang tertentu yang memenuhi persyaratan dalam
kedudukan tertentu yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya
tugas tersebut maka masyarakat yang bersangkutan berarti
sudah menunaikan tugas kolektif itu.
Gambaran selengkapnya dari teori tauliyah (dalam
pengangkatan hakim) diuraikan sebagai berikut:
Imam Dimyathi menguraikan bahwa pengangkatan hakim harus
merupakan tauliyah dari Imam atau Pemegang kekuasaan
tertinggi dalam pemerintahan atau pejabat (makdzun) yang
ditunjuk olehnya. Jika tidak terdapat penguasa seperti itu,
maka tauliyah dilakukan oleh ahl-u 'l-halli wa 'l-'aqd yaitu
kelompok orang-orang yang berwibawa dalam masyarakat yang
dapat menentukan pelaksanaan atau pembatalan suatu urusan
penting dalam masyarakatnya, dalam hal ini seperti para
ulama dan pemuka-pemuka masyarakat yang dapat berhimpun dan
membuat kesepakatan diantara mereka. Atau cukup sebahagian
dari mereka walaupun hanya seorang diantara mereka asal ada
persetujuan. Dalam proses perubahan sosial, fiqh
mengembangkan teori yang lebih rialistik dengan teori
kekuasaan "sulthan." Yaitu, pemegang kekuasaan dan
kewenangan memerintah dengan kekuasaan yang nyata (dzu
syaukah). Penguasa seperti itu dapat menggantikan kedudukan
Imam dalam fungsinya menegakkan (melindungi dan mengurus)
kepentingan umum dari masyarakatnya, sebagai satu hal yang
tak terelakkan (li 'l-dharurah) untuk tidak terbengkalai
kepentingan rakyat banyak (untuk menghindari kevakuman dalam
kekuasaan yang menjurus kepada anarki).
Uraian Imam Dimyati tersebut di atas bertemu dengan
pokok-pokok pandangan Imam al-Mawardi dalam pembahasannya
tentang latar belakang pemikiran dalam teori Imamah atau
Khilafah, yaitu suatu bentuk- kekuasaan umum dalam sosok
seorang penguasa tertinggi dalam lingkungan suatu masyarakat
besar untuk mencegah terjadinya anarki dalam masyarakat
tersebut, dengan adanya kekuasaan yang berwibawa dengan
kewenangan memerintah, mengadili, mengamankan dan ketertiban
masyarakat.
Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat kaum muslimin,
kekuasaan seperti tersebut telah dijalankan oleh Rasulullah
setelah berhasil membentuk masyarakat merdeka yang terdiri
dari masyarakat majemuk di kota Yatsrib (Madinah) dimana ia
memperoleh suatu kekuasaan umum yang luas, meliputi
kewenangan memerintah, mengadili, melindungi wilayah dan
penduduknya, menegakkan keadilan dan mengembangkan
kesejahteraannya, melalui suatu perjanjian yang dibuat
bersama dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang
bersangkutan dengan tata masyarakat baru. Dengan lahirnya
naskah perjanjian Madinah (al-'Ahd al-Madani) ini, dunia
abad ke-7 Masehi diperkenalkan pada satu model kekuasaan
yang sebelumnya dunia hanya mengenal dua jenis atau model
kekuasaan yang mengatur masyarakat, yaitu kekuasaan kepala
suku (dalam masyarakat yang mengenal domisili tetap dan
lahan pemukiman). Ketika itu dunia sama sekali belum
mengenal dan menyaksikan model kekuasaan dalam bentuk negara
dan pemerintahan modern, kecuali sedikit teori klasik negara
utopia ciptaan para filsuf Yunani yang tidak pernah lahir
dalam kenyataan.
Dari model pertama tersebut di atas, berkembang model
kekuasaan kekhalifahan, yang kemudian berangsur pudar dimana
pada gilirannya model kesultanan muncul menjadi kenyataan,
yang menurut ilmuwan kenamaan Ibn Khaldun, model terakhir
ini cenderung bersifat sekuler, namun tidak dapat melepaskan
dlri dari berbagai bagian kekuasaan keagamaan (wilayat
syar'iyyah), karena tidak dapat mengabaikan kepentingan
rakyatnya yaitu kaum muslimin.
Problematika Hubungan Ulama dan Umara
Pembicaraan teoritis tentang masalah kekuasaan yang dibahas
dalam fiqh merupakan bagian dari peran ulama dalam
pembentukan hukum Islam. Di lain pihak praktek-praktek
penyelenggaraan kekuasaan nyata yang dijalankan oleh umara
(waliy-u 'l-amr) mulai dari model kekhalifahan, selanjutnya
dalam model kesultanan dan terakhir dalam model negara
dengan bentuk-bentuk pemerintahan modern ada kalanya terpadu
atau menyatu dengan upaya para ulama dalam pembentukan hukum
Islam (penggalian dan pengembangan serta penetrapannya), dan
ada masanya juga tidak sejalan.
Sepanjang masa kekhalifahan pertama (umara' al-mu'minin) itu
personalnya adalah ulama penuh, dan kerja samanya dengan
para ulama yang berada di luar jaringan kekuasaan sangat
baik, sehingga tidak timbul sesuatu dalam hal pengembangan
dan penerapan hukum Islam yang merupakan problematika dalam
arti yang menimbulkan kesulitan atau konflik. Namun dalam
perkembangan sejarah pasca kekhalifahanpertama,
kebijaksanaan umum umara dalam kekuasaan kekhalifahan Bani
Umayyah mengalami perubahan orientasi dimana keseimbangan
antar fungsi "harasat-u 'l-din" (pemeliharaan kepentingan
agama) dan fungsi "siasat-u 'l-dunya" (kebijakan penataan
urusan pemerintahan), cenderung lebih memberatkan sisi yang
kedua itu. Ditambah lagi kalau kebetulan personalia umaranya
bukan ulama. Dalam hal perkembangan keadaan yang demikian
itu, kita melihat keengganan banyak tokoh ulama (termasuk
para imam mujtahidin) menolak ajakan atau permintaan para
umara, supaya mereka masuk menempati kedudukan-kedudukan
dalam jaringan kekuasaan. Di antaranya ada yang melakukan
penentangan legal terbuka seperti Imam Ahmad Bin Hanbal
terhadap Khalifah al-Maimun. Sepanjang zaman itu hukum
positif yang diberlakukan oleh umara senantiasa diawasi dan
dari waktu ke waktu mendapat koreksi dari para ulama,
pengemban amanat pemeliharaan dan penerapan hukum Islam.
Maka pembentukan hukum Islam lebih banyak berkembang diluar
lembaga kekuasaan atau pemerintahan. Hukum Islam terbentuk
dengan mantap didalam lembaga keilmuan dan di tangan para
ulama dan kesadaran hukum di kalangan rakyat banyak (kaum
muslimin) tumbuh berkembang dan terbentuk melalui jalur
pendidikan dalam Ilmu fiqh. Hal ini banyak positifnya dalam
memberikan daya tahan bagi hukum Islam itu. Diantaranya yang
terpenting bahwa dengan keadaan seperti itu, ada pengawasan
juridis yang bebas terhadap perilaku kekuasaan yang ada di
tangan umara. Itu hal positif yang pertama, dan yang kedua
ialah nasib hukum Islam itu tidak tergantung pada nasib
lembaga-lembaga kekuasaan yang dari waktu ke waktu timbul
tenggelam, dan pada waktu-waktu tertentu menjadi hancur
berantakan. Yang sangat menyedihkan ialah sekitar empat abad
terakhir dari sejarah kaum muslimin sedunia, lembaga-lembaga
kekuasaannya yang pernah jaya dan dibanggakan, menjadi
hancur berantakan di tangan-tangan penjajahan Barat.
Wilayah-wilayah Islam yang luas di Afrika, Timur Tengah dan
Asia, ditaklukan oleh penjajah-penjajah itu, dan mereka
menduduki kawasan yang terbentang luas itu sebagai
penguasa-penguasa yang tidak disenangi dan tidak diakui
legalitasnya oleh rakyat banyak (kaum Muslim). Oleh
karenanya secara terpaksa mereka menciptakan
penguasa-penguasa boneka dari Bumiputera, atau memberi
pengakuan terbatas kepada umara lokal (raja-raja atau
sultan-sultan setempat) dengan bentuk pemerintahan yang
mereka namakan zelfbestuur. Keadaan seperti itu berlangsung
cukup lama sampai terjadinya perubahan global dengan
terjadinya dua Perang Dunia yang berjarak tidak terlalu
lama, yang mengubah struktur umum kekuasaan di seluruh
dunia. Maka di Indonesia lahirlah suatu negara merdeka
(Republik Indonesia) yang segera disambut oleh para ulama
dengan satu pengakuan legalitas, diantaranya yang dicetuskan
oleh pertemuan besar para ulama di Surabaya pada awal
Oktober 1945 yang menerima baik Fatwa Rois Akbar K.H. Hasyim
Asy'ari, didalamnya tercantum dua butir penting yang
berkaitan langsung dengan pembahasan kita ini, yaitu
bagian-bagian fatwa tersebut yang berbunyi: Kemerdekaan
Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945
wajib dipertahankan; Republik Indonesia sebagai satu-satunya
pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan meski
pun meminta pengorbanan harta dan jiwa.
Legilitas yang diberikan oleh sejumlah ahl-u 'l-hall-i wa
'l-'aqd-i yaitu para ulama tersebut diatas merupakan titik
tolak yang penting dalam perkembangan ketata-negaraan dan
hukum di Indonesia ini, yang mengantarkan adanya penegasan
yang bersifat parsial yang memberikan status waliy-u 'l-amr
kepada pemegang kekuasaan tertinggi di negara merdeka ini
yaitu Kepala Negara (ketika itu dijabat oleh Presiden
Sukarno). Dan kelanjutannya dari perkembangan itu
memungkinkan kehadiran Undang-undang Perkawinan dan
Undang-undang Peradilan Agama sebagaimana disinggung di
atas.
CATATAN
1. Tafsir Ibn Katsir
2. Tafsir Bin Badis
3. Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin,
4. Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al-Shulthaniyah
5. Ibn Ya'la Al Farra, Al-Ahkam Al-Shulthaniyah
6. Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah
7. Sayyid Bakri Addimyathi, I'anat-u al-Thalibin.
8. Inwar al-Khathub, Al-Ahliyyah al-Madaniyah.
9. Dr. Mushthafa Ahmad Azzarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am
10. K.H. Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam.
11. Elias A. Elias, Al-Qamus al-'Ashari.
12. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia
13. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum.

keroncong- KAPTEN
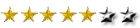
-

Age : 70
Posts : 4535
Kepercayaan : Islam
Location : di rumah saya
Join date : 09.11.11
Reputation : 67
 Re: hubungan antara ulama dan umara
Re: hubungan antara ulama dan umara
Hubungan antara Umara dan Ulama sebenarnya merupakan gejala
mutakhir. Sebab, pada dasarnya Islam tidak mengenal pemisahan
antara agama dan negara; atau lebih khusus lagi, antara gereja
dan negara, sebagaimana halnya dalam agama Kristen. Masalahnya
sederhana, yakni kalau dalam Islam tidak ada institusi gereja
sehingga dari segi ajaran apa yang dianggap sebagai
pertentangan antara gereja dan negara tidak pernah ada. Dalam
sejarah, sejak awal lahirnya agama Islam tidak ada pemisahan
antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan dan pada
masa Nabi baik kepemimpinan keagamaan maupun kepemimpinan
kenegaraan bersatu pada diri beliau. Demikian juga halnya
semasa para Khalifah mengganti Nabi. Mungkin sekali hal itu
terjadi karena masyarakatnya masih lebih sederhana dalam arti
belum banyak lembaga dan pranata yang majemuk sebagaimana
dalam masyarakat mutakhir. Bahkan pengertian tentang negara
saja tumbuh secara pelan-pelan dari masyarakat kesukuan atau
federasi kesukuan, kemudian berkembang menjadi umat dan lambat
laun menjelma menjadi negara.
Istilah umat sebenarnya sudah dipakai dalam masa sebelum Islam
yang berarti kelompok agama. Konon, dalam masyarakat Arabia
Selatan Kuno dikenal istilah lumiya yang berarti konfederasi
suku-suku, dan istilah umat pada masa Nabi agaknya berdekatan
dengan istilah ini yang dimaksudkan untuk menunjuk komunitas
Islam yang pertama di Madinah. Perkataan Madinah yang semula
menjadi gelar kehormatan untuk kota Yathrib kemudian sering
dipakai Yunani. Dari pengertian inilah lambat laun muncul
negara sebagaimana kita kenal dalam masa sekarang.
Sesudah Nabi, istilah yang banyak dipakai untuk menyebut
pimpinan negara adalah Khalifah. Pada masa Abu Bakar,
istilahnya adalah Khalifat-u Rasul-u 'l-Lah yang berarti
pengganti Nabi. Pada masa Umar diusulkan penggunaan gelar
Khalifat-u Khalifat-i Rasul-u 'l-Lah yang berarti pengganti
Nabi. Konon, Umar berkeberatan dengan istilah yang panjang ini
sehingga kemudian diperkenalkan istilah baru Amir-u
'l-Mukmin-in. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Amir ini
banyak dipakai untuk menyebut penguasa-penguasa pada tingkat
yang lebih rendah seperti Gubernur atau Walikota. Konon, pada
tahun 935, seorang Amir di Baghdad mulai menggunakan gelar
Amir al-Umara' untuk menegaskan bahwa dia adalah Amir yang
tertinggi atau Amir di atas Amir.
Istilah lain yang juga sering dipakai untuk menunjuk pimpinan
negara adalah Sultan. Gelar ini konon pertama kalinya
diberikan oleh Khalifah Harun al-Rashid kepada Wazirnya. Konon
pada abad ke X sudah banyak dipakai secara tak resmi untuk
menunjuk kepada penguasa-penguasa daerah yang merdeka. Pada
masa kesultanan Seljuk, istilah Sultan lantas dipakai sebagai
gelar untuk pimpinan politik dan militer tertinggi, sementara
istilah Khalifah lebih terbatas kepada pimpinan keagamaan
saja. Hal ini menunjukkan telah merosotnya istilah Khalifah
yang sudah mulai sejak abad-abad akhir dari Khalifah Abbasiah
di Baghdad. Dan dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 1258, maka
gelar Khalifah hanyalah semacam gelar kehormatan tanpa
wewenang politik. Ini terbukti misalnya dengan diterimanya
seorang Pangeran Abbasiah yang melarikan diri dari Baghdad
pada tahun 1261 dengan gelar Khalifah tetapi tanpa kekuasaan
politik. Khalifah lalu diartikan sebagai Imam yang hanya
mengurusi soal-soal peribadatan, sedangkan soal-soal
kenegaraan menjadi urusan Sultan.
Dari telaah tarikh ringkas ini barangkali kita bisa mengatakan
bahwa walaupun pada mulanya agama dan negara tidak dapat
dipisahkan dalam Islam, perkembangan masyarakat bisa
menyebabkan terpisahnya kepemimpinan agama dan kepemimpinan
negara karena berbagai alasan. Yang pertama tentu saja karena
harapan untuk memperoleh pimpinan politik yang saleh dan
religius serta memperoleh dukungan yang luas dari umat tidak
berhasil. Yang kedua, mungkin juga karena makin majemuknya
masyarakat dan makin luasnya kekuasaan negara. Dua jenis
kekuasaan itu sulit disatukan dalam satu tangan. Apakah hal
ini melanggar doktrin asli, para ahli fiqh yang bisa menjawab
itu.
Memang, kemerosotan kedudukan Khalifah sebenarnya terjadi pada
saat kekuasaan politik mengalami kemerosotan. Dan pada masa
semacam itu sering terjadi perebutan kekuasaan. Menghadapi
situasi semacam itu para ulama banyak yang memilih berada di
luar kekuasaan dan berbakti sebagai penjaga hati nurani
umatnya. Karena itu sering kita mendengar cerita ketegangan
antara Sultan atau para umara dengan para ulama. Hal ini bisa
terjadi karena para ulama itu menilai bahwa Sultan tidak lagi
berada di garis agama atau sedikitnya melakukan maksiat dengan
kekuasaannya. Karena para ulama ini hidup di tengah rakyat
dengan gaya hidup sederhana seperti masyarakat sekitarnya,
maka fatwanya tidak saja berbobot agama tetapi juga
berpengaruh luas dan sering kali mencerminkan pendapat
masyarakatnya. Dalam kedudukan seperti itu fatwa para ulama
lantas menjadi semacam sumber legitimasi. Karena itulah kita
mendengar banyak cerita tentang usaha Sultan untuk "membeli"
ulama yang berpengaruh, dengan memberinya jabatan sebagai
qadli atau mufti negara. Lalu ada banyak cerita tentang ulama
besar yang menolak tawaran Sultan dan kemudian mengalami
siksaan. Dalam bahasa sekarang seakan-akan ulama besar ini
menjadi semacam "tokoh oposisi" yang tidak mau tunduk kepada
kekuasaan Sultan. Tentu saja ada juga ulama yang bersedia
menerima tawaran Sultan dan kemudian menjadi Ulama Negara.
Ketegangan semacam ini tampaknya agak laten di dunia Islam
yang tidak lagi bisa menyatakan kembali kuasa agama dan kuasa
negara.
Seperti kita baca dari sejarah klasik Islam, proses itu sudah
mulai sejak berakhirnya masa Khulafa-u 'l-Rasjid-in. Kekuasaan
Islam yang semula bersumbu pada ikatan keagamaan (umat)
pelan-pelan terbawa kembali ke dalam ikatan kesukuan
(qabilah). Hal ini terus terjadi sampai kepada tergesernya
kekuasaan itu dari bangsa Arab sampai kemudian berakhir pada
masa Turki Usmani. Keummatan memang masih menjadi dasar
legitimasi tetapi kekuasaan riil mulai bertumpu kepada ikatan
kesukuan bahkan cabang-cabang keluarga. Dari segi agama
barangkali kita bisa menganggap ini sebagai kemerosotan,
tetapi dari segi sejarah tampaknya hal itu menunjukkan
kemustahilan menegakkan republik keagamaan dalam susunan
masyarakat feodal.
Pada masa kita sekarang jarak antara umara dan ulama
diperbesar oleh banyak faktor yang kompleks. Masyarakat telah
jauh mengalami proses deferensiasi dan para ulama seakan-akan
hanya mengkhususkan diri dalam soal-soal keagamaan. Juga
perkembangan ilmu pengetahuan modern menyebabkan perbedaan
bidang antara ilmuwan dan ulama walaupun secara bahasa
sebenarnya kedua kata itu masih searti. Sekalipun demikian
pengaruh ulama pada masyarakat masih tetap besar sehingga
fatwa mereka sedikit banyak masih mempengaruhi legitimasi
pemerintahan. Dengan kalimat yang lebih singkat para ulama ini
bagaimanapun juga masih punya peranan politik. Karena itu
senantiasa ada usaha-usaha untuk merangkul para Ulama; baik
itu dilakukan oleh Partai Politik, atau golongan-golongan lain
yang ingin turut serta dalam pengambilan keputusan politik.
Dan seperti biasa, senantiasa ada ulama yang ingin tetap
merdeka dan ada pula yang memutuskan untuk bergabung dengan
kekuatan politik. semua ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat
modern sekalipun, agama masih memiliki peranan penting dalam
proses politik.
Pada abad kita sekarang masalah yang menonjol adalah
tarik-menarik antara agama dan kebangsaan sebagai dasar ikatan
kenegaraan. Hal ini muncul, sebagaimana umum diketahui, dari
proses modernisasi yang mulai di Eropa kemudian menyebar
keseluruh dunia. Gejala yang kita kenal adalah jatuhnya
imperium-imperium besar dan munculnya negara-negara kebangsaan
sebagai pengganti. Di dunia Islam mula-mula dasar ikatan
keagamaan dan kebangsaan bersama-sama digunakan sebagai dasar
untuk melawan imperialisme. Patriotisme dinyatakan sebagai
bagian dari iman. Di negara kita pada masa pergerakan nasional
juga muncul perlawanan dengan kombinasi keagamaan dan
kebangsaan. Pada Sarekat Islam misalnya istilah "selam" sama
artinya dengan "Bumiputera". Dengan kata lain menjadi muslim
sama artinya dengan menjadi Pribumi. Tetapi perkembangan
kemudian, terutama pada saat konsolidasi kemerdekaan,
menunjukkan meningkatnya persaingan antara kedua dasar ini
yang akhirnya dimenangkan oleh dasar kebangsaan. Hal ini tidak
saja terjadi di negeri kita tapi juga di negara-negara Islam
lannya. Di Turki misalnya, sekalipun semula Mustafa Kemal
Ataturk juga berusaha memperoleh legitimasi keagamaan untuk
perjuangan nasionalnya, pada akhirnya Turki modern lebih
didasarkan pada ikatan kebangsaan. Juga di negara-negara Arab,
ikatan keakraban kemudian lebih ditekankan daripada ikatan
ke-Islam-an. Dan sudah wajar bila dalam semua masyarakat itu
timbul persoalan hubungan antara ulama dan umara karena
keduanya merupakan peranan yang berbeda tetapi punya kaitan
dalam legitimasi politik. Dalam situasi serupa itu agama masih
senantiasa diperlukan untuk memberi motivasi religius pada
program-program yang sesungguhnya profan. Demikianlah agama
masih diharapkan menjadi pemberi motivasi untuk pembangunan,
untuk keluarga berencana dan untuk modernisasi itu sendiri.
Sehingga bagaimana pun juga peranan ulama senantiasa masih
cukup besar.
Seperti kita baca dari sejarah klasik Islam, proses itu sudah
mulai sejak berakhirnya masa Khulafa-n 'l-Rasjid-in. Kekuasaan
Islam yang semula bersumbu pada ikatan keagamaan (umat)
pelan-pelan terbawa kembali ke dalam ikatan kesukuan
(qabilah). Hal ini terus terjadi sampai kepada tergesernya
kekuasaan itu dari bangsa Arab sampai kemudian berakhir pada
masa Turki Usmani. Keumatan memang masih menjadi dasar
legitimasi tetapi kekuasaan riil mulai bertumpu kepada ikatan
kesukuan bahkan cabang-cabang keluarga. Dari segi agama
barangkali kita bisa menganggap ini sebagai kemerosotan,
tetapi dari segi sejarah tampaknya hal itu menunjukkan
kemustahilan menegakkan republik keagamaan dalam susunan
masyarakat feodal.
Pada masa kita sekarang jarak antara umara dan ulama
diperbesar oleh banyak faktor yang kompleks. Masyarakat telah
jauh mengalami proses differensiasi dan para ulama seakan-akan
hanya mengkhususkan diri dalam soal-soal keagamaan. Juga
perkembangan ilmu pengetahuan modern menyebabkan perbedaan
bidang antara ilmuwan dan ulama walaupun secara bahasa
sebenarnya kedua kata itu masih searti. Sekalipun demikian
pengaruh ulama pada masyarakat masih tetap besar sehingga
fatwa mereka sedikit banyak masih mempengaruhi legitimasi
pemerintahan. Dengan kalimat yang lebih singkat para ulama ini
bagaimanapun juga masih punya peranan politik. Karena itu
senantiasa ada usaha-usaha untuk merangkul para Ulama; baik
itu dilakukan oleh Partai Politik, atau golongan-golongan lain
yang ingin turut serta dalam pengambilan keputusan politik.
Dan seperti biasa, senantiasa ada ulama yang ingin tetap
merdeka dan ada pula yang memutuskan untuk bergabung dengan
kekuatan politik. Semua ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat
modern sekalipun, agama masih memiliki peranan penting dalam
proses politik.
Pada abad kita sekarang masalah yang menonjol adalah
tolak-tarik antara agama dan kebangsaan sebagai dasar ikatan
kenegaraan. Hal ini muncul, sebagaimana umum diketahui, dari
proses modernisasi yang mulai di Eropa kemudian menyebar
keseluruh dunia. Gejala yang kita kenal adalah jatuhnya
imperium-imperium besar dan munculnya negara-negara kebangsaan
sebagai pengganti. Di dunia Islam mula-mula dasar ikatan
keagamaan dan kebangsaan bersama-sama digunakan sebagai dasar
untuk melawan imperialisme. Patriotisme dinyatakan sebagai
bagian dari iman. Di negara kita pada masa pergerakan nasional
juga muncul perlawanan dengan kombinasi keagamaan dan
kebangsaan. Pada Sarekat Islam misalnya istilah "selam" sama
artinya dengan "Bumiputera". Dengan kata lain menjadi muslim
sama artinya dengan menjadi Pribumi. Tetapi perkembangan
kemudian, terutama pada saat konsolidasi kemerdekaan,
menunjukkan meningkatnya persaingan antara kedua dasar ini
yang akhirnya dimenangkan oleh dasar kebangsaan. Hal ini tidak
saja terjadi di negeri kita tapi juga di negara-negara Islam
lainnya. Di Turki misalnya, sekalipun semula Mustafa Kemal
Ataturk juga berusaha memperoleh legitimasi keagamaan untuk
perjuangan nasionalnya, pada akhirnya Turki modern lebih
didasarkan pada ikatan kebangsaan. Juga di negara-negara Arab,
ikatan keakraban kemudian lebih ditekankan daripada ikatan
ke-Islam-an. Dan sudah wajar bila dalam kesemua masyarakat itu
timbul persoalan hubungan antara ulama dan umara karena
keduanya merupakan peranan yang berbeda tetapi punya kaitan
dalam legitimasi politik. Dalam situasi serupa itu agama masih
senantiasa diperlukan untuk memberi motivasi religius pada
program-program yang sesungguhnya profan. Demikianlah agama
masih diharapkan menjadi pemberi motivasi untuk pembangunan,
untuk keluarga berencana dan untuk modernisasi itu sendiri.
Sehingga bagaimana pun juga peranan ulama senantiasa masih
cukup besar.
Bagi seorang yang beragama mungkin keadaan ini terasa sebagai
suatu dilema yang sulit. Yang terang kondisi ideal sebagaimana
terkandung dalam doktrin asal dan tradisi awal Islam sudah
tidak ada lagi. Hidup dalam kondisi seperti sekarang, maka
menurut hemat saya hubungan ulama dan umara itu bisa
diibaratkan sebagai hubungan antara dua gajah yang sama-sama
besar, dan umat merupakan lapangan di mana dua gajah itu
hidup. Bencana akan terjadi jika dua gajah itu bertarung. Tapi
lapangan itu akan sama porak-porandanya jika dua gajah itu
kawin. Karena itu suasana yang ideal adalah jika kedua gajah
itu merumput bersama-sama tetapi tidak bertempur dan tidak
kawin. Dalam bahasa yang lebih teknis, sebaiknya ulama tetap
berada pada posisinya yang merdeka sebagai pembawa nilai-nilai
agama dan hati nurani masyarakatnya. Sehingga mereka tetap
bisa berperan korektif ketika terjadi sesuatu kesalahan dalam
penggunaan kekuasaan. Demikian juga para Umara sebaiknya
menghormati kedudukan yang merdeka dari para ulama tanpa
berusaha "menggusur" atau "membeli" mereka. Sudah barang tentu
para umara harus senatiasa mendengarkan para ulama apalagi
karena fatwa mereka mempunyai pengaruh yang luas. Dengan
demikian ulama dan umara akan bertindak sebagai pengimbang
satu sama lain. Hanya jika perimbangan itu tetap terjaga dan
serasi maka kesejahteraan umat akan senantiasa terjaga.
mutakhir. Sebab, pada dasarnya Islam tidak mengenal pemisahan
antara agama dan negara; atau lebih khusus lagi, antara gereja
dan negara, sebagaimana halnya dalam agama Kristen. Masalahnya
sederhana, yakni kalau dalam Islam tidak ada institusi gereja
sehingga dari segi ajaran apa yang dianggap sebagai
pertentangan antara gereja dan negara tidak pernah ada. Dalam
sejarah, sejak awal lahirnya agama Islam tidak ada pemisahan
antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan dan pada
masa Nabi baik kepemimpinan keagamaan maupun kepemimpinan
kenegaraan bersatu pada diri beliau. Demikian juga halnya
semasa para Khalifah mengganti Nabi. Mungkin sekali hal itu
terjadi karena masyarakatnya masih lebih sederhana dalam arti
belum banyak lembaga dan pranata yang majemuk sebagaimana
dalam masyarakat mutakhir. Bahkan pengertian tentang negara
saja tumbuh secara pelan-pelan dari masyarakat kesukuan atau
federasi kesukuan, kemudian berkembang menjadi umat dan lambat
laun menjelma menjadi negara.
Istilah umat sebenarnya sudah dipakai dalam masa sebelum Islam
yang berarti kelompok agama. Konon, dalam masyarakat Arabia
Selatan Kuno dikenal istilah lumiya yang berarti konfederasi
suku-suku, dan istilah umat pada masa Nabi agaknya berdekatan
dengan istilah ini yang dimaksudkan untuk menunjuk komunitas
Islam yang pertama di Madinah. Perkataan Madinah yang semula
menjadi gelar kehormatan untuk kota Yathrib kemudian sering
dipakai Yunani. Dari pengertian inilah lambat laun muncul
negara sebagaimana kita kenal dalam masa sekarang.
Sesudah Nabi, istilah yang banyak dipakai untuk menyebut
pimpinan negara adalah Khalifah. Pada masa Abu Bakar,
istilahnya adalah Khalifat-u Rasul-u 'l-Lah yang berarti
pengganti Nabi. Pada masa Umar diusulkan penggunaan gelar
Khalifat-u Khalifat-i Rasul-u 'l-Lah yang berarti pengganti
Nabi. Konon, Umar berkeberatan dengan istilah yang panjang ini
sehingga kemudian diperkenalkan istilah baru Amir-u
'l-Mukmin-in. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Amir ini
banyak dipakai untuk menyebut penguasa-penguasa pada tingkat
yang lebih rendah seperti Gubernur atau Walikota. Konon, pada
tahun 935, seorang Amir di Baghdad mulai menggunakan gelar
Amir al-Umara' untuk menegaskan bahwa dia adalah Amir yang
tertinggi atau Amir di atas Amir.
Istilah lain yang juga sering dipakai untuk menunjuk pimpinan
negara adalah Sultan. Gelar ini konon pertama kalinya
diberikan oleh Khalifah Harun al-Rashid kepada Wazirnya. Konon
pada abad ke X sudah banyak dipakai secara tak resmi untuk
menunjuk kepada penguasa-penguasa daerah yang merdeka. Pada
masa kesultanan Seljuk, istilah Sultan lantas dipakai sebagai
gelar untuk pimpinan politik dan militer tertinggi, sementara
istilah Khalifah lebih terbatas kepada pimpinan keagamaan
saja. Hal ini menunjukkan telah merosotnya istilah Khalifah
yang sudah mulai sejak abad-abad akhir dari Khalifah Abbasiah
di Baghdad. Dan dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 1258, maka
gelar Khalifah hanyalah semacam gelar kehormatan tanpa
wewenang politik. Ini terbukti misalnya dengan diterimanya
seorang Pangeran Abbasiah yang melarikan diri dari Baghdad
pada tahun 1261 dengan gelar Khalifah tetapi tanpa kekuasaan
politik. Khalifah lalu diartikan sebagai Imam yang hanya
mengurusi soal-soal peribadatan, sedangkan soal-soal
kenegaraan menjadi urusan Sultan.
Dari telaah tarikh ringkas ini barangkali kita bisa mengatakan
bahwa walaupun pada mulanya agama dan negara tidak dapat
dipisahkan dalam Islam, perkembangan masyarakat bisa
menyebabkan terpisahnya kepemimpinan agama dan kepemimpinan
negara karena berbagai alasan. Yang pertama tentu saja karena
harapan untuk memperoleh pimpinan politik yang saleh dan
religius serta memperoleh dukungan yang luas dari umat tidak
berhasil. Yang kedua, mungkin juga karena makin majemuknya
masyarakat dan makin luasnya kekuasaan negara. Dua jenis
kekuasaan itu sulit disatukan dalam satu tangan. Apakah hal
ini melanggar doktrin asli, para ahli fiqh yang bisa menjawab
itu.
Memang, kemerosotan kedudukan Khalifah sebenarnya terjadi pada
saat kekuasaan politik mengalami kemerosotan. Dan pada masa
semacam itu sering terjadi perebutan kekuasaan. Menghadapi
situasi semacam itu para ulama banyak yang memilih berada di
luar kekuasaan dan berbakti sebagai penjaga hati nurani
umatnya. Karena itu sering kita mendengar cerita ketegangan
antara Sultan atau para umara dengan para ulama. Hal ini bisa
terjadi karena para ulama itu menilai bahwa Sultan tidak lagi
berada di garis agama atau sedikitnya melakukan maksiat dengan
kekuasaannya. Karena para ulama ini hidup di tengah rakyat
dengan gaya hidup sederhana seperti masyarakat sekitarnya,
maka fatwanya tidak saja berbobot agama tetapi juga
berpengaruh luas dan sering kali mencerminkan pendapat
masyarakatnya. Dalam kedudukan seperti itu fatwa para ulama
lantas menjadi semacam sumber legitimasi. Karena itulah kita
mendengar banyak cerita tentang usaha Sultan untuk "membeli"
ulama yang berpengaruh, dengan memberinya jabatan sebagai
qadli atau mufti negara. Lalu ada banyak cerita tentang ulama
besar yang menolak tawaran Sultan dan kemudian mengalami
siksaan. Dalam bahasa sekarang seakan-akan ulama besar ini
menjadi semacam "tokoh oposisi" yang tidak mau tunduk kepada
kekuasaan Sultan. Tentu saja ada juga ulama yang bersedia
menerima tawaran Sultan dan kemudian menjadi Ulama Negara.
Ketegangan semacam ini tampaknya agak laten di dunia Islam
yang tidak lagi bisa menyatakan kembali kuasa agama dan kuasa
negara.
Seperti kita baca dari sejarah klasik Islam, proses itu sudah
mulai sejak berakhirnya masa Khulafa-u 'l-Rasjid-in. Kekuasaan
Islam yang semula bersumbu pada ikatan keagamaan (umat)
pelan-pelan terbawa kembali ke dalam ikatan kesukuan
(qabilah). Hal ini terus terjadi sampai kepada tergesernya
kekuasaan itu dari bangsa Arab sampai kemudian berakhir pada
masa Turki Usmani. Keummatan memang masih menjadi dasar
legitimasi tetapi kekuasaan riil mulai bertumpu kepada ikatan
kesukuan bahkan cabang-cabang keluarga. Dari segi agama
barangkali kita bisa menganggap ini sebagai kemerosotan,
tetapi dari segi sejarah tampaknya hal itu menunjukkan
kemustahilan menegakkan republik keagamaan dalam susunan
masyarakat feodal.
Pada masa kita sekarang jarak antara umara dan ulama
diperbesar oleh banyak faktor yang kompleks. Masyarakat telah
jauh mengalami proses deferensiasi dan para ulama seakan-akan
hanya mengkhususkan diri dalam soal-soal keagamaan. Juga
perkembangan ilmu pengetahuan modern menyebabkan perbedaan
bidang antara ilmuwan dan ulama walaupun secara bahasa
sebenarnya kedua kata itu masih searti. Sekalipun demikian
pengaruh ulama pada masyarakat masih tetap besar sehingga
fatwa mereka sedikit banyak masih mempengaruhi legitimasi
pemerintahan. Dengan kalimat yang lebih singkat para ulama ini
bagaimanapun juga masih punya peranan politik. Karena itu
senantiasa ada usaha-usaha untuk merangkul para Ulama; baik
itu dilakukan oleh Partai Politik, atau golongan-golongan lain
yang ingin turut serta dalam pengambilan keputusan politik.
Dan seperti biasa, senantiasa ada ulama yang ingin tetap
merdeka dan ada pula yang memutuskan untuk bergabung dengan
kekuatan politik. semua ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat
modern sekalipun, agama masih memiliki peranan penting dalam
proses politik.
Pada abad kita sekarang masalah yang menonjol adalah
tarik-menarik antara agama dan kebangsaan sebagai dasar ikatan
kenegaraan. Hal ini muncul, sebagaimana umum diketahui, dari
proses modernisasi yang mulai di Eropa kemudian menyebar
keseluruh dunia. Gejala yang kita kenal adalah jatuhnya
imperium-imperium besar dan munculnya negara-negara kebangsaan
sebagai pengganti. Di dunia Islam mula-mula dasar ikatan
keagamaan dan kebangsaan bersama-sama digunakan sebagai dasar
untuk melawan imperialisme. Patriotisme dinyatakan sebagai
bagian dari iman. Di negara kita pada masa pergerakan nasional
juga muncul perlawanan dengan kombinasi keagamaan dan
kebangsaan. Pada Sarekat Islam misalnya istilah "selam" sama
artinya dengan "Bumiputera". Dengan kata lain menjadi muslim
sama artinya dengan menjadi Pribumi. Tetapi perkembangan
kemudian, terutama pada saat konsolidasi kemerdekaan,
menunjukkan meningkatnya persaingan antara kedua dasar ini
yang akhirnya dimenangkan oleh dasar kebangsaan. Hal ini tidak
saja terjadi di negeri kita tapi juga di negara-negara Islam
lannya. Di Turki misalnya, sekalipun semula Mustafa Kemal
Ataturk juga berusaha memperoleh legitimasi keagamaan untuk
perjuangan nasionalnya, pada akhirnya Turki modern lebih
didasarkan pada ikatan kebangsaan. Juga di negara-negara Arab,
ikatan keakraban kemudian lebih ditekankan daripada ikatan
ke-Islam-an. Dan sudah wajar bila dalam semua masyarakat itu
timbul persoalan hubungan antara ulama dan umara karena
keduanya merupakan peranan yang berbeda tetapi punya kaitan
dalam legitimasi politik. Dalam situasi serupa itu agama masih
senantiasa diperlukan untuk memberi motivasi religius pada
program-program yang sesungguhnya profan. Demikianlah agama
masih diharapkan menjadi pemberi motivasi untuk pembangunan,
untuk keluarga berencana dan untuk modernisasi itu sendiri.
Sehingga bagaimana pun juga peranan ulama senantiasa masih
cukup besar.
Seperti kita baca dari sejarah klasik Islam, proses itu sudah
mulai sejak berakhirnya masa Khulafa-n 'l-Rasjid-in. Kekuasaan
Islam yang semula bersumbu pada ikatan keagamaan (umat)
pelan-pelan terbawa kembali ke dalam ikatan kesukuan
(qabilah). Hal ini terus terjadi sampai kepada tergesernya
kekuasaan itu dari bangsa Arab sampai kemudian berakhir pada
masa Turki Usmani. Keumatan memang masih menjadi dasar
legitimasi tetapi kekuasaan riil mulai bertumpu kepada ikatan
kesukuan bahkan cabang-cabang keluarga. Dari segi agama
barangkali kita bisa menganggap ini sebagai kemerosotan,
tetapi dari segi sejarah tampaknya hal itu menunjukkan
kemustahilan menegakkan republik keagamaan dalam susunan
masyarakat feodal.
Pada masa kita sekarang jarak antara umara dan ulama
diperbesar oleh banyak faktor yang kompleks. Masyarakat telah
jauh mengalami proses differensiasi dan para ulama seakan-akan
hanya mengkhususkan diri dalam soal-soal keagamaan. Juga
perkembangan ilmu pengetahuan modern menyebabkan perbedaan
bidang antara ilmuwan dan ulama walaupun secara bahasa
sebenarnya kedua kata itu masih searti. Sekalipun demikian
pengaruh ulama pada masyarakat masih tetap besar sehingga
fatwa mereka sedikit banyak masih mempengaruhi legitimasi
pemerintahan. Dengan kalimat yang lebih singkat para ulama ini
bagaimanapun juga masih punya peranan politik. Karena itu
senantiasa ada usaha-usaha untuk merangkul para Ulama; baik
itu dilakukan oleh Partai Politik, atau golongan-golongan lain
yang ingin turut serta dalam pengambilan keputusan politik.
Dan seperti biasa, senantiasa ada ulama yang ingin tetap
merdeka dan ada pula yang memutuskan untuk bergabung dengan
kekuatan politik. Semua ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat
modern sekalipun, agama masih memiliki peranan penting dalam
proses politik.
Pada abad kita sekarang masalah yang menonjol adalah
tolak-tarik antara agama dan kebangsaan sebagai dasar ikatan
kenegaraan. Hal ini muncul, sebagaimana umum diketahui, dari
proses modernisasi yang mulai di Eropa kemudian menyebar
keseluruh dunia. Gejala yang kita kenal adalah jatuhnya
imperium-imperium besar dan munculnya negara-negara kebangsaan
sebagai pengganti. Di dunia Islam mula-mula dasar ikatan
keagamaan dan kebangsaan bersama-sama digunakan sebagai dasar
untuk melawan imperialisme. Patriotisme dinyatakan sebagai
bagian dari iman. Di negara kita pada masa pergerakan nasional
juga muncul perlawanan dengan kombinasi keagamaan dan
kebangsaan. Pada Sarekat Islam misalnya istilah "selam" sama
artinya dengan "Bumiputera". Dengan kata lain menjadi muslim
sama artinya dengan menjadi Pribumi. Tetapi perkembangan
kemudian, terutama pada saat konsolidasi kemerdekaan,
menunjukkan meningkatnya persaingan antara kedua dasar ini
yang akhirnya dimenangkan oleh dasar kebangsaan. Hal ini tidak
saja terjadi di negeri kita tapi juga di negara-negara Islam
lainnya. Di Turki misalnya, sekalipun semula Mustafa Kemal
Ataturk juga berusaha memperoleh legitimasi keagamaan untuk
perjuangan nasionalnya, pada akhirnya Turki modern lebih
didasarkan pada ikatan kebangsaan. Juga di negara-negara Arab,
ikatan keakraban kemudian lebih ditekankan daripada ikatan
ke-Islam-an. Dan sudah wajar bila dalam kesemua masyarakat itu
timbul persoalan hubungan antara ulama dan umara karena
keduanya merupakan peranan yang berbeda tetapi punya kaitan
dalam legitimasi politik. Dalam situasi serupa itu agama masih
senantiasa diperlukan untuk memberi motivasi religius pada
program-program yang sesungguhnya profan. Demikianlah agama
masih diharapkan menjadi pemberi motivasi untuk pembangunan,
untuk keluarga berencana dan untuk modernisasi itu sendiri.
Sehingga bagaimana pun juga peranan ulama senantiasa masih
cukup besar.
Bagi seorang yang beragama mungkin keadaan ini terasa sebagai
suatu dilema yang sulit. Yang terang kondisi ideal sebagaimana
terkandung dalam doktrin asal dan tradisi awal Islam sudah
tidak ada lagi. Hidup dalam kondisi seperti sekarang, maka
menurut hemat saya hubungan ulama dan umara itu bisa
diibaratkan sebagai hubungan antara dua gajah yang sama-sama
besar, dan umat merupakan lapangan di mana dua gajah itu
hidup. Bencana akan terjadi jika dua gajah itu bertarung. Tapi
lapangan itu akan sama porak-porandanya jika dua gajah itu
kawin. Karena itu suasana yang ideal adalah jika kedua gajah
itu merumput bersama-sama tetapi tidak bertempur dan tidak
kawin. Dalam bahasa yang lebih teknis, sebaiknya ulama tetap
berada pada posisinya yang merdeka sebagai pembawa nilai-nilai
agama dan hati nurani masyarakatnya. Sehingga mereka tetap
bisa berperan korektif ketika terjadi sesuatu kesalahan dalam
penggunaan kekuasaan. Demikian juga para Umara sebaiknya
menghormati kedudukan yang merdeka dari para ulama tanpa
berusaha "menggusur" atau "membeli" mereka. Sudah barang tentu
para umara harus senatiasa mendengarkan para ulama apalagi
karena fatwa mereka mempunyai pengaruh yang luas. Dengan
demikian ulama dan umara akan bertindak sebagai pengimbang
satu sama lain. Hanya jika perimbangan itu tetap terjaga dan
serasi maka kesejahteraan umat akan senantiasa terjaga.

keroncong- KAPTEN
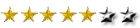
-

Age : 70
Posts : 4535
Kepercayaan : Islam
Location : di rumah saya
Join date : 09.11.11
Reputation : 67
 Similar topics
Similar topics» hubungan antara dosa dan bencana
» Hubungan antara Allah dan Yesus
» hubungan antara ismail dengan Muhammad
» hubungan antara fiqih prioritas dan fiqih pertimbangan
» Batak Dikristenkan Ternyata Hanya Untuk Dimanfaatkan Sebagai Batas Antara 2 Kerajaan Islam Pada Saat Itu di Sumatera Antara Aceh & Minang
» Hubungan antara Allah dan Yesus
» hubungan antara ismail dengan Muhammad
» hubungan antara fiqih prioritas dan fiqih pertimbangan
» Batak Dikristenkan Ternyata Hanya Untuk Dimanfaatkan Sebagai Batas Antara 2 Kerajaan Islam Pada Saat Itu di Sumatera Antara Aceh & Minang
Halaman 1 dari 1
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik


