konsep hareem fatimah mernisi
Halaman 1 dari 1 • Share
 konsep hareem fatimah mernisi
konsep hareem fatimah mernisi
ebagai seorang akademisi, Mernissi telah sekian lama merebut perhatian para aktivis perempuan dan peminat gender melalui buku-bukunya seperti Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in Modern Moslem Society— yang aslinya adalah disertasi doktornya, The Veil and the Male Elite dan seabrek buku lainnya yang—alhamdulillah— sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia. Dari tulisan-tulisannya, sedikit atau banyak kita dapat menarik benang merah untaian pemikiran Mernisi sekitar feminisme: Yakni betapa gigihnya dia menelisik kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintahan Arab —yang menurutnya— bukanlah intrinsik karena doktrin agama. Namun, lebih karena agama itu telah dimanipulasi oleh orang yang berkuasa untuk kepentingan dirinya sendiri.
Ada yang menarik dari rubrik “Kisah” berjudul Pengakuan “Selir” Pangeran Jefri dalam Media Indonesia edisi Minggu, 4/6/2000. Kisah ini mirip cerita 1001 malam, demikian Media mengawali beritanya. Kehidupan seorang pangeran; bergelimang uang, hidup mewah dan dikelilingi wanita-wanita cantik yang siap menghibur “luar-dalam.” Ya, benar, laporan tersebut membicarakan seorang pangeran flamboyan nan kaya raya bernama Pangeran Jefri Bolkiah, anggota kerajaan Brunei Darussalam.
Bukan kekayaan dan hobi pangeran yang suka pesta itu yang dijadikan satu-satunya sasaran tembak. Tapi “kesukaan” Pangeran Jefri Bolkiah yang lain yang hendak dikupas seiring dengan adanya pengakuan seorang model asal Los Angeles bernama Rebbeca Ferratti kepada Melba Newsome dari Majalah Marie Claire. Rebbeca mengaku pernah menjadi “harem” (selir) Pangeran Jefri dengan gaji puluhan ribu dollar. Yang menghebohkan lagi, selain dirinya, masih ada 69 harem (selir) Pangeran Jefri plus empat istri resmi sang pangeran.
Istilah “harem” yang dipakai Rebbeca untuk menyebut dirinya bersama 69 selir Pangeran Jefri inilah yang menarik untuk dicermati. Tepatkah istilah “harem” itu dipakai untuk melihat kasus Rebbeca? Adakah implikasi teologis-politis penyebutan “harem” yang berkonotasi Arab? Di atas segalanya, untuk mendudukkan persoalan, perlu kiranya kita merefer karya Fatima Mernissi tentang The Dream of Trespass yang diterjemahkan dalam Edisi Bahasa Indonesia menjadi Teras Terlarang. Buku terbitan Mizan (November, 1999) ini banyak mengupas sisi-sisi kehidupan di dalam harem yang langsung dilakoni oleh sang penulisnya sendiri.
Sebagai seorang akademisi, Mernissi telah sekian lama merebut perhatian para aktivis perempuan dan peminat gender melalui buku-bukunya seperti Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in Modern Moslem Society— yang aslinya adalah disertasi doktornya, The Veil and the Male Elite dan seabrek buku lainnya yang—alhamdulillah— sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia.
Dari tulisan-tulisannya, sedikit atau banyak kita dapat menarik benang merah untaian pemikiran Mernisi sekitar feminisme: Yakni betapa gigihnya dia menelisik kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintahan Arab —yang menurutnya— bukanlah intrinsik karena doktrin agama. Namun, lebih karena agama itu telah dimanipulasi oleh orang yang berkuasa untuk kepentingan dirinya sendiri. Mernissi rela “mewakafkan” sebagian besar usianya untuk melakukan penggalian arkeologis dengan membuka-buka teks agama dan mengakrabi ruang-ruang perpustakaan. Dengan maksud, tentu saja, untuk membuktikan hipotesis dia tentang intervensi budaya patriarkhat dalam teks-teks sakral yang bersifat misoginis
Tapi, satu hal yang agak berbeda pada buku ini dari buku-buku Mernissi yang lain adalah “keengganannya” untuk masuk lebih dalam lagi pada arena debat kusir teologis tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Persoalan feminisme dalam Islam tidaklah harus melulu serius mengagendakan perlu tidaknya penghapusan poligami, kesetaraan harta waris, hijab, dan hal-hal lain yang bisa menegakkan bulu alis kaum agamawan konservatif. Mernissi ingin menampilkan area of expert-nya itu dalam tulisan yang ringan-ringan saja alias mudah dicerna.
Oleh karenanya, ia serasa ingin bertutur tentang dirinya. Dan buku yang aslinya berjudul Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood ini memuatnya sekelumit lika-liku perjalanan hidup Fatima Mernissi dari seorang gadis kecil manis yang hidup dalam lingkungan budaya patriarkhi yang diskriminatif sampai pada proses pematangan ideologinya sebagai seorang feminis.
Bak seorang penulis biografi yang piawai, Mernissi menceritakan masa kanak-kanaknya di dalam sebuah harem Fez, yang dilihat dari kacamata seorang gadis muda. “Masa kanak-kanak saya tidaklah seindah dalam buku ini, “tuturnya dengan nada agak getir. Memang sekilas Mernissi tampak menikmati masa kecilnya di dalam harem, tapi ia tetap tidak dapat mengabaikan adanya penindasan di dalamnya.
Seperti pernah diulas Satrio (1994) ketika meresensi buku ini dalam edisi bahasa Inggris, judul The Dreams of Trespass (Impian-impian tentang Keluar Batas) sengaja dipakai karena inilah yang Mernissi ingat tentang apa yang dilakukan kaum perempuan di dalam harem. Mereka melihat ke rentang langit dari dalam lingkungan halaman harem dan memimpikan hal-hal yang sederhana, seperti melangkah bebas di jalan. Ia menulis tentang batas-batas yang mengatur perilaku dalam masyarakat, garis antara laki-laki dan perempuan. Bukankah inovasi besar di dunia ini berawal dari sebuah mimpi yang menggantung?
Mernissi membuat perbedaan antara harem kerajaan (imperial) dan harem tingkat biasa (domestic) (h. 37). Orang Barat biasanya membayangkan harem kelas tinggi, yakni istana-istana yang dimiliki laki-laki yang kaya raya dan berkuasa, yang membeli ratusan wanita budak dan menyimpan mereka dalam lingkungan harem dengan dijaga ketat oleh orang kasim. Harem-harem semacam ini telah lenyap oleh Perang Dunia I, ketika kerajaan Ottoman runtuh dan praktek-praktek itu dilarang oleh penguasa Barat. Mernissi dibesarkan dalam harem tingkat biasa, yakni rumah bertembok anggun, meskipun bukan istana. Rumah ini didiami oleh sebuah keluarga besar dengan maksud mencegah perempuan memiliki kontak dengan dunia luar (Ibid.)
Distingsi kategoris yang dibuat Mernissi tentang harem di atas sebenarnya sangat membantu kita untuk menjernihkan pandangan steriotipikal Barat yang menganggap bahwa para raja Islam di Timur Tengah dan Maghribi (Afrika Utara) masih melanggengkan institusi harem. Dalam bayangan mereka, harem yang berisi selir-selir raja yang berjumlah belasan, bahkan puluhan wanita beserta anak-anaka yang berjumlah puluhan masih bercokol hingga kini. Walhal, harem model imperial seperti itu telah lama punah, sementara harem model domestik tetap ada seiring dengan masih hidupnya “kepercayaan teologis” yang berakar pada faktor kultural untuk menjaga sekaligus memudahkan proses pemantauan terhadap istri-istri dan anak-anak perempuan dari pengaruh luar.
Harem model imperial, dalam wujudnya yang tak jauh beda, sebenarnya bisa kita jumpai di Indonesia, katakanlah di Keraton Solo, misalnya. Secara fisikal-arsitektural, bangunan yang diperuntukkan buat kalangan istri-istri raja itu tentu tampak anggun dan megah, dan merupakan bagian dari institusi keraton secara keseluruhan. Selain secara latent ditujukan untuk membatasi pergaulan istri-istri raja berikut anak-anak mereka dengan dunia luar, bangunan yang boleh juga disebut harem imperial tersebut berguna untuk memisahkan sekaligus membedakan “trah” garis keturunan raja dengan yang lain.
Yang menarik sebagaimana dapat dibaca dalam entri “seclusion” dalam The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, meskipun lekat dengan tradisi masyarakat dan nilai keislaman, pemisahan ruang antara kedua jenis kelamin itu ternyata bukan berasal dari Islam sendiri. Masyarakat Bizantium, Kristen Suriah, serta masyarakat pra-Islam di kawasan Mediterania, Mesopotamia, serta Persia, sudah terlebih dahulu mempraktekkan hal ini. (h. x)
Di samping itu, pemisahan ruang ini juga sesuai dengan gagasan yang dipegang oleh suku-suku asli di Timur Tengah yang menghendaki kemurnian darahnya terjaga. Meskipun demikian, Mernissi tak selalu menunjuk institusi harem sebagai cerminan dari “keangkuhan” laki-laki untuk mengendalikan perempuan. Harem dalam buku ini adalah harem domestik yang sebenarnya mirip sebuah keluarga besar (extanded family) tanpa budak maupun kasim. Tapi, apa pun alasannya, karena eksistensi harem yang sengaja diperuntukkan buat pengekangan perempuan dari aktivitas dengandunia luar, maka bagaimana pun juga harem tetaplah sebuah produk institusi budaya patriarkhi yang menindas perempuan.
Tradisi harem yang membatasi perempuan dalam berinteraksi dengan dunia luar ini sebenarnya bisa dijelaskan melalui konsep space yang biasa dikenal dalam literatur antropologi. Dalam hal ini, segregasi yang ketat menyangkut space (ruang) buat laki-laki atau perempuan lebih merujuk pada faktor budaya yang melingkupinya. Dan karenanya, lepas dari tanggung jawab sakralitas teks agama. Meskipun, misalnya, ada teks yang menyebut secara eksplisit batas demarkasi laki-laki dan perempuan, itu tak lebih dari bentuk akomodasi teks agama terhadap kultur budaya lokal (baca: Arab). Kalau kita mengikuti asumsi ini, maka teks-teks suci yang membatasi ruang gerak perempuan—yang kemudian berimplikasi pada penyudutan peran perempuan— bersifat relatif atau nisbi. Atau, meminjam istilah bahasa tafsir (Ulumul Qur’an) disebut dzanniy.
Contoh sederhana bahwa pemisahan laki-laki dan perempuan bisa dibaca lewat konsep space yang berdimensi lokal-kultural adalah hanya pada konteks Arab sajalah, daerah komunitas muslim, yang memiliki batasan ketat pemisahan laki-laki dan perempuan. Di Indonesia misalnya, hampir-hampir tidak ada segregasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dapat beraktivitas bersama, tanpa pemisahan, baik di kampus, kantor, sarana transportasi umum dan lain-lain. Hanya WC dan kamar mandi saja yang terpisah.
Namun di atas segalanya, kehidupan masa kecil Mernissi di lingkungan harem malah mematangkan visinya sehingga ia berhasil menjadi scholar kaliber international yang sangat dihormati. Menarik disimak, yakni tumbuhnya benih-benih kritisisme Mernissi justru ketika ia mendapat kungkungan yang kuat. Itu merupakan pesan berharga bahwa “penjara” seketat apa pun tidak bakal mampu mengerdilkan pemikiran seseorang. Hanya tubuhnya saja yang terbelenggu. Bukankah Raden Ajeng Kartini besar karena pikiran-pikirannya yang —tertuang dalam lipatan surat kepada Abendanon, sahabatnya—ternyata mampu menerobos kungkungan tradisi yang melingkupinya dan mampu melampaui zamannya?
“Bagaimanapun banyaknya keterbatasan Anda, Anda selalu bisa memiliki impian dan visi. Jika Anda berpegang pada hal itu, Anda bisa mengubah dunia. Itulah cerita saya, “ujar Mernisi. Dus, melalui buku ini, Mernissi tidak saja mampu mendeskripsikan ketertindasan perempuan secara apik, tapi ia juga memiliki semangat liberatif dan transformatif untuk mengubahnya.
Sebagai epilog, boleh saya katakan bahwa buku ini niscaya sayang seribu sayang apabila dilewatkan begitu saja oleh para peminat kajian gender dan aktivis perempuan. Selamat Membaca! []
Burhanuddin
Redaktur Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dan alumnus Tafsir Hadis IAIN Syarif Hidayatullah
Ada yang menarik dari rubrik “Kisah” berjudul Pengakuan “Selir” Pangeran Jefri dalam Media Indonesia edisi Minggu, 4/6/2000. Kisah ini mirip cerita 1001 malam, demikian Media mengawali beritanya. Kehidupan seorang pangeran; bergelimang uang, hidup mewah dan dikelilingi wanita-wanita cantik yang siap menghibur “luar-dalam.” Ya, benar, laporan tersebut membicarakan seorang pangeran flamboyan nan kaya raya bernama Pangeran Jefri Bolkiah, anggota kerajaan Brunei Darussalam.
Bukan kekayaan dan hobi pangeran yang suka pesta itu yang dijadikan satu-satunya sasaran tembak. Tapi “kesukaan” Pangeran Jefri Bolkiah yang lain yang hendak dikupas seiring dengan adanya pengakuan seorang model asal Los Angeles bernama Rebbeca Ferratti kepada Melba Newsome dari Majalah Marie Claire. Rebbeca mengaku pernah menjadi “harem” (selir) Pangeran Jefri dengan gaji puluhan ribu dollar. Yang menghebohkan lagi, selain dirinya, masih ada 69 harem (selir) Pangeran Jefri plus empat istri resmi sang pangeran.
Istilah “harem” yang dipakai Rebbeca untuk menyebut dirinya bersama 69 selir Pangeran Jefri inilah yang menarik untuk dicermati. Tepatkah istilah “harem” itu dipakai untuk melihat kasus Rebbeca? Adakah implikasi teologis-politis penyebutan “harem” yang berkonotasi Arab? Di atas segalanya, untuk mendudukkan persoalan, perlu kiranya kita merefer karya Fatima Mernissi tentang The Dream of Trespass yang diterjemahkan dalam Edisi Bahasa Indonesia menjadi Teras Terlarang. Buku terbitan Mizan (November, 1999) ini banyak mengupas sisi-sisi kehidupan di dalam harem yang langsung dilakoni oleh sang penulisnya sendiri.
Sebagai seorang akademisi, Mernissi telah sekian lama merebut perhatian para aktivis perempuan dan peminat gender melalui buku-bukunya seperti Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in Modern Moslem Society— yang aslinya adalah disertasi doktornya, The Veil and the Male Elite dan seabrek buku lainnya yang—alhamdulillah— sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia.
Dari tulisan-tulisannya, sedikit atau banyak kita dapat menarik benang merah untaian pemikiran Mernisi sekitar feminisme: Yakni betapa gigihnya dia menelisik kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintahan Arab —yang menurutnya— bukanlah intrinsik karena doktrin agama. Namun, lebih karena agama itu telah dimanipulasi oleh orang yang berkuasa untuk kepentingan dirinya sendiri. Mernissi rela “mewakafkan” sebagian besar usianya untuk melakukan penggalian arkeologis dengan membuka-buka teks agama dan mengakrabi ruang-ruang perpustakaan. Dengan maksud, tentu saja, untuk membuktikan hipotesis dia tentang intervensi budaya patriarkhat dalam teks-teks sakral yang bersifat misoginis
Tapi, satu hal yang agak berbeda pada buku ini dari buku-buku Mernissi yang lain adalah “keengganannya” untuk masuk lebih dalam lagi pada arena debat kusir teologis tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Persoalan feminisme dalam Islam tidaklah harus melulu serius mengagendakan perlu tidaknya penghapusan poligami, kesetaraan harta waris, hijab, dan hal-hal lain yang bisa menegakkan bulu alis kaum agamawan konservatif. Mernissi ingin menampilkan area of expert-nya itu dalam tulisan yang ringan-ringan saja alias mudah dicerna.
Oleh karenanya, ia serasa ingin bertutur tentang dirinya. Dan buku yang aslinya berjudul Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood ini memuatnya sekelumit lika-liku perjalanan hidup Fatima Mernissi dari seorang gadis kecil manis yang hidup dalam lingkungan budaya patriarkhi yang diskriminatif sampai pada proses pematangan ideologinya sebagai seorang feminis.
Bak seorang penulis biografi yang piawai, Mernissi menceritakan masa kanak-kanaknya di dalam sebuah harem Fez, yang dilihat dari kacamata seorang gadis muda. “Masa kanak-kanak saya tidaklah seindah dalam buku ini, “tuturnya dengan nada agak getir. Memang sekilas Mernissi tampak menikmati masa kecilnya di dalam harem, tapi ia tetap tidak dapat mengabaikan adanya penindasan di dalamnya.
Seperti pernah diulas Satrio (1994) ketika meresensi buku ini dalam edisi bahasa Inggris, judul The Dreams of Trespass (Impian-impian tentang Keluar Batas) sengaja dipakai karena inilah yang Mernissi ingat tentang apa yang dilakukan kaum perempuan di dalam harem. Mereka melihat ke rentang langit dari dalam lingkungan halaman harem dan memimpikan hal-hal yang sederhana, seperti melangkah bebas di jalan. Ia menulis tentang batas-batas yang mengatur perilaku dalam masyarakat, garis antara laki-laki dan perempuan. Bukankah inovasi besar di dunia ini berawal dari sebuah mimpi yang menggantung?
Mernissi membuat perbedaan antara harem kerajaan (imperial) dan harem tingkat biasa (domestic) (h. 37). Orang Barat biasanya membayangkan harem kelas tinggi, yakni istana-istana yang dimiliki laki-laki yang kaya raya dan berkuasa, yang membeli ratusan wanita budak dan menyimpan mereka dalam lingkungan harem dengan dijaga ketat oleh orang kasim. Harem-harem semacam ini telah lenyap oleh Perang Dunia I, ketika kerajaan Ottoman runtuh dan praktek-praktek itu dilarang oleh penguasa Barat. Mernissi dibesarkan dalam harem tingkat biasa, yakni rumah bertembok anggun, meskipun bukan istana. Rumah ini didiami oleh sebuah keluarga besar dengan maksud mencegah perempuan memiliki kontak dengan dunia luar (Ibid.)
Distingsi kategoris yang dibuat Mernissi tentang harem di atas sebenarnya sangat membantu kita untuk menjernihkan pandangan steriotipikal Barat yang menganggap bahwa para raja Islam di Timur Tengah dan Maghribi (Afrika Utara) masih melanggengkan institusi harem. Dalam bayangan mereka, harem yang berisi selir-selir raja yang berjumlah belasan, bahkan puluhan wanita beserta anak-anaka yang berjumlah puluhan masih bercokol hingga kini. Walhal, harem model imperial seperti itu telah lama punah, sementara harem model domestik tetap ada seiring dengan masih hidupnya “kepercayaan teologis” yang berakar pada faktor kultural untuk menjaga sekaligus memudahkan proses pemantauan terhadap istri-istri dan anak-anak perempuan dari pengaruh luar.
Harem model imperial, dalam wujudnya yang tak jauh beda, sebenarnya bisa kita jumpai di Indonesia, katakanlah di Keraton Solo, misalnya. Secara fisikal-arsitektural, bangunan yang diperuntukkan buat kalangan istri-istri raja itu tentu tampak anggun dan megah, dan merupakan bagian dari institusi keraton secara keseluruhan. Selain secara latent ditujukan untuk membatasi pergaulan istri-istri raja berikut anak-anak mereka dengan dunia luar, bangunan yang boleh juga disebut harem imperial tersebut berguna untuk memisahkan sekaligus membedakan “trah” garis keturunan raja dengan yang lain.
Yang menarik sebagaimana dapat dibaca dalam entri “seclusion” dalam The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, meskipun lekat dengan tradisi masyarakat dan nilai keislaman, pemisahan ruang antara kedua jenis kelamin itu ternyata bukan berasal dari Islam sendiri. Masyarakat Bizantium, Kristen Suriah, serta masyarakat pra-Islam di kawasan Mediterania, Mesopotamia, serta Persia, sudah terlebih dahulu mempraktekkan hal ini. (h. x)
Di samping itu, pemisahan ruang ini juga sesuai dengan gagasan yang dipegang oleh suku-suku asli di Timur Tengah yang menghendaki kemurnian darahnya terjaga. Meskipun demikian, Mernissi tak selalu menunjuk institusi harem sebagai cerminan dari “keangkuhan” laki-laki untuk mengendalikan perempuan. Harem dalam buku ini adalah harem domestik yang sebenarnya mirip sebuah keluarga besar (extanded family) tanpa budak maupun kasim. Tapi, apa pun alasannya, karena eksistensi harem yang sengaja diperuntukkan buat pengekangan perempuan dari aktivitas dengandunia luar, maka bagaimana pun juga harem tetaplah sebuah produk institusi budaya patriarkhi yang menindas perempuan.
Tradisi harem yang membatasi perempuan dalam berinteraksi dengan dunia luar ini sebenarnya bisa dijelaskan melalui konsep space yang biasa dikenal dalam literatur antropologi. Dalam hal ini, segregasi yang ketat menyangkut space (ruang) buat laki-laki atau perempuan lebih merujuk pada faktor budaya yang melingkupinya. Dan karenanya, lepas dari tanggung jawab sakralitas teks agama. Meskipun, misalnya, ada teks yang menyebut secara eksplisit batas demarkasi laki-laki dan perempuan, itu tak lebih dari bentuk akomodasi teks agama terhadap kultur budaya lokal (baca: Arab). Kalau kita mengikuti asumsi ini, maka teks-teks suci yang membatasi ruang gerak perempuan—yang kemudian berimplikasi pada penyudutan peran perempuan— bersifat relatif atau nisbi. Atau, meminjam istilah bahasa tafsir (Ulumul Qur’an) disebut dzanniy.
Contoh sederhana bahwa pemisahan laki-laki dan perempuan bisa dibaca lewat konsep space yang berdimensi lokal-kultural adalah hanya pada konteks Arab sajalah, daerah komunitas muslim, yang memiliki batasan ketat pemisahan laki-laki dan perempuan. Di Indonesia misalnya, hampir-hampir tidak ada segregasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dapat beraktivitas bersama, tanpa pemisahan, baik di kampus, kantor, sarana transportasi umum dan lain-lain. Hanya WC dan kamar mandi saja yang terpisah.
Namun di atas segalanya, kehidupan masa kecil Mernissi di lingkungan harem malah mematangkan visinya sehingga ia berhasil menjadi scholar kaliber international yang sangat dihormati. Menarik disimak, yakni tumbuhnya benih-benih kritisisme Mernissi justru ketika ia mendapat kungkungan yang kuat. Itu merupakan pesan berharga bahwa “penjara” seketat apa pun tidak bakal mampu mengerdilkan pemikiran seseorang. Hanya tubuhnya saja yang terbelenggu. Bukankah Raden Ajeng Kartini besar karena pikiran-pikirannya yang —tertuang dalam lipatan surat kepada Abendanon, sahabatnya—ternyata mampu menerobos kungkungan tradisi yang melingkupinya dan mampu melampaui zamannya?
“Bagaimanapun banyaknya keterbatasan Anda, Anda selalu bisa memiliki impian dan visi. Jika Anda berpegang pada hal itu, Anda bisa mengubah dunia. Itulah cerita saya, “ujar Mernisi. Dus, melalui buku ini, Mernissi tidak saja mampu mendeskripsikan ketertindasan perempuan secara apik, tapi ia juga memiliki semangat liberatif dan transformatif untuk mengubahnya.
Sebagai epilog, boleh saya katakan bahwa buku ini niscaya sayang seribu sayang apabila dilewatkan begitu saja oleh para peminat kajian gender dan aktivis perempuan. Selamat Membaca! []
Burhanuddin
Redaktur Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dan alumnus Tafsir Hadis IAIN Syarif Hidayatullah

keroncong- KAPTEN
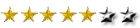
-

Age : 70
Posts : 4535
Kepercayaan : Islam
Location : di rumah saya
Join date : 09.11.11
Reputation : 67
 Similar topics
Similar topics» konsep kebahagiaan dan kesengsaraan
» kepribadian fatimah az zahra
» konsep baitul mal
» KONSEP ALLAH YANG ESA
» konsep teologis dalam beragama
» kepribadian fatimah az zahra
» konsep baitul mal
» KONSEP ALLAH YANG ESA
» konsep teologis dalam beragama
Halaman 1 dari 1
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik


