pemberdayaan politik ummat
Halaman 1 dari 1 • Share
 pemberdayaan politik ummat
pemberdayaan politik ummat
Baik karena substansi ajarannya mau pun karena jumlah penganutnya Islam dan umat Islam secara otomatis telah menjadi kekuatan politik tersendiri. Elaborasi di bawah ini berusaha memaparkan pernyataan hipotesis di atas, yang dimulai dengan tinjauan aspek substansi ajaran kemasyarakatannya. Melalui substansi ajaran Islam tentang perkauman, kita menemukan konsep ummatan wahidah. Lepas dari pengertian lainnya, konsep di atas mengandung elemen ideologis. Kendati pun secara harfiah ummatan wahidah bisa diterjemahkan sebagai “kesatuan komunitas” atau “komunitas yang satu”, secara konseptual gagasan tersebut bermakna lebih dalam daripada hanya kumpulan fisik. Melalui konsep ummatan wahidah struktur fisik komunitas Islam secara spritual mengalami peneguhan teologis: bahwa kesatuan yang dimaksud harus didasarkan pada persamaan imani —bukan karena persamaan kepentingan material. Ummatan wahidah, dengan demikian, lebih dihayati sebagai sebuah “persekutuan suci” yang bersifat distinktif —dan karenanya niscaya berbeda dengan kesatuan-kesatuan lainnya. Konsekuensi teoritis ummatan wahidah ini adalah bahwa segala perbedaan di antara sub-sub kelompok di dalamnya, atau, seperti dinyatakan Halliday dan Alavi, “different socieities and distinct historical epochs,”[2] harus dilebur dan ditransendensikan.
Dalam konteks antropologi, karakteristik kesatuan yang begitu khusus ini hanya mungkin terjadi karena bekerjanya sacred symbols (simbol-simbol suci) yang mengikat mereka bersama. Operasionalisasi dari the biding force of these sacred symbols ini terejawantahkan pada kemunculan sintesa antara etos (ethos) dan pandangan hidup (world view) yang spesifik di kalangan pemeluk agama tertentu. Antropolog Clifford Geertz melihat etos sebagai “sifat, karakter dan kualitas kehidupan pemeluk, wujud moral, estetika dan suasana jiwa.” Sedangkan pandangan hidup dilukiskan sebagai “gambaran yang dimiliki para pemeluk tentang keadaan yang sebenarnya, gagasan paling komprehensif mereka tentang tatanan kehidupan.”[3]
Apa yang penting ditekankan di sini adalah sintesa dan saling menguatkan antara etos dan pandangan hidup yang terbentuk melalui ajaran agama ini telah memberi arti paling distinktif dalam konteks konsep ummatan wahidah di atas. Elaborasi deskripsi Geertz ini membawa pada pengertian bagaimana spesifiknya struktur psikologi dan budaya penganut agama tertentu ketika etos dan pandangan hidup bertemu dan membentuk realitas tersendiri. Di sini Geertz menyatakan bahwa kepercayaan dan praktek keagamaan etos sebuah kelompok dibuat bisa terpahami secara intelektual dengan memperlihatkannya sebagai cara hidup yang secara ideal sesuai dengan struktur kejadian nyata (the actual state of affairs) —sebagaimana dilukiskan pandangan hidup. Sementara, pandangan hidup itu sendiri dibuat meyakinkan secara emosional (emotionally convincing) dengan menghadirkannya sebagai citra atau bayangan dari struktur kejadian-kejadian aktual yang secara khusus terkelola baik untuk mengakomodasikan cara hidup semacam itu.[4]
Jika kita kembali kepada konsep ummatan wahidah dalam Islam di atas, maka kombinasi hasil kinerja etos dan pandangan hidup tersebut telah menstrukturkan wujud kesatuan komunitas yang diserukan itu ke dalam bingkai kepaduan yang ketat. Dan dalam karakteristik kesatuan yang begitu khusus inilah struktur ummatan wahidah dengan sendirinya sangat berarti politis dan ideologis. Sebab struktur kesatuan masyarakat tersebut niscaya mengandung daya komando yang besar (the power to command), dan karena itu pula juga berdaya panggil massif terhadap kekuatan massa bagi proses mobilisasi dan pengorbanan. Suatu keadaan yang bagaimana pun juga sarat dengan semangat politik dan kekuasaan. Dalam konteks inilah kita memahami mengapa daya komando ini bisa bertahan untuk rentang waktu yang cukup lama dalam memobilisasikan perlawanan terhadap kaum kolonial, seperti diperlihatkan gerakan kaum sufi atau tarekat Aljazair terhadap imperialisme Perancis.[5] Dan kenyataan ini pula yang memberi dasar, seperti dinyatakan Keyes dan kawan-kawan, mengapa otoritas agama secara terus-menerus menjadi pesaing otoritas negara-negara modern.[6]
II
Dalam konteks Indonesia, karakteristik substansial di atas menjadi lebih signifikan secara politik, semata-mata karena pengikut atau penganut ajaran ini merupakan mayoritas penduduknya. Di mana pun juga, agregasi penduduk dalam jumlah besar senantiasa menggoda secara politik. Godaan ini akan semakin besar karena kemampuan kaum Muslimin mengorganisasikan diri telah teruji dalam sejarah. Sejak awal abad lalu, kemampuan pengorganisasian diri kaum Muslimin ini telah terlihat ketika Sarekat Islam (SI), pada 1912, lahir. Hanya dalam beberapa tahun sejak kelahirannya, seperti dicatat Kahin, SI berhasil mengakumulasi 2,5 juta anggota,[7] sebuah hal yang fantastis dan tampak terlalu modern kala itu, untuk sebuah masyarakat yang struktur kependudukannya masih didominasi lapisan petani. Sifat modern dari kemampuan pengorganisasian diri ini terlihat dari latarbelakang sebagian besar anggota SI yang telah memiliki, apa yang disebut Wertheim, bourgeois traits, dan karenanya mempunyai visi kesadaran kelas. Di samping berusaha mengeliminasikan pengaruh kaum feodal dan pemimpin-pemimpin pribumi tradisional, SI juga mengarahkan aksinya menentang dominasi raksasa kapitalis Barat.[8]
Lepas dari berbagai penafsiran lainnya, kita bisa meletakkan Masyumi (lahir 7 November 1945) sebagai kelanjutan kemampuan pengorganisasian diri kaum Muslimin secara politik, setelah kemerdekaan. Sebagai saluran politik tunggal bagi seluruh faksi-faksi dan aneka golongan Islam, Masyumi “sempat” berkembang menjadi salah satu pilar kekuasaan nasional yang disegani pasca kemerdekaan. Walau menggambarkan kegamangan posisinya secara kultural, Anderson menyebut Natsir, pemimpin puncak Masyumi kala itu, sebagai “the most prestigious Moslem politician of the postindependence period.”[9] Kenyataan ini mendorong Presiden Soekarno —yang berbagi kekhawatiran dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) terhadap semakin meluasnya pengaruh partai Islam ini— mengecam gagasan Negara Islam dalam pidatonya di Amuntai pada 1952, sebagai upaya mengerem laju perkembangan pengaruh partai politik ini.[10] Dan, seperti halnya dengan SI yang telah memiliki konstituen dari kalangan borjuasi, Masyumi mendapatkan dukungan luas dari kalangan kota, kaum pedagang dan lapisan terdidik Islam. Di atas segala-galanya, Masyumi lebih terlihat sebagai —meminjam istilah Duverger— a party of indirect structure, dalam arti memiliki keanggotaan yang bersifat korporasi (corporate members), di samping keanggotaan individual.[11] Ini berarti konstituen Masyumi telah memiliki kualitas tertentu dalam kemampuan pengorganisasian diri. Sebab dengan memiliki corporate members, telah menyebabkan Masyumi, pada masa itu, menjadi satu-satunya partai politik yang didukung oleh berbagai kalangan —tak kurang dari sebelas organisasi keagamaan, sosial dan pendidikan di mana Muhammadiyah dan NU merupakan yang terpenting.[12]
Namun, yang paling fenomenal dari seluruh gejala kemampuan pengorganisasian diri kalangan Islam ini adalah kehadiran chapter members (anggota utama) Masyumi itu sendiri: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Karena telah hampir menjadi “pengetahuan umum”, tidaklah pada tempatnya memaparkan kembali proses kelahiran dan perkembangan kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam kalam sederhana ini.[13] Apa yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kedua organisasi tersebut, sampai pada taraf tertentu, tidak melibatkan diri ke dalam dunia politik secara langsung.[14] Meski pun demikian, melalui gerakan dan pengaruh sosial-keagamaan mereka yang meluas, keduanya telah mengambil peran yang jauh lebih besar daripada sosok fisik masing-masing organisasi tersebut. Muhammadiyah, di satu pihak, yang lahir dan menjalarkan pengaruhnya di wilayah perkotaan, telah berperan sebagai penyebar gagasan negara modern Indonesia di kalangan kaum terdidik, antara lain, melalui pembiasaan membuat laporan-laporan dan publikasi organisasi dalam bahasa Indonesia di masa kolonial.[15] NU, yang memiliki akar pengaruh di kalangan massa pedesaan, di pihak lain, melalui para kiai, telah bertindak sebagai cultural brokers —menggunakan istilah Geertz— yang menerjemahkan gagasan-gagasan abstrak tentang politik modern dan arti negara-bangsa kepada kalangan luas yang umumnya “tak terdidik” di awal kemerdekaan.[16] Tanpa fungsi brokerage mereka, proses sosialisasi konsep “Indonesia” yang diperkenalkan kaum intelegensia —tetapi pada umumnya terasing dari masyarakat, karena lebih fasih berbahasa Belanda daripada bahasa Indonesia,[17] apa lagi bahasa lokal— terlalu lama untuk tertanam dalam sistem kognisi massa jelata yang terbelakang.
Dengan mendeskripsikan peranan Muhammadiyah dan NU dalam histoire mentalitè (sejarah kesadaran) masyarakat Indonesia, kita ingin menekankan bahwa keduanya lebih berhasil memainkan “peran politik” —daripada partai-partai politik Islam itu sendiri— tanpa menjadi organisasi politik secara resmi. Kendati pun harus disadari bahwa partai-partai politik Islam telah menjadi “wakil kaum Muslim” dalam permainan kekuasaan pada tingkat negara —dan karenanya tak terbayangkan nasib politik umat Islam tanpa kesempatan mereka berkinerja di parlemen, misalnya— namun dalam konteks wacana, publik jauh lebih mendengar seruan-seruan moral dan intelektual Muhammadiyah dan NU, daripada kekuatan-kekuatan politik resmi. Dan jika disadari bahwa dalam kenyataannya Muhammadiyah dan NU bukan saja hadir jauh lebih awal, melainkan memiliki nafas kehidupan yang juga jauh lebih panjang dari partai-partai politik Islam, maka kedua organisasi nonpolitik ini, telah terbukti dalam sejarah sebagai kenderaan yang cocok bagi wahana pemberdayaan politik umat Islam.
Dengan kalimat terakhir di atas kita ingin menyatakan bahwa pembahasan tentang pemberdayaan politik umat Islam tidaklah hanya bertumpu pada organisasi politik resmi. Bahwa di dalam kenyataannya, aksi-aksi politik yang distrukturkan oleh ideologi Islam —lepas dari aneka persepsi tentangnya— cenderung “berumur pendek”. Untuk sebagian, kenyataan ini dapat dijelaskan dengan logika sederhana, bahwa sekali sekelompok agama memasuki wilayah politik resmi, maka sekali itu mereka telah memasuki “wilayah peperangan”. Hukum besi peperangan hanya menawarkan satu alternatif: Anda akan survive jika Anda keluar sebagai pemenang! Dan, seperti diperlihatkan dalam sejarah, hukum besi tersebut tidak atau belum berpihak kepada Islam politik.[18] Dalam konteks inilah Muhammadiyah dan NU menjadi saluran alternatif proses pemberdayaan politik umat Islam —tanpa harus terjun ke duania politik secara resmi.
III
Akan tetapi harus cepat-cepat dikatakan di sini bahwa survivalitas Muhammadiyah dan NU pada dasarnya adalah karena keduanya menghindari “wilayah peperangan” itu. Dan karena itu pula “nafas panjang” Muhammadiyah dan NU pada intinya tidak substansial. Apa yang untuk sementara kita catat adalah bahwa keduanya hanya mampu bertahan, dan gagal memperluas pengaruhnya secara lebih monumental. Konsentrasi yang melulu terfokus pada wujud diri dan lingkungan sejarah, telah memberikan kontribusi besar akan tak ekspansifnya peran Muhammadiyah dan NU secara lebih substansial —karena sementara ini hanya mampu memberikan reaksi terhadap sinyal-sinyal tantangan yang datang dari luar diri mereka.
Kendati pun demikian, peluang untuk “menang” secara substansial dalam proses pemberdayaan politik umat bukan tak bercelah. Salah satu celah yang terkuak terletak pada fakta bahwa wilayah politik yang substansial tak lagi tergambar dalam bentuk peta masa lampau. Peta baru politik dewasa ini ditandai oleh tiga hal paling pokok. Pertama, munculnya sebuah kenyataan yang agak kontradiktif: melemahnya kekuatan negara tanpa diimbangi oleh munculnya organisasi kemasyarakatan yang kuat, yang menyebabkan, seperti dinyatakan Goenawan Mohamad, politik nasional telah menjadi “a competition between disconnected desires.”[19] Kedua, semakin besarnya pengaruh-pengaruh kekuatan internasional ke dalam percaturan politik domestik. Ketiga, semakin tergantungnya survivalitas sebuah rezim pada tingkat domestik terhadap preferensi aktor-aktor ekonomi transnasional.[20] Ketiga variabel di atas bekerja secara simbiosis membentuk struktur atau susunan-susunan kekuatan politik baru pada tingkat nasional —walau formatnya belum terlihat dengan mapan.
Tentu saja, dua variabel terbawah telah menjadi masalah besar, yang bahkan untuk sebuah negara adijaya seperti Amerika Serikat sekali pun tak mampu mengatasinya.[21] Akan tetapi untuk variabel pertama di atas, Muhammadiyah dan NU bisa memainkan peranan besar. Dalam situasi di mana negara tak lagi mampu berartikulasi dengan maksimal, sementara old social control, meminjam istilah Migdal,[22] tak lagi mempunyai daya, kedua organisasi ini justru bisa berperan sebagai kekuatan civil society yang signifikan. Situasi lemahnya baik negara maupun sistem kontrol sosial tradisional telah menimbulkan kekaburan orientasi dan tatanan kemasyarakatan, di mana kekuatan-kekuatan sosial-politik, ekonomi dan budaya bergerak tanpa arah. Maka, persis seperti dimiliki kaum militer, hanya Muhammadiyah dan NU-lah yang mempunyai kekuatan lebih terorganisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, keduanya secara potensial bisa tampil sebagai the leading groups dalam proses restrukturisasi pelataran keidupan sosial-budaya dan politik—di atas mana, negara dan kelompok-kelompok masyarakat berkinerja.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan NU bisa bertindak sebagai wakil kekuatan-kekuatan nonnegara yang otoritatif, baik dalam berhadapan dengan negara pada tingkat domestik mau pun kekuatan-kekuatan “supra” pada tingkat internasional. Untuk sementara, potensi semacam ini telah mulai terlihat. Di satu pihak, sebagaimana telah disinggung di atas, suara-suara Muhammadiyah dan NU jauh dianggap mempunyai otoritas moral dan intelektual dibandingkan dengan hampir semua kekuatan-kekuatan politik resmi di Indonesia. Di pihak lain, walau tetap untuk kepentingan domestik Indonesia, suara keduanya bukan hanya telah juga menjadi referensi pada tingkat duta besar negara-negara Barat —yang datang berkunjung dan berdialog. Melainkan juga telah menarik perhatian menteri luar negeri Inggris dengan mendatangi dan membeberkan rencana dan visi negara-negara “penguasa dunia” (Amerika dan Inggris) kepada mereka —walau untuk sementara, masih terbatas pada urusan perang melawan rezim Saddam Hussen dari Irak.
Jika Muhammadiyah dan NU berhasil mengarungi peran baru ini, maka akibat-akibat positifnya jelas jauh lebih strategis dan bermakna serta lebih substansial bagi proses pemberdayaan politik umat Islam. Sebab aktivitas “politik” semacam ini tak lagi menyangkut persoalan kepentingan kekuasaan dalam pengertian harfiah. Melainkan menyangkut kepentingan kelanjutan demokrasi dan keselamatan kemanusiaan secara keseluruhan.
Catatan Akhir:
[1] Pernah disampaikan dalam program Diskusi Serial bidang Politik International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 16 Januari 2003.
[2] Fred Halliday dan Hamzah Alavi, “Introduction”, untuk buku suntingan mereka, State and Ideology in the Middle-East and Pakistan (houndmills, Basingstoke, Hampshire RG 21 2XS and London: McMillan Education, 1988), hlm. 2.
[3] Clifford Geertz, “Religion As a Cultural System”, dalam Clifford Geertz, The Interpretation of (London: Fontana Press, 1993), hlm. 89
[4] Geertz, Religion As…,” hlm. 90.
[5] Lihat, misalnya, Julia Clancy-Smith, Saints, Mahdis and Arms: Religion and Resistance in Nineteenth-Century North Africa”, dalam Edmund Burke, III, dan Ira M. Lapidus, (peny.), Islam, Politics, and Social Movements (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1988), hlm. 60-80.
[6] Charles F. Keyes, Hellen Hardacre, dan Laurel Kendall, “Contested Visions of Community in East and Southeast Asia”, dalam buku suntingan mereka, Asian Visions of Authority, Religion and the Modern State of East and Southeast Asia (Honolulu: University of Hawaii Press, 1944), hlm. 1-18.
[7] George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1970, hlm. 66.
[8] W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change (Bandung: Sumur Bandung, Edisi Kedua, 1956), hlm. 185.
[9] Lihat Benedict R’OG Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culuture”, dalam buku kumpulan karangannya, Language and Power. Exploring Political Culture in Indonesia (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1990), hlm. 72. Lihat terutama catatan kaki no. 108.
[10] Tentang efek dari pidato ini, lihat Boyd R. Compton, Kemelut Demokrasi Liberal. Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton (Jakarta: LP3ES, 1992). Terutama lihat “Presiden Sukarno dan Negara Islam”, hlm. 121-133.
[11] Di sini, Duverger menunjuk partai-partai berorientasi Sosialisme dan yang berorientasi Katolik sebagai contoh party of indirect structure. Keduanya dianggotai oleh berbagai organisasi buruh, pedagang dan lainnya, untuk partai-partai sosialis, dan organisasi-organisasi keagamaan untuk partai-partai Katolik. Lihat Maurice Duverger, Political Parties (London: Metheun & Co., 1964), hlm. 6.
[12] Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Itacha, New York: Cornell University Press, 1962), hlm. 134-135.
[13] Penjelasan lebih lengkap tentang ini, lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980). Lihat juga Alfian, Muhammadiyah. The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation under Dutch Colonialism (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989). Lihat juga H. A. Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa (Ciputat: Logos, 1999). Lihat juga Marzuki Wahid, et al, (peny.) Geger di Republik NU. Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna (Jakarta: Kompas dan LAKPESDAM-NU, 1999).
[14] Setelah Masyumi dibubarkan pada awal 1960-an, Muhammadiyah secara resmi “mengundurkan diri” dari dunia politk. Dan kendati pun pada 1952 NU memisahkan diri dari Masyumi untuk menjadi partai politik tersendiri, namun sejak 1973, NU kembali menjadi organisasi nonpolitik hingga dewasa ini.
[15] Tentang hal ini, lihat, antara lain, Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree. Study of the Muhammadiyah Movement in a Central javanese Town (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983).
[16] Tentang hal ini, lihat Clifford Geertz, “Javanese Kiyayi: the Changing Role of Cultural Broker”, Comparative Studies in Society and History, No.2,1960.
[17] Bahkan sampai 1952, kaum intelegensia masih tergagap-gagap menggunakan bahasa Indonesia dalam sebuah percakapan “akademis”. Sjahrir, misalnya, menyatakan dalam percakapan itu: “Bahasa Indonesia jang kita gunakan malam ini tiada pula memudahkan tertjiptanja maksud kita untuk membentuk pengertian bersama… Untuk sementara, tampaknja kekeruhan pengertian jang disebabkan oleh penggunaan bahasa kita sendiri di dalam dunia berfikir abstak tadi hanja akan dapat dihilangkan dengan mengulangkan apa jang hendak kita katakan dalam salah satu bahasa Barat, yang telah biasa digunakan untuk itu.” Lihat St. Sjahrir, “Kesulitan-kesulitan dalam Masa Peralihan Sekarang Ditilik dari Sudut Sosiologi”, dalam Simposium tentang Kesulitan-kesulitan Zaman Peralihan Sekarang (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hlm. 75. Huruf miring adalah tambahan.
[18] Mungkin juga karena sifat agrarisnya, gerakan-gerakan politik dengan mengatasnamakan Islam tak pernah survive dalam “wilayah peperangan” ini, seperti diperlihatkan pemberontakan-pemberontakan petani dengan menggunakan “ideologi” Islam. Betapa pun tak ringkas dalam rentang waktu, toh akhirnya pemberontakan pedesaan Aljazair akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20—yang dilecut oleh sistem perpajakan kolonial Prancis dan akibat-akibat dislokasi sosial-budaya lainnya—tak kuasa untuk menang. Lihat Peter Von Sievers, “Rural Uprisings as Political Movements in Colonial Algeria, 1851-1914”. Dalam Burke, III dan Lapidus, Islam, Politics…, hlm. 39-59. ini juga terjadi pada kaum pedesaan Sumatera Barat yang memberontak karena alasan sistem pajak yang sama. Lihat Ken Young, Islamic Peasant and the State. The 1908 Anti-Tax Rebellion in West Sumatra.
[19] Goenawan Mohammad, “Visnu”, dalam Goenawan Mohammad, Conversation with Difference, terj. Jennifer Lindsay (Jakarta: PY Tempo Inti Media, Tbk., 2002) hlm 30.
[20] Pembahasan komprehensif tentang ini, lihat Eric Toussaint, Your Money or Your Life? Tyrany of Global Finance (London et al: Pluto Press, 1999).
[21] Tentang hal in, lihat antara lain, Susane Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World of Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). Lihat juga Philip C. Cerny, (peny.), Finance and World Politics. Markets, Regimes and State in Post-hegemonic Era (Hans GU11 3HR: Edward Elgar Publishing Ltd., 1993).
[22] Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabalities in the Third World (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1988), hlm. 93-96.
Dalam konteks antropologi, karakteristik kesatuan yang begitu khusus ini hanya mungkin terjadi karena bekerjanya sacred symbols (simbol-simbol suci) yang mengikat mereka bersama. Operasionalisasi dari the biding force of these sacred symbols ini terejawantahkan pada kemunculan sintesa antara etos (ethos) dan pandangan hidup (world view) yang spesifik di kalangan pemeluk agama tertentu. Antropolog Clifford Geertz melihat etos sebagai “sifat, karakter dan kualitas kehidupan pemeluk, wujud moral, estetika dan suasana jiwa.” Sedangkan pandangan hidup dilukiskan sebagai “gambaran yang dimiliki para pemeluk tentang keadaan yang sebenarnya, gagasan paling komprehensif mereka tentang tatanan kehidupan.”[3]
Apa yang penting ditekankan di sini adalah sintesa dan saling menguatkan antara etos dan pandangan hidup yang terbentuk melalui ajaran agama ini telah memberi arti paling distinktif dalam konteks konsep ummatan wahidah di atas. Elaborasi deskripsi Geertz ini membawa pada pengertian bagaimana spesifiknya struktur psikologi dan budaya penganut agama tertentu ketika etos dan pandangan hidup bertemu dan membentuk realitas tersendiri. Di sini Geertz menyatakan bahwa kepercayaan dan praktek keagamaan etos sebuah kelompok dibuat bisa terpahami secara intelektual dengan memperlihatkannya sebagai cara hidup yang secara ideal sesuai dengan struktur kejadian nyata (the actual state of affairs) —sebagaimana dilukiskan pandangan hidup. Sementara, pandangan hidup itu sendiri dibuat meyakinkan secara emosional (emotionally convincing) dengan menghadirkannya sebagai citra atau bayangan dari struktur kejadian-kejadian aktual yang secara khusus terkelola baik untuk mengakomodasikan cara hidup semacam itu.[4]
Jika kita kembali kepada konsep ummatan wahidah dalam Islam di atas, maka kombinasi hasil kinerja etos dan pandangan hidup tersebut telah menstrukturkan wujud kesatuan komunitas yang diserukan itu ke dalam bingkai kepaduan yang ketat. Dan dalam karakteristik kesatuan yang begitu khusus inilah struktur ummatan wahidah dengan sendirinya sangat berarti politis dan ideologis. Sebab struktur kesatuan masyarakat tersebut niscaya mengandung daya komando yang besar (the power to command), dan karena itu pula juga berdaya panggil massif terhadap kekuatan massa bagi proses mobilisasi dan pengorbanan. Suatu keadaan yang bagaimana pun juga sarat dengan semangat politik dan kekuasaan. Dalam konteks inilah kita memahami mengapa daya komando ini bisa bertahan untuk rentang waktu yang cukup lama dalam memobilisasikan perlawanan terhadap kaum kolonial, seperti diperlihatkan gerakan kaum sufi atau tarekat Aljazair terhadap imperialisme Perancis.[5] Dan kenyataan ini pula yang memberi dasar, seperti dinyatakan Keyes dan kawan-kawan, mengapa otoritas agama secara terus-menerus menjadi pesaing otoritas negara-negara modern.[6]
II
Dalam konteks Indonesia, karakteristik substansial di atas menjadi lebih signifikan secara politik, semata-mata karena pengikut atau penganut ajaran ini merupakan mayoritas penduduknya. Di mana pun juga, agregasi penduduk dalam jumlah besar senantiasa menggoda secara politik. Godaan ini akan semakin besar karena kemampuan kaum Muslimin mengorganisasikan diri telah teruji dalam sejarah. Sejak awal abad lalu, kemampuan pengorganisasian diri kaum Muslimin ini telah terlihat ketika Sarekat Islam (SI), pada 1912, lahir. Hanya dalam beberapa tahun sejak kelahirannya, seperti dicatat Kahin, SI berhasil mengakumulasi 2,5 juta anggota,[7] sebuah hal yang fantastis dan tampak terlalu modern kala itu, untuk sebuah masyarakat yang struktur kependudukannya masih didominasi lapisan petani. Sifat modern dari kemampuan pengorganisasian diri ini terlihat dari latarbelakang sebagian besar anggota SI yang telah memiliki, apa yang disebut Wertheim, bourgeois traits, dan karenanya mempunyai visi kesadaran kelas. Di samping berusaha mengeliminasikan pengaruh kaum feodal dan pemimpin-pemimpin pribumi tradisional, SI juga mengarahkan aksinya menentang dominasi raksasa kapitalis Barat.[8]
Lepas dari berbagai penafsiran lainnya, kita bisa meletakkan Masyumi (lahir 7 November 1945) sebagai kelanjutan kemampuan pengorganisasian diri kaum Muslimin secara politik, setelah kemerdekaan. Sebagai saluran politik tunggal bagi seluruh faksi-faksi dan aneka golongan Islam, Masyumi “sempat” berkembang menjadi salah satu pilar kekuasaan nasional yang disegani pasca kemerdekaan. Walau menggambarkan kegamangan posisinya secara kultural, Anderson menyebut Natsir, pemimpin puncak Masyumi kala itu, sebagai “the most prestigious Moslem politician of the postindependence period.”[9] Kenyataan ini mendorong Presiden Soekarno —yang berbagi kekhawatiran dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) terhadap semakin meluasnya pengaruh partai Islam ini— mengecam gagasan Negara Islam dalam pidatonya di Amuntai pada 1952, sebagai upaya mengerem laju perkembangan pengaruh partai politik ini.[10] Dan, seperti halnya dengan SI yang telah memiliki konstituen dari kalangan borjuasi, Masyumi mendapatkan dukungan luas dari kalangan kota, kaum pedagang dan lapisan terdidik Islam. Di atas segala-galanya, Masyumi lebih terlihat sebagai —meminjam istilah Duverger— a party of indirect structure, dalam arti memiliki keanggotaan yang bersifat korporasi (corporate members), di samping keanggotaan individual.[11] Ini berarti konstituen Masyumi telah memiliki kualitas tertentu dalam kemampuan pengorganisasian diri. Sebab dengan memiliki corporate members, telah menyebabkan Masyumi, pada masa itu, menjadi satu-satunya partai politik yang didukung oleh berbagai kalangan —tak kurang dari sebelas organisasi keagamaan, sosial dan pendidikan di mana Muhammadiyah dan NU merupakan yang terpenting.[12]
Namun, yang paling fenomenal dari seluruh gejala kemampuan pengorganisasian diri kalangan Islam ini adalah kehadiran chapter members (anggota utama) Masyumi itu sendiri: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Karena telah hampir menjadi “pengetahuan umum”, tidaklah pada tempatnya memaparkan kembali proses kelahiran dan perkembangan kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam kalam sederhana ini.[13] Apa yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kedua organisasi tersebut, sampai pada taraf tertentu, tidak melibatkan diri ke dalam dunia politik secara langsung.[14] Meski pun demikian, melalui gerakan dan pengaruh sosial-keagamaan mereka yang meluas, keduanya telah mengambil peran yang jauh lebih besar daripada sosok fisik masing-masing organisasi tersebut. Muhammadiyah, di satu pihak, yang lahir dan menjalarkan pengaruhnya di wilayah perkotaan, telah berperan sebagai penyebar gagasan negara modern Indonesia di kalangan kaum terdidik, antara lain, melalui pembiasaan membuat laporan-laporan dan publikasi organisasi dalam bahasa Indonesia di masa kolonial.[15] NU, yang memiliki akar pengaruh di kalangan massa pedesaan, di pihak lain, melalui para kiai, telah bertindak sebagai cultural brokers —menggunakan istilah Geertz— yang menerjemahkan gagasan-gagasan abstrak tentang politik modern dan arti negara-bangsa kepada kalangan luas yang umumnya “tak terdidik” di awal kemerdekaan.[16] Tanpa fungsi brokerage mereka, proses sosialisasi konsep “Indonesia” yang diperkenalkan kaum intelegensia —tetapi pada umumnya terasing dari masyarakat, karena lebih fasih berbahasa Belanda daripada bahasa Indonesia,[17] apa lagi bahasa lokal— terlalu lama untuk tertanam dalam sistem kognisi massa jelata yang terbelakang.
Dengan mendeskripsikan peranan Muhammadiyah dan NU dalam histoire mentalitè (sejarah kesadaran) masyarakat Indonesia, kita ingin menekankan bahwa keduanya lebih berhasil memainkan “peran politik” —daripada partai-partai politik Islam itu sendiri— tanpa menjadi organisasi politik secara resmi. Kendati pun harus disadari bahwa partai-partai politik Islam telah menjadi “wakil kaum Muslim” dalam permainan kekuasaan pada tingkat negara —dan karenanya tak terbayangkan nasib politik umat Islam tanpa kesempatan mereka berkinerja di parlemen, misalnya— namun dalam konteks wacana, publik jauh lebih mendengar seruan-seruan moral dan intelektual Muhammadiyah dan NU, daripada kekuatan-kekuatan politik resmi. Dan jika disadari bahwa dalam kenyataannya Muhammadiyah dan NU bukan saja hadir jauh lebih awal, melainkan memiliki nafas kehidupan yang juga jauh lebih panjang dari partai-partai politik Islam, maka kedua organisasi nonpolitik ini, telah terbukti dalam sejarah sebagai kenderaan yang cocok bagi wahana pemberdayaan politik umat Islam.
Dengan kalimat terakhir di atas kita ingin menyatakan bahwa pembahasan tentang pemberdayaan politik umat Islam tidaklah hanya bertumpu pada organisasi politik resmi. Bahwa di dalam kenyataannya, aksi-aksi politik yang distrukturkan oleh ideologi Islam —lepas dari aneka persepsi tentangnya— cenderung “berumur pendek”. Untuk sebagian, kenyataan ini dapat dijelaskan dengan logika sederhana, bahwa sekali sekelompok agama memasuki wilayah politik resmi, maka sekali itu mereka telah memasuki “wilayah peperangan”. Hukum besi peperangan hanya menawarkan satu alternatif: Anda akan survive jika Anda keluar sebagai pemenang! Dan, seperti diperlihatkan dalam sejarah, hukum besi tersebut tidak atau belum berpihak kepada Islam politik.[18] Dalam konteks inilah Muhammadiyah dan NU menjadi saluran alternatif proses pemberdayaan politik umat Islam —tanpa harus terjun ke duania politik secara resmi.
III
Akan tetapi harus cepat-cepat dikatakan di sini bahwa survivalitas Muhammadiyah dan NU pada dasarnya adalah karena keduanya menghindari “wilayah peperangan” itu. Dan karena itu pula “nafas panjang” Muhammadiyah dan NU pada intinya tidak substansial. Apa yang untuk sementara kita catat adalah bahwa keduanya hanya mampu bertahan, dan gagal memperluas pengaruhnya secara lebih monumental. Konsentrasi yang melulu terfokus pada wujud diri dan lingkungan sejarah, telah memberikan kontribusi besar akan tak ekspansifnya peran Muhammadiyah dan NU secara lebih substansial —karena sementara ini hanya mampu memberikan reaksi terhadap sinyal-sinyal tantangan yang datang dari luar diri mereka.
Kendati pun demikian, peluang untuk “menang” secara substansial dalam proses pemberdayaan politik umat bukan tak bercelah. Salah satu celah yang terkuak terletak pada fakta bahwa wilayah politik yang substansial tak lagi tergambar dalam bentuk peta masa lampau. Peta baru politik dewasa ini ditandai oleh tiga hal paling pokok. Pertama, munculnya sebuah kenyataan yang agak kontradiktif: melemahnya kekuatan negara tanpa diimbangi oleh munculnya organisasi kemasyarakatan yang kuat, yang menyebabkan, seperti dinyatakan Goenawan Mohamad, politik nasional telah menjadi “a competition between disconnected desires.”[19] Kedua, semakin besarnya pengaruh-pengaruh kekuatan internasional ke dalam percaturan politik domestik. Ketiga, semakin tergantungnya survivalitas sebuah rezim pada tingkat domestik terhadap preferensi aktor-aktor ekonomi transnasional.[20] Ketiga variabel di atas bekerja secara simbiosis membentuk struktur atau susunan-susunan kekuatan politik baru pada tingkat nasional —walau formatnya belum terlihat dengan mapan.
Tentu saja, dua variabel terbawah telah menjadi masalah besar, yang bahkan untuk sebuah negara adijaya seperti Amerika Serikat sekali pun tak mampu mengatasinya.[21] Akan tetapi untuk variabel pertama di atas, Muhammadiyah dan NU bisa memainkan peranan besar. Dalam situasi di mana negara tak lagi mampu berartikulasi dengan maksimal, sementara old social control, meminjam istilah Migdal,[22] tak lagi mempunyai daya, kedua organisasi ini justru bisa berperan sebagai kekuatan civil society yang signifikan. Situasi lemahnya baik negara maupun sistem kontrol sosial tradisional telah menimbulkan kekaburan orientasi dan tatanan kemasyarakatan, di mana kekuatan-kekuatan sosial-politik, ekonomi dan budaya bergerak tanpa arah. Maka, persis seperti dimiliki kaum militer, hanya Muhammadiyah dan NU-lah yang mempunyai kekuatan lebih terorganisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, keduanya secara potensial bisa tampil sebagai the leading groups dalam proses restrukturisasi pelataran keidupan sosial-budaya dan politik—di atas mana, negara dan kelompok-kelompok masyarakat berkinerja.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah dan NU bisa bertindak sebagai wakil kekuatan-kekuatan nonnegara yang otoritatif, baik dalam berhadapan dengan negara pada tingkat domestik mau pun kekuatan-kekuatan “supra” pada tingkat internasional. Untuk sementara, potensi semacam ini telah mulai terlihat. Di satu pihak, sebagaimana telah disinggung di atas, suara-suara Muhammadiyah dan NU jauh dianggap mempunyai otoritas moral dan intelektual dibandingkan dengan hampir semua kekuatan-kekuatan politik resmi di Indonesia. Di pihak lain, walau tetap untuk kepentingan domestik Indonesia, suara keduanya bukan hanya telah juga menjadi referensi pada tingkat duta besar negara-negara Barat —yang datang berkunjung dan berdialog. Melainkan juga telah menarik perhatian menteri luar negeri Inggris dengan mendatangi dan membeberkan rencana dan visi negara-negara “penguasa dunia” (Amerika dan Inggris) kepada mereka —walau untuk sementara, masih terbatas pada urusan perang melawan rezim Saddam Hussen dari Irak.
Jika Muhammadiyah dan NU berhasil mengarungi peran baru ini, maka akibat-akibat positifnya jelas jauh lebih strategis dan bermakna serta lebih substansial bagi proses pemberdayaan politik umat Islam. Sebab aktivitas “politik” semacam ini tak lagi menyangkut persoalan kepentingan kekuasaan dalam pengertian harfiah. Melainkan menyangkut kepentingan kelanjutan demokrasi dan keselamatan kemanusiaan secara keseluruhan.
Catatan Akhir:
[1] Pernah disampaikan dalam program Diskusi Serial bidang Politik International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 16 Januari 2003.
[2] Fred Halliday dan Hamzah Alavi, “Introduction”, untuk buku suntingan mereka, State and Ideology in the Middle-East and Pakistan (houndmills, Basingstoke, Hampshire RG 21 2XS and London: McMillan Education, 1988), hlm. 2.
[3] Clifford Geertz, “Religion As a Cultural System”, dalam Clifford Geertz, The Interpretation of (London: Fontana Press, 1993), hlm. 89
[4] Geertz, Religion As…,” hlm. 90.
[5] Lihat, misalnya, Julia Clancy-Smith, Saints, Mahdis and Arms: Religion and Resistance in Nineteenth-Century North Africa”, dalam Edmund Burke, III, dan Ira M. Lapidus, (peny.), Islam, Politics, and Social Movements (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1988), hlm. 60-80.
[6] Charles F. Keyes, Hellen Hardacre, dan Laurel Kendall, “Contested Visions of Community in East and Southeast Asia”, dalam buku suntingan mereka, Asian Visions of Authority, Religion and the Modern State of East and Southeast Asia (Honolulu: University of Hawaii Press, 1944), hlm. 1-18.
[7] George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1970, hlm. 66.
[8] W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change (Bandung: Sumur Bandung, Edisi Kedua, 1956), hlm. 185.
[9] Lihat Benedict R’OG Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culuture”, dalam buku kumpulan karangannya, Language and Power. Exploring Political Culture in Indonesia (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1990), hlm. 72. Lihat terutama catatan kaki no. 108.
[10] Tentang efek dari pidato ini, lihat Boyd R. Compton, Kemelut Demokrasi Liberal. Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton (Jakarta: LP3ES, 1992). Terutama lihat “Presiden Sukarno dan Negara Islam”, hlm. 121-133.
[11] Di sini, Duverger menunjuk partai-partai berorientasi Sosialisme dan yang berorientasi Katolik sebagai contoh party of indirect structure. Keduanya dianggotai oleh berbagai organisasi buruh, pedagang dan lainnya, untuk partai-partai sosialis, dan organisasi-organisasi keagamaan untuk partai-partai Katolik. Lihat Maurice Duverger, Political Parties (London: Metheun & Co., 1964), hlm. 6.
[12] Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Itacha, New York: Cornell University Press, 1962), hlm. 134-135.
[13] Penjelasan lebih lengkap tentang ini, lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980). Lihat juga Alfian, Muhammadiyah. The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation under Dutch Colonialism (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989). Lihat juga H. A. Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa (Ciputat: Logos, 1999). Lihat juga Marzuki Wahid, et al, (peny.) Geger di Republik NU. Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna (Jakarta: Kompas dan LAKPESDAM-NU, 1999).
[14] Setelah Masyumi dibubarkan pada awal 1960-an, Muhammadiyah secara resmi “mengundurkan diri” dari dunia politk. Dan kendati pun pada 1952 NU memisahkan diri dari Masyumi untuk menjadi partai politik tersendiri, namun sejak 1973, NU kembali menjadi organisasi nonpolitik hingga dewasa ini.
[15] Tentang hal ini, lihat, antara lain, Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree. Study of the Muhammadiyah Movement in a Central javanese Town (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983).
[16] Tentang hal ini, lihat Clifford Geertz, “Javanese Kiyayi: the Changing Role of Cultural Broker”, Comparative Studies in Society and History, No.2,1960.
[17] Bahkan sampai 1952, kaum intelegensia masih tergagap-gagap menggunakan bahasa Indonesia dalam sebuah percakapan “akademis”. Sjahrir, misalnya, menyatakan dalam percakapan itu: “Bahasa Indonesia jang kita gunakan malam ini tiada pula memudahkan tertjiptanja maksud kita untuk membentuk pengertian bersama… Untuk sementara, tampaknja kekeruhan pengertian jang disebabkan oleh penggunaan bahasa kita sendiri di dalam dunia berfikir abstak tadi hanja akan dapat dihilangkan dengan mengulangkan apa jang hendak kita katakan dalam salah satu bahasa Barat, yang telah biasa digunakan untuk itu.” Lihat St. Sjahrir, “Kesulitan-kesulitan dalam Masa Peralihan Sekarang Ditilik dari Sudut Sosiologi”, dalam Simposium tentang Kesulitan-kesulitan Zaman Peralihan Sekarang (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hlm. 75. Huruf miring adalah tambahan.
[18] Mungkin juga karena sifat agrarisnya, gerakan-gerakan politik dengan mengatasnamakan Islam tak pernah survive dalam “wilayah peperangan” ini, seperti diperlihatkan pemberontakan-pemberontakan petani dengan menggunakan “ideologi” Islam. Betapa pun tak ringkas dalam rentang waktu, toh akhirnya pemberontakan pedesaan Aljazair akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20—yang dilecut oleh sistem perpajakan kolonial Prancis dan akibat-akibat dislokasi sosial-budaya lainnya—tak kuasa untuk menang. Lihat Peter Von Sievers, “Rural Uprisings as Political Movements in Colonial Algeria, 1851-1914”. Dalam Burke, III dan Lapidus, Islam, Politics…, hlm. 39-59. ini juga terjadi pada kaum pedesaan Sumatera Barat yang memberontak karena alasan sistem pajak yang sama. Lihat Ken Young, Islamic Peasant and the State. The 1908 Anti-Tax Rebellion in West Sumatra.
[19] Goenawan Mohammad, “Visnu”, dalam Goenawan Mohammad, Conversation with Difference, terj. Jennifer Lindsay (Jakarta: PY Tempo Inti Media, Tbk., 2002) hlm 30.
[20] Pembahasan komprehensif tentang ini, lihat Eric Toussaint, Your Money or Your Life? Tyrany of Global Finance (London et al: Pluto Press, 1999).
[21] Tentang hal in, lihat antara lain, Susane Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World of Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). Lihat juga Philip C. Cerny, (peny.), Finance and World Politics. Markets, Regimes and State in Post-hegemonic Era (Hans GU11 3HR: Edward Elgar Publishing Ltd., 1993).
[22] Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabalities in the Third World (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1988), hlm. 93-96.

keroncong- KAPTEN
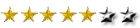
-

Age : 70
Posts : 4535
Kepercayaan : Islam
Location : di rumah saya
Join date : 09.11.11
Reputation : 67
 Similar topics
Similar topics» Pembunuhan Ummat Islam Oleh Ummat Budha Myanmar
» imam khomeni:politik tuhan vs politik setan
» islam dan politik
» [info] COKLAT NYOMOT UNTUK UMKM PEMBERDAYAAN BISNIS NINUMAN
» Ummat Trans 7 - Muslim Tionghoa
» imam khomeni:politik tuhan vs politik setan
» islam dan politik
» [info] COKLAT NYOMOT UNTUK UMKM PEMBERDAYAAN BISNIS NINUMAN
» Ummat Trans 7 - Muslim Tionghoa
Halaman 1 dari 1
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik


