meleburkan dikotomi yang sakral dan profan
Halaman 1 dari 1 • Share
 meleburkan dikotomi yang sakral dan profan
meleburkan dikotomi yang sakral dan profan
Di tengah gempuran ideologi rasionalisme dan kebangkitan sains, agama ternyata masih terus bertahan, walau agak gamang. Manusia masih percaya bahwa agama tetap dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Bukan hanya dapat bertahan, dalam perjalanannya agama bahkan tumbuh dalam banyak bentuk dan ragam. Sekarang ini, misalnya, kita cukup akrab dengan istilah-istilah seperti kultus, new age, spiritualitas baru, dan sebagainya. Belum lagi maraknya minat terhadap segi-segi esoterisme agama seperti tasawuf yang melibatkan kalangan kelas menengah perkotaan. Semua itu merupakan fenomena yang memperlihatkan bahwa agama justru tengah mengukuhkan kembali eksistensinya bersama-sama dengan kebangkitan gerakan spiritualitas.
Beberapa Pendekatan
Agama atau religi dalam pengertian umum adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh sebuah masyarakat atau suku dan bersifat mengikat mereka serta memberi sanksi pada kehidupan mereka. Karena Indonesia memiliki pulau-pulau dan suku yang begitu banyak maka sesungguhnya di Indonesia terdapat banyak sekali agama, terutama agama dalam pengertian “primitif” dan sederhana. Dapatlah dikatakan bahwa dalam setiap komunitas terdapat agama-atau apapun yang semisal dengannya, yang semuanya mempunyai apa yang disebut dengan sistem kepercayaan (belief system).
Dalam pengertian obyektif, keberadaan etnis dan letak geografi menjadi sebab bagi munculnya agama-agama. Hal ini berbeda dengan pulau yang homogen seperti Jepang, misalnya, di mana agama tidak terlalu banyak seperti di Indonesia. Tapi memang agama dalam pengertian Pancasila baru ada lima, dan semuanya merupakan pendatang. Islam merupakan agama pendatang. Begitu juga Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Agama-agama di luar yang disebut tadi tidak diakui, dan tidak disahkan. Mereka (agama-agama asli itu) hidup di negeri sendiri tapi mengalami nasib diskriminasi. Tidakkah ini sebuah ironi?
Dalam kajian para ahli agama dan antropologi yang didukung oleh analisa psikologi, terungkap bahwa agama memang masih tetap dan akan bertahan dalam kehidupan manusia kapan dan di mana pun. Secara psikologis, setiap orang membutuhkan kepercayaan, sejak dari kepercayaan pada hubungan inter-personal, antar-personal maupun antar-masyarakat dan alam raya. Pada kepercayaan antar-personal dapat melahirkan kesalingpercayaan sehingga dapat mengadakan kerjasama. Pada kepercayaan terhadap alam, timbul mitologi-mitologi serta kepercayaan pada yang gaib atau yang supra, yaitu Pencipta. Kemudian secara antropologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap komunitas kolektif selalu mempunyai sistem kepercayaan.
Walaupun nantinya mereka menerima agama (dan nilai-nilai) baru, bukanlah menjadi sebab bagi lebur dan hilangnya agama mereka sebelumnya. Setiap agama yang diterima memang selalu dapat mempengaruhi seseorang atau masyarakat secara mendalam, terutama dalam hal nilai-nilai. Tetapi walaupun ada kemiripan dengan yg ada pada agamanya, tetap saja agama terdahulu sulit utk ditinggalkan. Hal tersebut dapat kita pahami dengan ungkapan; Mengapa di mana-mana orang minum menggunakan cangkir dan ada model yang sama seperti cangkir? Itu karena fonomena universal di mana ada orang dan ada minuman. Sedangkan alat untuk minum yang praktis hanya cangkir, atau gelas yang ada pegangannya. Karenanya peristiwa itu merupakan sesuatu yang hadir serta bertahan karena mempunyai fungsi yang memenuhi kebutuhan seseorang dan masyarakat. Agama baru hadir karena juga bertugas memenuhi kebutuhan manusia yang mungkin belum tercukupi oleh nilai-nilai lain. Kalau agama baru sama sekali bertentangan, apalagi mengkanter, agama atau nilai-nilai, pasti ia mengalami perlawanan. Dengan demikian, setiap agama ketika hadir harus melakukan penyesuaian, bahkan kerjasama.
Anomali Sejarah
Indonesia sebagai negeri yang kaya akan agama, justru banyak sekali memperlihatkan anomali dalam perjalanan sejarah agama itu sendiri. Dalam kenyataan kita merasakan hal-hal yang sulit dipahami, misalnya fakta bahwa di luar agama Kristen dan Islam, agama-agama lain mengalami keterlambatan penyebaran maupun perkembangan. Walaupun hal tersebut mungkin dapat dipahami dengan melihat watak masing-masing agama, tetapi tetap sulit dimengerti dengan sederhana. Sebagai contoh, agama Yahudi adalah agama yang mempunyai kaitan dengan hubungan darah atau persaudaraan, sehingga perkembangan pemeluknya baru beredar di sekitar keturunan dan handai taulan. Karenanya agama Yahudi kurang berkembang di Indonesia. Apalagi dalam kenyataannya, begitu suatu agama dipeluk oleh masyarakat, maka masyarakat tersebut akan membangun suatu eksklusivisme kelompok berdasarkan hubungan agama, darah dan keluarga. Dengan begitu agama akan bertahan antara lain bukan karena kekuatan ajarannya saja, tapi juga solidaritas kelompok (penganut) yang lebih dulu lahir. Hal ini dapat dipahami dengan generasi berikutnya yang akan mengikuti agama moyang sebelumnya. Dengan demikian agama kemudian menguat dan dikuatkan oleh kelompok keturunan yang selalu berkembang.
Agama dalam arti yang kita pahami selama ini adalah agama yang datangnya belakangan. Artinya, sebelum agama datang, sesungguhnya sudah ada masyarakat. Kedatangan agama berfungsi memperkokoh tradisi yang sudah ada dan memperkaya dengan hal-hal yang baru. Tapi bukan hanya itu. Agama juga akan mensakralkan dan mensublimasikan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan universal ke dalam masyarakat. Itulah sebabnya mengapa agama, walaupun datangnya pada masa lalu, tetapi akan selalu aktual ketika bicara tentang hal-hal yang memang perennial, terutama berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Karena pada diri manusia selalu ada sifat-sifat yang laten, misalnya kebaikan, keadilan, kejujuran, dan sifat-sifat universal lainnya. Ketika agama dipahami dan dirumuskan menjadi suatu identitas kelompok, maka masyarakat dengan norma-norma sebelum agama tadi akan mengalami “konversi”. Maka kemudian norma agama menjadi suatu hal yang baru.
Dalam Islam hal semacam ini sangat besar dan mencolok sekali. Islam memang datang dengan melakukan akomodasi dan memperkaya, sehingga masyarakat-masyarakat Islam punya warna yang agak monolitik tetapi pluralistik dalam sikap dan ekspresi. Walaupun berbeda-beda, orang atau masyarakat Islam itu selalu memiliki karakter yang menonjol: ada masjid, ada shalat jama’ah, ada seruan azan. Ajaran-ajarannya terlihat sangat dominan. Itulah sebabnya seorang sarjana Kristen pernah menyatakan: “Kalau saya ingin tahu dunia Islam, saya tidak perlu riset, sebab apa saja ajaran Muhammad yang prinsip, kelihatan di seluruh dunia, itulah wajah Islam di seluruh dunia.”
Corak dan Ritus Agama
Dalam sejarahnya yang panjang, agama mengalami pluralisasi baik ritus maupun cara penganutannya. Masing-masing daerah selalu mempunyai corak dan ritual agama yang berbeda antar-satu agama, apalagi antar-agama yang berbeda. Pola yang terjadi adalah dengan berkerumun (berkelompok) atas nama identitas agama atau ajaran agama. Begitu tingginya perbedaan itu sehingga mereka kadang-kadang lebih fanatik pada persamaan sempit daripada fungsi-fungsi substansi dari agama itu sendiri.
Indonesia dalam hal ini menjadi contoh yang baik bagi munculnya perbedaan ritual dan cara penganutan agama-agama, bahkan di dalam satu agama sendiri seperti Islam. Sudah bukan rahasia lagi bahwa perbedaan antara NU dan Muhamamadiyah sering dibawa pada perbedaan yang terlalu jauh pada sikap-sikap hidup keseharian, terutama pada level masyarakat bawah. Seorang yang menyekolahkan anaknya di bangku sekolah Muhammadiyah, misalnya, akan dipandang “beda agama” oleh masyarakat lainnya yang NU. Nurcholish Madjid pernah mengemukakan ilustrasi mengenai orang-orang Madura yang ditanya: “Bagaimana kehidupan beragama di sini Pak?” Pertanyaan itu dijawab oleh orang Madura: “Alhamdulillah, di sini semuanya Islam, kecuali satu-dua orang saja yang Muhammadiyah.”
Tentu saja itu hanya ilustrasi. Tetapi itu cukup untuk menggambarkan kehidupan keagamaan masyarakat kita yang menyiratkan identifikasi keagamaan yang hampir-hampir buta. Kalau kita menganggap bahwa dalam jangka panjang cara pandang semacam itu tidak menguntungkan bagi kehidupan pluralisme, maka tentu “kebutaan” itu harus disembuhkan. Cara penyembuhannya mungkin perlu diberi shock therapy. Tapi itu pun tidak cukup tanpa diangkat satu kenyataan, misalnya dengan menyadari bahwa ternyata teori-teori yang ada selama ini tidak bekerja (doesn't work). Kita memerlukan suatu gerakan sosial yang baru untuk menyegarkan faham pluralisme, salah satunya adalah gerakan di bidang pendidikan, di mana perlu mulai dikenalkan pendidikan multikulturalisme (lihat artikel, Mazhabisme vs Multikulturalisme).
Hancurnya Simbol Agama
Dalam konteks ini, untuk kasus Indonesia, kita pernah melihat ironi politik Islam yang mengingkari pluralisme. Ketika itu “Poros Tengah” yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam yang kalah pemilu begitu solid menghadapi PDI-P sebagai pemenang pemilu. Kekuatan Poros Tengah dibangun dengan satu persepsi bahwa PDI-P itu bukan mewakili aspirasi Islam, sedang Poros Tengah itu Islam. Oleh karena itu daripada yang naik Megawati (PDI-P) dan dikhawatirkan yang duduk di DPR/MPR bukan Islam, maka didoronglah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon Presiden. Dan memang kemudian Gus Dur berhasil mengalahkan Megawati. Maka ketika Gus Dur naik, dia dianggap mewakili simbol semangat agama, bahkan santri par excellence.
Tetapi, apa yang terjadi kemudian? Misi dan tugas kabinet Gus Dur itu akan dianggap berhasil kalau bisa membangun ekonomi. Ironisnya kemudian karena ternyata juru selamatnya itu bukan agama, melainkan IMF, Bank Dunia, yang bukan Islam, maka “mandat Islam” di pundak Gus Dur menjadi kedodoran. Ini sebenarnya peristiwa menggelikan. Sebab apabila menggunakan simbol agama sebagai solusi, maka mestinya juru selamatnya juga adalah agama, tapi ternyata Bank Dunia dan IMF yang Yahudi. Jadi romantisme simbol agama pada hakekatnya sudah hancur.
Dalam kasus Indonesia, romantisme simbol agama juga tidak mampu mengartikulasikan problem yang riil, tidak mampu menjawab soal-soal masyarakat. Yang ada dalam romantisme justru antusiasme beragama. Sekarang ini ada kekuatan transnasional yang menjadi sumber malapetaka Indonesia. Masyarakat terpuruk dalam bidang ekonomi, dan ekonomi obatnya tidak dengan memperbanyak kiai atau dakwah, melainkan harus realistis-ekonomis.
Kita menyaksikan sekarang ini banyak sekali televisi dan radio yang menyiarkan acara keagamaan Islam. Mubalig sudah tak terhitung jumlahnya. Tapi sebenarnya ada kanker menggerogoti. Sayangnya kanker itu tidak dianggap, karena dalam agama seakan-akan semua beres dengan retorika, dengan khotbah-khotbah, tetapi tidak tahunya kondisi masyarakat ambruk dan solusinya pada ekonomi. Karenanya terhadap persoalan kanker (ekonomi) yang menggerogoti masyarakat itu, IMF dan Bank Dunia dipilih sebagai jawaban.
Problem Sekarang: SDM
Dengan berubahnya makna simbol agama, maka perlu ada radikalisasi pemahaman terhadap agama itu sendiri. Tetapi persoalannya adalah masyarakat masih feodal. Mereka, misalnya, masih menganggap pemimpinnya adalah orang-orang yang tidak dapat salah, sehingga tidak boleh dikritik. Inilah yang harus diubah. Para da’i perlu dikenalkan pada pendekatan empiris dalam melihat persoalan umat. Tidak deduktif dan utopis. Sehingga harus ada wacana ekonomisasi bagi para da’i agar berwawasan induktif dan realistis bahwa problem umat sekarang adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dengan SDM yang mumpuni diharapkan akan terjadi perubahan yang berkelanjutan dalam paradigma berpikir dan bertindak. Sehingga agendanya nanti ialah bagaimana memenej kekayaaan alam dengan baik. Dan ini membutuhkan satu wawasan ekonomi, teknologi, dan politik-bukan dalam arti politicking, tetapi dalam arti seni mengatur negara modern, manajemen potensi kebangsaan, yang sebenarnya itu adalah istilah-istilah dari Barat dan berasal dari wilayah non-agama.
Salah satu agenda penting pengembangan SDM ialah pendidikan. Lebih spesifik lagi, perlu dilakukan elaborasi kurikulum, misalnya tidak ada lagi dikotomi Islam dan non-Islam, agama dan non-agama. Misalnya lagi, belajar fiqh dimulai dengan bab ilmu (bâb al-`ilm). Kenapa? Karena ayat pertama adalah “Iqra” dan itu karena Allah menghargai akal manusia. Setelah itu bab kerja (bâb al-`amal), sebab kata “amal” (kerja) dalam bahasa Arab satu akar kata dengan “ilmu”, hanya dibalik posisi hurufnya. Berarti ilmu itu akan meaningful kalau ada implikasi praktis dalam bentuk “amal”. Demikian juga amal itu akan benar kalau ada ilmu. Jadi ilmu itu turun menyinari amal.
Terkait dengan agenda itu ialah bahwa kerangka pikir dalam merespon persoalan kehidupan ini dituangkan dalam buku yang selalu baru. Artinya, banyak buku yang harus diubah, yaitu kitab-kitab lama, karena cara pandang manusia pada dunia selalu berubah dan dipengaruhi oleh banyak hal. Jangan seperti membeli komputer yang diinstal hanya dengan WS 4, tapi semua problem ingin dapat diselesaikan dengan WS 4, tidak bisa. Persoalan sosial kemasyarakatan lebih sulit lagi, karena itu tidak dapat dipecahkan dengan cepat kecuali harus dengan mengubah programnya.
Kaji Ulang Metodologi
Memang tidak bisa diingkari adanya dua wilayah: wilayah agama yang sakral dan wilayah dunia yang profan. Tetapi dalam kenyataannya, terlebih bagi seorang Muslim, keduanya melebur menjadi satu. Pemisahan dikotomis itu hanyalah retorika. Misalnya batas antara ilmu agama dan ilmu umum, juga antara agama dan teknologi, dalam operasionalnya semuanya melebur secara fungsional. Agama dan filsafat memberikan visi dan pemikiran seputar makna hidup, sedangkan ilmu dan teknologi memberikan kemudahan bagaimana menyelenggarakan hidup agar lebih nyaman dan mudah. Disayangkan, paradigma pemikiran kita masih terbelah, dan hal ini diperkuat lagi dengan adanya dua departemen, yaitu: Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional sehingga melahirkan bayangan adanya dikotomi keilmuan dan kepribadian yang dihasilkan oleh masing-masing departemen yang juga mengelola dunia pendidikan.
Menyadari adanya kekeliruan ini maka visi dan kurikulum pendidikan serta ceramah-ceramah keagaman harus diperbaiki sehingga artikulasi dan praktek keberagamaan bisa sejalan, bahkan memberikan inspirasi dan arahan, dengan perubahan sosial yang berlangsung. Sekarang ini dirasa perlu merombak strategi pembelajaran agama. Misalnya, seperti telah kita singgung, dalam buku-buku keagamaan mestinya pembahasan mengenai ilmu lebih didahulukan sebelum membahas soal wudlu ataupun ibadah lain. Jika mengikuti kronologi turunnya ayat al-Qur’an, mestinya rukun Islam yang pertama itu mencari ilmu, baru memasuki rukun yang lain. Bukankah rukun berarti sesuatu yang prinsipil? Sedangkan mencari ilmu itu sangat prinsipil dalam pandangan al-Qur’an. Kemudian setelah haji, perlu ditambahkan lagi rukun yang lain, yaitu amal saleh, karena muara ibadah haji secara sosial adalah berbuat al-birr, yaitu amal saleh secara vertikal dan sosial.
Jadi persoalan metodologi, bukan hanya substansi dan bangunan normatifnya, dalam mempelajari Islam dan mengembangkannya, sangat mendesak untuk dikaji ulang. Sekadar contoh, dulu belajar membaca al-Qur’an dengan sistem Hijaiyah membutuhkan beberapa tahun. Itu pun sudah disebut mengaji, padahal sesungguhnya baru belajar membaca tulisan Arab. Tapi sekarang dengan metode baru, hanya dalam beberapa bulan saja anak bisa membaca al-Qur’an. Belum lagi mereka yang belajar al-Qur’an dan tafsirnya dengan bantuan komputer dan CD Rom yang ternyata jauh lebih cepat ketimbang dengan pendekatan tradisional semacam ceramah. Itu terjadi karena adanya perubahan metodologi. Oleh karenanya perlu dibedakan antara substansi dan metodologi. Jangan disamakan orang belajar bahasa Arab dengan belajar substansi agama karena di negara Arab banyak yang tahu bahasa Arab, namun tidak faham kandungan al-Qur’an. Bahwa orang menguasai bahasa Arab itu bagus, namun tidak jaminan menguasai ilmu keislaman.
Sementara ini bangsa kita masih disibukkan oleh perjuangan simbol dengan luapan emosi, karena itu yang lebih substansial tidak menjadi agenda pokok perjuangan. Kemiskinan, kesulitan pendidikan, problem kesehatan, adalah masalah-masalah riil yang terabaikan. Dengan turunnya wibawa para politisi kaum santri dan ulama yang menggejala akhir-akhir ini, maka orang mulai tidak respek dan tidak percaya pada tokoh dan lembaga agama karena dinilai tidak mampu memecahkan problem bangsa yang riil tadi. Menghadapi kenyataan ini maka agamawan harus lebih arif dalam menyikapi hal tersebut. Misalnya seorang pakar agama bicara ekonomi, maka dia harus bisa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang agamawan yang berhasil di bidang ekonomi, karena orang akan dipercaya kalau mempunyai referensi konkrit, amal yang nyata. Di Bandung, misalnya, ada koperasi pesantren, dan melibatkan orang-orang profesional dalam bidang manajemen, maka orang pun akan percaya pada konsep koperasi pesantren. Bank Muamalah juga diuji, kalau dia berhasil, orang akan percaya ada Bank Islam. Tapi kalau tidak berhasil, orang akan bertanya, untuk apa Islam-Islaman. Jadi, sekali lagi, harus ada yang konkrit. Orang sudah jenuh dengan kata-kata, dan orang juga sudah tidak mudah terbius dengan pidato agama. Orang bisa saja kagum dengan pidato KH Zainuddin MZ, tapi secara psikologis orang juga akan senang mendengarkan Srimulat karena di situ terdapat unsur hiburan.
Di samping mengandalkan retorika, seharusnya kita bisa mulai memecahkan problem riil dengan pendekatan program, skill, dan institusi. Dan ini semua harus dijadikan program jangka panjang secara berkelanjutan. Kalau program di atas berhasil mungkin akan memunculkan phobia-phobia sebagaimana masa lalu, dimana orang luar takut pada Islam. Tetapi jawabannya adalah kalau hal tersebut dirasakan rakyat maka tidak ada alasan untuk phobia. Misalnya pendidikan yang didirikan orang Katolik, orang Islam tidak bisa marah, karena nyatanya pendidikannya mengikuti kurikulum umum, hasilnya bagus, anak didiknya bisa lulus UMPTN. Sehingga tidak ada alasan marah, karena terbuka alias transparan. Amal yang baik adalah transparansi.
Sekarang banyak pendidikan yang dibangun orang Kristen. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menghalangi karena riil sumbangannya. Sebaliknya kalau orang Islam marah, mereka harus membuat pendidikan yang lebih bagus. Hal tersebut tidak terkait dengan persoalan romantis-emosional karena memang untuk menjawab persoalan yang riil.
Memang romantisme dan sejarah masa lalu diperlukan, tapi jangan sampai hal itu dijadikan sebagai tempat pelarian. Sikap romantisme juga tidak serta merta dapat langsung dihilangkan dengan tergesa-gesa, karena masyarakat adalah anak kandung sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu mengandung values serta cita-cita hidup, sehingga harus dijaga seperlunya. Bukankah dalam hidup itu ada makna, imajinasi, eskatologi. Seorang pria yang patah hati, kemudian kepadanya ditawarkan wanita yang lebih cantik, tentu hatinya tidak bisa langsung berubah, karena tidak ada hubungan kimiawi, karena di sana ada sesuatu yang non-materi, yang menggetarkan, yang membuat seseorang merasa hidup. Apalagi itu berkembang dalam setiap masyarakat secara lama dan laten, dan merupakan endapan yang terbentuk oleh habitat, konsep diri, dan cita-cita. Ketika orang bertemu dengan orang lain perilakunya juga dipengaruhi oleh konsep diri: aku ini siapa. Misalnya ketika menjabat Presiden dan ketika tidak lagi jadi Presiden akan lain lagi sikapnya. Konsep diri ini berpengaruh dalam korelasi, karena ada values yang mempengaruhi. Tetapi itu juga perlu bagi kita untuk mengatakan kepada generasi muda Islam agar memasuki wilayah-wilayah riil tanpa harus meninggalkan tradisi agama yang sudah dianut.
Etos Ketaatan Vs Etos Kreativitas
Ketika kita membicarakan ilmu pengetahuan dalam konteks agama Islam maka terasa ada hal yang hilang. Yaitu, tidak berkembangnya ilmu futurologi secara pesat. Dalam Islam yang berkembang justru ilmu eskatologis. Ini disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, ikatan masa lalu yang sangat kuat. The golden years begitu digemari, sehingga orang menjadi terus menerus merujuknya. Sementara kaki berjalan ke depan, kepala kita ingin ke belakang, sehingga perlu diimbangi; bukan pergi ke belakang dalam arti konsep waktu, tapi ke belakang dalam arti menggali substansi ajaran Islam. Karena kalau substansi tidak perlu terpenjara oleh romantisme historis.
Kedua, orang Islam lebih mempunyai etos ketaatan, bukan etos kreativitas. Ada satu persepsi dari sebagian besar orang Islam bahwa hukum Tuhan itu sudah jadi dan komplit. Kalau sudah komplit, buat apa lagi berpikir, tinggal mengikuti saja. Inilah yang menyebabkan lahirnya etos ketaatan. Karenanya dalam kenyataan orang Islam lebih suka pergi ke dukun yang kontemplatif. Alasannya, karena ketaatan tadi dapat menyelesaikan masalah. Tapi juga perlu dilihat, fenomena ketaatan adalah fenomena Islam tradisional. Apalagi fenomena itu juga merupakan sumbangan kultural dan bukan karena watak keislaman yang sesungguhnya.
Watak tersebut berasal dari dunia pesantren sehingga sering dianggap sumbernya dari Tuhan, dan Tuhan memberikan karamah pada orang-orang tertentu. Maka muncullah fenomena wali atau kiai khas. Karena itu kemudian orang datang kepada Tuhan lewat wasilah orang-orang tersebut. Hal ini berbeda dengan humanisme sekuler yang mempercayai bahwa karamah itu ada di pabrik dan pada kegiatan inovasi. Dunia maju memandang mukjizat tidak lagi terletak pada doa, melainkan pada inovasi-kreatif. Mukjizat baru di Jepang ialah menciptakan robot atau kereta api yang super cepat. Mukjizat di situ adalah produk dari riset yang empirik. Di dunia Islam mukjizat adalah sesuatu yang metafisis. Itulah yang menyebabkan persoalan teologis-epistemologisnya dilarikan ke eskatologi sehingga kemudian mengambil jarak dari dunia empiris, dan pada akhirnya berpengaruh dalam cara memandang dunia. Di dunia Islam petualangan imajinasi luar angkasa adalah lewat mukjizat Mikraj, sedang di Barat petualangan itu sesuatu yang riil, membuat pesawat ulang alik. Jadi memang berbeda sekali alam pikiran orang Muslim dan Barat ketika berbicara tentang luar angkasa.
Sekarang coba kita riset sarjana-sarjana IAIN, ilmunya tidak ada yang baru, karena yang baru adalah mengenalkan yang lama. Istilah baru sama sekali tidak dikenal. Karena Islam itu azali, shalih `alâ kulli zamân wa makân, sehingga tugas mereka hanyalah mengenalkan dan menyebarkan. Akhirnya konsep dakwah juga hanya menyebarkan ajaran, bukan menggali ilmu baru. Ibaratnya kita hanya shopping, memahami, menghapal, dan menyebarkan. Sehingga kita tidak punya fasilitas riset untuk mencipta dan berkreasi. Umat Islam tidak berusaha untuk menjadi produsen, seperti membuat pabrik, tetapi hanya diajari ber-shopping. Akibatnya, retail dealer kita kecil. Kita shopping ke masa lalu dan pada al-Qur'an yang sudah komplit.
Dalam banyak hal, mata kita kini hanya mencari referensi literer pada khazanah keislaman. Kita kurang kreatif dan apresiatif terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh pengalaman agama, kebudayaan, dan bangsa lain. Misalnya, contoh paling riil adalah, dulu naik haji dengan unta, sekarang dengan pesawat. Peristiwa tersebut sudah sangat maju dan teknikal. Sadar atau tidak wilayah yang netral itu sudah ada kemajuan.
Kita sepakat bahwa memang harus ada guncangan kultural untuk membangkitkan kesadaran ini. Selain itu tentu kita perlu mendengarkan orang-orang yang berkata bahwa Islam belum sempurna. Seperti yang dikatakan (almarhum) Prof. Harun Nasution, Islam hanya mengenalkan basic principle, selebihnya kita harus mencari sendiri. Dan banyak wilayah yang memang diserahkan kepada kita. Ayat Allah yang turun pada kita hanyalah ayat lafdziyah yang sudah berakhir pada Muhammad. Ayat al-Qur'an yang perlu banyak kita baca seharusnya perintah al-Qur'an atau ayat Allah yang berupa ayat-ayat ijtimaiyah (sosial), ayat-ayat tarikhiyah (sejarah), ayat-ayat nafsiyah (jiwa). Kita harus banyak belajar dari peristiwa kemanusiaan. Sayangnya selama ini kita belajar hanya teks yang struktural. Mungkin kita tidak serius mendengarkan al-Qur'an itu sendiri.
Sebelum mengakhiri uraian ini, tanamkanlah dalam hati dengan sungguh-sungguh bahwa al-Qur'an itu adalah masa lalu yang tidak harus selalu diapresiasi. Al-Qur'an sebagai teks sudah selesai. Karena sesungguhnya al-Qur'an itu sendiri mengusir orang yang membacanya. Al-Qur'an sebenarnya hendak mengatakan pada umatnya, “Bukan ini ayatku, aku ini hanya konsultan yang sekali-kali perlu dirujuk, tapi selebihnya jangan ke sini, pergilah ke masyarakat, lakukanlah riset.” Kita tidak mau mendengarkan usulan al-Qur'an, karenanya riset yang bernilai empiris mandeg. Akhirnya dunia eskatologis yang menyesatkan banyak berkembang di dunia Islam menggantikan empirisisme. Karena itu para agamawan hendaknya mulai menyadari betapa kajian-kajian eskatologis harus mulai ditinggalkan, sebagai gantinya harus ada seruan moral bersama agar pada waktu-waktu mendatang generasi baru kita adalah generasi yang menyeimbangkan kajian yang bersifat empiris, futurologis, etik eskatologis.[*]
Beberapa Pendekatan
Agama atau religi dalam pengertian umum adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh sebuah masyarakat atau suku dan bersifat mengikat mereka serta memberi sanksi pada kehidupan mereka. Karena Indonesia memiliki pulau-pulau dan suku yang begitu banyak maka sesungguhnya di Indonesia terdapat banyak sekali agama, terutama agama dalam pengertian “primitif” dan sederhana. Dapatlah dikatakan bahwa dalam setiap komunitas terdapat agama-atau apapun yang semisal dengannya, yang semuanya mempunyai apa yang disebut dengan sistem kepercayaan (belief system).
Dalam pengertian obyektif, keberadaan etnis dan letak geografi menjadi sebab bagi munculnya agama-agama. Hal ini berbeda dengan pulau yang homogen seperti Jepang, misalnya, di mana agama tidak terlalu banyak seperti di Indonesia. Tapi memang agama dalam pengertian Pancasila baru ada lima, dan semuanya merupakan pendatang. Islam merupakan agama pendatang. Begitu juga Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Agama-agama di luar yang disebut tadi tidak diakui, dan tidak disahkan. Mereka (agama-agama asli itu) hidup di negeri sendiri tapi mengalami nasib diskriminasi. Tidakkah ini sebuah ironi?
Dalam kajian para ahli agama dan antropologi yang didukung oleh analisa psikologi, terungkap bahwa agama memang masih tetap dan akan bertahan dalam kehidupan manusia kapan dan di mana pun. Secara psikologis, setiap orang membutuhkan kepercayaan, sejak dari kepercayaan pada hubungan inter-personal, antar-personal maupun antar-masyarakat dan alam raya. Pada kepercayaan antar-personal dapat melahirkan kesalingpercayaan sehingga dapat mengadakan kerjasama. Pada kepercayaan terhadap alam, timbul mitologi-mitologi serta kepercayaan pada yang gaib atau yang supra, yaitu Pencipta. Kemudian secara antropologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap komunitas kolektif selalu mempunyai sistem kepercayaan.
Walaupun nantinya mereka menerima agama (dan nilai-nilai) baru, bukanlah menjadi sebab bagi lebur dan hilangnya agama mereka sebelumnya. Setiap agama yang diterima memang selalu dapat mempengaruhi seseorang atau masyarakat secara mendalam, terutama dalam hal nilai-nilai. Tetapi walaupun ada kemiripan dengan yg ada pada agamanya, tetap saja agama terdahulu sulit utk ditinggalkan. Hal tersebut dapat kita pahami dengan ungkapan; Mengapa di mana-mana orang minum menggunakan cangkir dan ada model yang sama seperti cangkir? Itu karena fonomena universal di mana ada orang dan ada minuman. Sedangkan alat untuk minum yang praktis hanya cangkir, atau gelas yang ada pegangannya. Karenanya peristiwa itu merupakan sesuatu yang hadir serta bertahan karena mempunyai fungsi yang memenuhi kebutuhan seseorang dan masyarakat. Agama baru hadir karena juga bertugas memenuhi kebutuhan manusia yang mungkin belum tercukupi oleh nilai-nilai lain. Kalau agama baru sama sekali bertentangan, apalagi mengkanter, agama atau nilai-nilai, pasti ia mengalami perlawanan. Dengan demikian, setiap agama ketika hadir harus melakukan penyesuaian, bahkan kerjasama.
Anomali Sejarah
Indonesia sebagai negeri yang kaya akan agama, justru banyak sekali memperlihatkan anomali dalam perjalanan sejarah agama itu sendiri. Dalam kenyataan kita merasakan hal-hal yang sulit dipahami, misalnya fakta bahwa di luar agama Kristen dan Islam, agama-agama lain mengalami keterlambatan penyebaran maupun perkembangan. Walaupun hal tersebut mungkin dapat dipahami dengan melihat watak masing-masing agama, tetapi tetap sulit dimengerti dengan sederhana. Sebagai contoh, agama Yahudi adalah agama yang mempunyai kaitan dengan hubungan darah atau persaudaraan, sehingga perkembangan pemeluknya baru beredar di sekitar keturunan dan handai taulan. Karenanya agama Yahudi kurang berkembang di Indonesia. Apalagi dalam kenyataannya, begitu suatu agama dipeluk oleh masyarakat, maka masyarakat tersebut akan membangun suatu eksklusivisme kelompok berdasarkan hubungan agama, darah dan keluarga. Dengan begitu agama akan bertahan antara lain bukan karena kekuatan ajarannya saja, tapi juga solidaritas kelompok (penganut) yang lebih dulu lahir. Hal ini dapat dipahami dengan generasi berikutnya yang akan mengikuti agama moyang sebelumnya. Dengan demikian agama kemudian menguat dan dikuatkan oleh kelompok keturunan yang selalu berkembang.
Agama dalam arti yang kita pahami selama ini adalah agama yang datangnya belakangan. Artinya, sebelum agama datang, sesungguhnya sudah ada masyarakat. Kedatangan agama berfungsi memperkokoh tradisi yang sudah ada dan memperkaya dengan hal-hal yang baru. Tapi bukan hanya itu. Agama juga akan mensakralkan dan mensublimasikan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan universal ke dalam masyarakat. Itulah sebabnya mengapa agama, walaupun datangnya pada masa lalu, tetapi akan selalu aktual ketika bicara tentang hal-hal yang memang perennial, terutama berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Karena pada diri manusia selalu ada sifat-sifat yang laten, misalnya kebaikan, keadilan, kejujuran, dan sifat-sifat universal lainnya. Ketika agama dipahami dan dirumuskan menjadi suatu identitas kelompok, maka masyarakat dengan norma-norma sebelum agama tadi akan mengalami “konversi”. Maka kemudian norma agama menjadi suatu hal yang baru.
Dalam Islam hal semacam ini sangat besar dan mencolok sekali. Islam memang datang dengan melakukan akomodasi dan memperkaya, sehingga masyarakat-masyarakat Islam punya warna yang agak monolitik tetapi pluralistik dalam sikap dan ekspresi. Walaupun berbeda-beda, orang atau masyarakat Islam itu selalu memiliki karakter yang menonjol: ada masjid, ada shalat jama’ah, ada seruan azan. Ajaran-ajarannya terlihat sangat dominan. Itulah sebabnya seorang sarjana Kristen pernah menyatakan: “Kalau saya ingin tahu dunia Islam, saya tidak perlu riset, sebab apa saja ajaran Muhammad yang prinsip, kelihatan di seluruh dunia, itulah wajah Islam di seluruh dunia.”
Corak dan Ritus Agama
Dalam sejarahnya yang panjang, agama mengalami pluralisasi baik ritus maupun cara penganutannya. Masing-masing daerah selalu mempunyai corak dan ritual agama yang berbeda antar-satu agama, apalagi antar-agama yang berbeda. Pola yang terjadi adalah dengan berkerumun (berkelompok) atas nama identitas agama atau ajaran agama. Begitu tingginya perbedaan itu sehingga mereka kadang-kadang lebih fanatik pada persamaan sempit daripada fungsi-fungsi substansi dari agama itu sendiri.
Indonesia dalam hal ini menjadi contoh yang baik bagi munculnya perbedaan ritual dan cara penganutan agama-agama, bahkan di dalam satu agama sendiri seperti Islam. Sudah bukan rahasia lagi bahwa perbedaan antara NU dan Muhamamadiyah sering dibawa pada perbedaan yang terlalu jauh pada sikap-sikap hidup keseharian, terutama pada level masyarakat bawah. Seorang yang menyekolahkan anaknya di bangku sekolah Muhammadiyah, misalnya, akan dipandang “beda agama” oleh masyarakat lainnya yang NU. Nurcholish Madjid pernah mengemukakan ilustrasi mengenai orang-orang Madura yang ditanya: “Bagaimana kehidupan beragama di sini Pak?” Pertanyaan itu dijawab oleh orang Madura: “Alhamdulillah, di sini semuanya Islam, kecuali satu-dua orang saja yang Muhammadiyah.”
Tentu saja itu hanya ilustrasi. Tetapi itu cukup untuk menggambarkan kehidupan keagamaan masyarakat kita yang menyiratkan identifikasi keagamaan yang hampir-hampir buta. Kalau kita menganggap bahwa dalam jangka panjang cara pandang semacam itu tidak menguntungkan bagi kehidupan pluralisme, maka tentu “kebutaan” itu harus disembuhkan. Cara penyembuhannya mungkin perlu diberi shock therapy. Tapi itu pun tidak cukup tanpa diangkat satu kenyataan, misalnya dengan menyadari bahwa ternyata teori-teori yang ada selama ini tidak bekerja (doesn't work). Kita memerlukan suatu gerakan sosial yang baru untuk menyegarkan faham pluralisme, salah satunya adalah gerakan di bidang pendidikan, di mana perlu mulai dikenalkan pendidikan multikulturalisme (lihat artikel, Mazhabisme vs Multikulturalisme).
Hancurnya Simbol Agama
Dalam konteks ini, untuk kasus Indonesia, kita pernah melihat ironi politik Islam yang mengingkari pluralisme. Ketika itu “Poros Tengah” yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam yang kalah pemilu begitu solid menghadapi PDI-P sebagai pemenang pemilu. Kekuatan Poros Tengah dibangun dengan satu persepsi bahwa PDI-P itu bukan mewakili aspirasi Islam, sedang Poros Tengah itu Islam. Oleh karena itu daripada yang naik Megawati (PDI-P) dan dikhawatirkan yang duduk di DPR/MPR bukan Islam, maka didoronglah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon Presiden. Dan memang kemudian Gus Dur berhasil mengalahkan Megawati. Maka ketika Gus Dur naik, dia dianggap mewakili simbol semangat agama, bahkan santri par excellence.
Tetapi, apa yang terjadi kemudian? Misi dan tugas kabinet Gus Dur itu akan dianggap berhasil kalau bisa membangun ekonomi. Ironisnya kemudian karena ternyata juru selamatnya itu bukan agama, melainkan IMF, Bank Dunia, yang bukan Islam, maka “mandat Islam” di pundak Gus Dur menjadi kedodoran. Ini sebenarnya peristiwa menggelikan. Sebab apabila menggunakan simbol agama sebagai solusi, maka mestinya juru selamatnya juga adalah agama, tapi ternyata Bank Dunia dan IMF yang Yahudi. Jadi romantisme simbol agama pada hakekatnya sudah hancur.
Dalam kasus Indonesia, romantisme simbol agama juga tidak mampu mengartikulasikan problem yang riil, tidak mampu menjawab soal-soal masyarakat. Yang ada dalam romantisme justru antusiasme beragama. Sekarang ini ada kekuatan transnasional yang menjadi sumber malapetaka Indonesia. Masyarakat terpuruk dalam bidang ekonomi, dan ekonomi obatnya tidak dengan memperbanyak kiai atau dakwah, melainkan harus realistis-ekonomis.
Kita menyaksikan sekarang ini banyak sekali televisi dan radio yang menyiarkan acara keagamaan Islam. Mubalig sudah tak terhitung jumlahnya. Tapi sebenarnya ada kanker menggerogoti. Sayangnya kanker itu tidak dianggap, karena dalam agama seakan-akan semua beres dengan retorika, dengan khotbah-khotbah, tetapi tidak tahunya kondisi masyarakat ambruk dan solusinya pada ekonomi. Karenanya terhadap persoalan kanker (ekonomi) yang menggerogoti masyarakat itu, IMF dan Bank Dunia dipilih sebagai jawaban.
Problem Sekarang: SDM
Dengan berubahnya makna simbol agama, maka perlu ada radikalisasi pemahaman terhadap agama itu sendiri. Tetapi persoalannya adalah masyarakat masih feodal. Mereka, misalnya, masih menganggap pemimpinnya adalah orang-orang yang tidak dapat salah, sehingga tidak boleh dikritik. Inilah yang harus diubah. Para da’i perlu dikenalkan pada pendekatan empiris dalam melihat persoalan umat. Tidak deduktif dan utopis. Sehingga harus ada wacana ekonomisasi bagi para da’i agar berwawasan induktif dan realistis bahwa problem umat sekarang adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dengan SDM yang mumpuni diharapkan akan terjadi perubahan yang berkelanjutan dalam paradigma berpikir dan bertindak. Sehingga agendanya nanti ialah bagaimana memenej kekayaaan alam dengan baik. Dan ini membutuhkan satu wawasan ekonomi, teknologi, dan politik-bukan dalam arti politicking, tetapi dalam arti seni mengatur negara modern, manajemen potensi kebangsaan, yang sebenarnya itu adalah istilah-istilah dari Barat dan berasal dari wilayah non-agama.
Salah satu agenda penting pengembangan SDM ialah pendidikan. Lebih spesifik lagi, perlu dilakukan elaborasi kurikulum, misalnya tidak ada lagi dikotomi Islam dan non-Islam, agama dan non-agama. Misalnya lagi, belajar fiqh dimulai dengan bab ilmu (bâb al-`ilm). Kenapa? Karena ayat pertama adalah “Iqra” dan itu karena Allah menghargai akal manusia. Setelah itu bab kerja (bâb al-`amal), sebab kata “amal” (kerja) dalam bahasa Arab satu akar kata dengan “ilmu”, hanya dibalik posisi hurufnya. Berarti ilmu itu akan meaningful kalau ada implikasi praktis dalam bentuk “amal”. Demikian juga amal itu akan benar kalau ada ilmu. Jadi ilmu itu turun menyinari amal.
Terkait dengan agenda itu ialah bahwa kerangka pikir dalam merespon persoalan kehidupan ini dituangkan dalam buku yang selalu baru. Artinya, banyak buku yang harus diubah, yaitu kitab-kitab lama, karena cara pandang manusia pada dunia selalu berubah dan dipengaruhi oleh banyak hal. Jangan seperti membeli komputer yang diinstal hanya dengan WS 4, tapi semua problem ingin dapat diselesaikan dengan WS 4, tidak bisa. Persoalan sosial kemasyarakatan lebih sulit lagi, karena itu tidak dapat dipecahkan dengan cepat kecuali harus dengan mengubah programnya.
Kaji Ulang Metodologi
Memang tidak bisa diingkari adanya dua wilayah: wilayah agama yang sakral dan wilayah dunia yang profan. Tetapi dalam kenyataannya, terlebih bagi seorang Muslim, keduanya melebur menjadi satu. Pemisahan dikotomis itu hanyalah retorika. Misalnya batas antara ilmu agama dan ilmu umum, juga antara agama dan teknologi, dalam operasionalnya semuanya melebur secara fungsional. Agama dan filsafat memberikan visi dan pemikiran seputar makna hidup, sedangkan ilmu dan teknologi memberikan kemudahan bagaimana menyelenggarakan hidup agar lebih nyaman dan mudah. Disayangkan, paradigma pemikiran kita masih terbelah, dan hal ini diperkuat lagi dengan adanya dua departemen, yaitu: Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional sehingga melahirkan bayangan adanya dikotomi keilmuan dan kepribadian yang dihasilkan oleh masing-masing departemen yang juga mengelola dunia pendidikan.
Menyadari adanya kekeliruan ini maka visi dan kurikulum pendidikan serta ceramah-ceramah keagaman harus diperbaiki sehingga artikulasi dan praktek keberagamaan bisa sejalan, bahkan memberikan inspirasi dan arahan, dengan perubahan sosial yang berlangsung. Sekarang ini dirasa perlu merombak strategi pembelajaran agama. Misalnya, seperti telah kita singgung, dalam buku-buku keagamaan mestinya pembahasan mengenai ilmu lebih didahulukan sebelum membahas soal wudlu ataupun ibadah lain. Jika mengikuti kronologi turunnya ayat al-Qur’an, mestinya rukun Islam yang pertama itu mencari ilmu, baru memasuki rukun yang lain. Bukankah rukun berarti sesuatu yang prinsipil? Sedangkan mencari ilmu itu sangat prinsipil dalam pandangan al-Qur’an. Kemudian setelah haji, perlu ditambahkan lagi rukun yang lain, yaitu amal saleh, karena muara ibadah haji secara sosial adalah berbuat al-birr, yaitu amal saleh secara vertikal dan sosial.
Jadi persoalan metodologi, bukan hanya substansi dan bangunan normatifnya, dalam mempelajari Islam dan mengembangkannya, sangat mendesak untuk dikaji ulang. Sekadar contoh, dulu belajar membaca al-Qur’an dengan sistem Hijaiyah membutuhkan beberapa tahun. Itu pun sudah disebut mengaji, padahal sesungguhnya baru belajar membaca tulisan Arab. Tapi sekarang dengan metode baru, hanya dalam beberapa bulan saja anak bisa membaca al-Qur’an. Belum lagi mereka yang belajar al-Qur’an dan tafsirnya dengan bantuan komputer dan CD Rom yang ternyata jauh lebih cepat ketimbang dengan pendekatan tradisional semacam ceramah. Itu terjadi karena adanya perubahan metodologi. Oleh karenanya perlu dibedakan antara substansi dan metodologi. Jangan disamakan orang belajar bahasa Arab dengan belajar substansi agama karena di negara Arab banyak yang tahu bahasa Arab, namun tidak faham kandungan al-Qur’an. Bahwa orang menguasai bahasa Arab itu bagus, namun tidak jaminan menguasai ilmu keislaman.
Sementara ini bangsa kita masih disibukkan oleh perjuangan simbol dengan luapan emosi, karena itu yang lebih substansial tidak menjadi agenda pokok perjuangan. Kemiskinan, kesulitan pendidikan, problem kesehatan, adalah masalah-masalah riil yang terabaikan. Dengan turunnya wibawa para politisi kaum santri dan ulama yang menggejala akhir-akhir ini, maka orang mulai tidak respek dan tidak percaya pada tokoh dan lembaga agama karena dinilai tidak mampu memecahkan problem bangsa yang riil tadi. Menghadapi kenyataan ini maka agamawan harus lebih arif dalam menyikapi hal tersebut. Misalnya seorang pakar agama bicara ekonomi, maka dia harus bisa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang agamawan yang berhasil di bidang ekonomi, karena orang akan dipercaya kalau mempunyai referensi konkrit, amal yang nyata. Di Bandung, misalnya, ada koperasi pesantren, dan melibatkan orang-orang profesional dalam bidang manajemen, maka orang pun akan percaya pada konsep koperasi pesantren. Bank Muamalah juga diuji, kalau dia berhasil, orang akan percaya ada Bank Islam. Tapi kalau tidak berhasil, orang akan bertanya, untuk apa Islam-Islaman. Jadi, sekali lagi, harus ada yang konkrit. Orang sudah jenuh dengan kata-kata, dan orang juga sudah tidak mudah terbius dengan pidato agama. Orang bisa saja kagum dengan pidato KH Zainuddin MZ, tapi secara psikologis orang juga akan senang mendengarkan Srimulat karena di situ terdapat unsur hiburan.
Di samping mengandalkan retorika, seharusnya kita bisa mulai memecahkan problem riil dengan pendekatan program, skill, dan institusi. Dan ini semua harus dijadikan program jangka panjang secara berkelanjutan. Kalau program di atas berhasil mungkin akan memunculkan phobia-phobia sebagaimana masa lalu, dimana orang luar takut pada Islam. Tetapi jawabannya adalah kalau hal tersebut dirasakan rakyat maka tidak ada alasan untuk phobia. Misalnya pendidikan yang didirikan orang Katolik, orang Islam tidak bisa marah, karena nyatanya pendidikannya mengikuti kurikulum umum, hasilnya bagus, anak didiknya bisa lulus UMPTN. Sehingga tidak ada alasan marah, karena terbuka alias transparan. Amal yang baik adalah transparansi.
Sekarang banyak pendidikan yang dibangun orang Kristen. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menghalangi karena riil sumbangannya. Sebaliknya kalau orang Islam marah, mereka harus membuat pendidikan yang lebih bagus. Hal tersebut tidak terkait dengan persoalan romantis-emosional karena memang untuk menjawab persoalan yang riil.
Memang romantisme dan sejarah masa lalu diperlukan, tapi jangan sampai hal itu dijadikan sebagai tempat pelarian. Sikap romantisme juga tidak serta merta dapat langsung dihilangkan dengan tergesa-gesa, karena masyarakat adalah anak kandung sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu mengandung values serta cita-cita hidup, sehingga harus dijaga seperlunya. Bukankah dalam hidup itu ada makna, imajinasi, eskatologi. Seorang pria yang patah hati, kemudian kepadanya ditawarkan wanita yang lebih cantik, tentu hatinya tidak bisa langsung berubah, karena tidak ada hubungan kimiawi, karena di sana ada sesuatu yang non-materi, yang menggetarkan, yang membuat seseorang merasa hidup. Apalagi itu berkembang dalam setiap masyarakat secara lama dan laten, dan merupakan endapan yang terbentuk oleh habitat, konsep diri, dan cita-cita. Ketika orang bertemu dengan orang lain perilakunya juga dipengaruhi oleh konsep diri: aku ini siapa. Misalnya ketika menjabat Presiden dan ketika tidak lagi jadi Presiden akan lain lagi sikapnya. Konsep diri ini berpengaruh dalam korelasi, karena ada values yang mempengaruhi. Tetapi itu juga perlu bagi kita untuk mengatakan kepada generasi muda Islam agar memasuki wilayah-wilayah riil tanpa harus meninggalkan tradisi agama yang sudah dianut.
Etos Ketaatan Vs Etos Kreativitas
Ketika kita membicarakan ilmu pengetahuan dalam konteks agama Islam maka terasa ada hal yang hilang. Yaitu, tidak berkembangnya ilmu futurologi secara pesat. Dalam Islam yang berkembang justru ilmu eskatologis. Ini disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, ikatan masa lalu yang sangat kuat. The golden years begitu digemari, sehingga orang menjadi terus menerus merujuknya. Sementara kaki berjalan ke depan, kepala kita ingin ke belakang, sehingga perlu diimbangi; bukan pergi ke belakang dalam arti konsep waktu, tapi ke belakang dalam arti menggali substansi ajaran Islam. Karena kalau substansi tidak perlu terpenjara oleh romantisme historis.
Kedua, orang Islam lebih mempunyai etos ketaatan, bukan etos kreativitas. Ada satu persepsi dari sebagian besar orang Islam bahwa hukum Tuhan itu sudah jadi dan komplit. Kalau sudah komplit, buat apa lagi berpikir, tinggal mengikuti saja. Inilah yang menyebabkan lahirnya etos ketaatan. Karenanya dalam kenyataan orang Islam lebih suka pergi ke dukun yang kontemplatif. Alasannya, karena ketaatan tadi dapat menyelesaikan masalah. Tapi juga perlu dilihat, fenomena ketaatan adalah fenomena Islam tradisional. Apalagi fenomena itu juga merupakan sumbangan kultural dan bukan karena watak keislaman yang sesungguhnya.
Watak tersebut berasal dari dunia pesantren sehingga sering dianggap sumbernya dari Tuhan, dan Tuhan memberikan karamah pada orang-orang tertentu. Maka muncullah fenomena wali atau kiai khas. Karena itu kemudian orang datang kepada Tuhan lewat wasilah orang-orang tersebut. Hal ini berbeda dengan humanisme sekuler yang mempercayai bahwa karamah itu ada di pabrik dan pada kegiatan inovasi. Dunia maju memandang mukjizat tidak lagi terletak pada doa, melainkan pada inovasi-kreatif. Mukjizat baru di Jepang ialah menciptakan robot atau kereta api yang super cepat. Mukjizat di situ adalah produk dari riset yang empirik. Di dunia Islam mukjizat adalah sesuatu yang metafisis. Itulah yang menyebabkan persoalan teologis-epistemologisnya dilarikan ke eskatologi sehingga kemudian mengambil jarak dari dunia empiris, dan pada akhirnya berpengaruh dalam cara memandang dunia. Di dunia Islam petualangan imajinasi luar angkasa adalah lewat mukjizat Mikraj, sedang di Barat petualangan itu sesuatu yang riil, membuat pesawat ulang alik. Jadi memang berbeda sekali alam pikiran orang Muslim dan Barat ketika berbicara tentang luar angkasa.
Sekarang coba kita riset sarjana-sarjana IAIN, ilmunya tidak ada yang baru, karena yang baru adalah mengenalkan yang lama. Istilah baru sama sekali tidak dikenal. Karena Islam itu azali, shalih `alâ kulli zamân wa makân, sehingga tugas mereka hanyalah mengenalkan dan menyebarkan. Akhirnya konsep dakwah juga hanya menyebarkan ajaran, bukan menggali ilmu baru. Ibaratnya kita hanya shopping, memahami, menghapal, dan menyebarkan. Sehingga kita tidak punya fasilitas riset untuk mencipta dan berkreasi. Umat Islam tidak berusaha untuk menjadi produsen, seperti membuat pabrik, tetapi hanya diajari ber-shopping. Akibatnya, retail dealer kita kecil. Kita shopping ke masa lalu dan pada al-Qur'an yang sudah komplit.
Dalam banyak hal, mata kita kini hanya mencari referensi literer pada khazanah keislaman. Kita kurang kreatif dan apresiatif terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh pengalaman agama, kebudayaan, dan bangsa lain. Misalnya, contoh paling riil adalah, dulu naik haji dengan unta, sekarang dengan pesawat. Peristiwa tersebut sudah sangat maju dan teknikal. Sadar atau tidak wilayah yang netral itu sudah ada kemajuan.
Kita sepakat bahwa memang harus ada guncangan kultural untuk membangkitkan kesadaran ini. Selain itu tentu kita perlu mendengarkan orang-orang yang berkata bahwa Islam belum sempurna. Seperti yang dikatakan (almarhum) Prof. Harun Nasution, Islam hanya mengenalkan basic principle, selebihnya kita harus mencari sendiri. Dan banyak wilayah yang memang diserahkan kepada kita. Ayat Allah yang turun pada kita hanyalah ayat lafdziyah yang sudah berakhir pada Muhammad. Ayat al-Qur'an yang perlu banyak kita baca seharusnya perintah al-Qur'an atau ayat Allah yang berupa ayat-ayat ijtimaiyah (sosial), ayat-ayat tarikhiyah (sejarah), ayat-ayat nafsiyah (jiwa). Kita harus banyak belajar dari peristiwa kemanusiaan. Sayangnya selama ini kita belajar hanya teks yang struktural. Mungkin kita tidak serius mendengarkan al-Qur'an itu sendiri.
Sebelum mengakhiri uraian ini, tanamkanlah dalam hati dengan sungguh-sungguh bahwa al-Qur'an itu adalah masa lalu yang tidak harus selalu diapresiasi. Al-Qur'an sebagai teks sudah selesai. Karena sesungguhnya al-Qur'an itu sendiri mengusir orang yang membacanya. Al-Qur'an sebenarnya hendak mengatakan pada umatnya, “Bukan ini ayatku, aku ini hanya konsultan yang sekali-kali perlu dirujuk, tapi selebihnya jangan ke sini, pergilah ke masyarakat, lakukanlah riset.” Kita tidak mau mendengarkan usulan al-Qur'an, karenanya riset yang bernilai empiris mandeg. Akhirnya dunia eskatologis yang menyesatkan banyak berkembang di dunia Islam menggantikan empirisisme. Karena itu para agamawan hendaknya mulai menyadari betapa kajian-kajian eskatologis harus mulai ditinggalkan, sebagai gantinya harus ada seruan moral bersama agar pada waktu-waktu mendatang generasi baru kita adalah generasi yang menyeimbangkan kajian yang bersifat empiris, futurologis, etik eskatologis.[*]

keroncong- KAPTEN
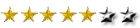
-

Age : 70
Posts : 4535
Kepercayaan : Islam
Location : di rumah saya
Join date : 09.11.11
Reputation : 67
 Similar topics
Similar topics» video yang berkaitan dengan perempuan yang ada aksi yang mengandung ilmu bela diri
» KEYWORD yang bisa terkait info yang lainya atau yang lain lagi
» muslim yang jahat bahkan yang sekelas teroris sekalipun lebih mulia daripada kafir yang baik
» tentang orang-orang yang sedang dalam keadaan miskin atau yang dalam keadaan yang tergolong kurang mampu dan hal-hal yang terkait dengan itu
» *Persiapan Mental adalah yang termasuk inti sari yang merupakan dasar yang utama ilmu rohani tentang keikhlasan tingkat tertinggi dalam taraf manusia*
» KEYWORD yang bisa terkait info yang lainya atau yang lain lagi
» muslim yang jahat bahkan yang sekelas teroris sekalipun lebih mulia daripada kafir yang baik
» tentang orang-orang yang sedang dalam keadaan miskin atau yang dalam keadaan yang tergolong kurang mampu dan hal-hal yang terkait dengan itu
» *Persiapan Mental adalah yang termasuk inti sari yang merupakan dasar yang utama ilmu rohani tentang keikhlasan tingkat tertinggi dalam taraf manusia*
Halaman 1 dari 1
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik


